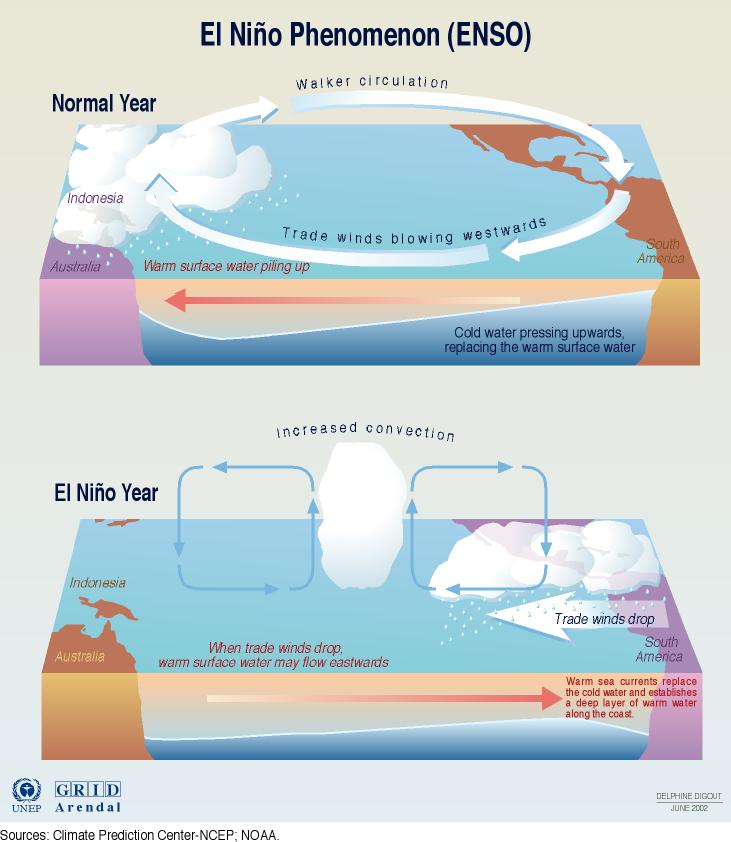MI/Seno(Dok. Pribadi)
MI/Seno(Dok. Pribadi)
SAYA besar dalam tradisi masyarakat muslim yang cenderung homogen. Namun, semenjak mengenal sejarah Tuhan-nya Karen Armstrong, Katolik yang disebut oleh Romo Magnis sebagai NU-nya Kristen di Indonesia menarik minat saya untuk memutuskan memilih konsentrasi sejarah Kristen saat program S-2. Apalagi semenjak Paus Fransiskus yang dengan wajah teduhnya menuju takhta sucinya pada 2013. Bukan karena jubah putihnya, bukan pula karena tongkat sucinya. Namun, karena caranya memimpin: tenang, sederhana, tapi juga tegas dan bermakna.
Ada adegan dalam film The Two Popes yang terus teringat--Fransiskus (saat itu masih Kardinal Bergoglio) duduk di Vatikan, makan piza bareng Paus Benediktus. Melalui adegan makan piza yang diiringi nobar World Cup, film itu memperlihatkan sisi kemanusiaan dua tokoh besar Gereja Katolik yang sering diposisikan secara ideologis berseberangan: konservatisme teologis Benediktus dan progresivisme pastoral Bergoglio.
Saya melihatnya bukan sekadar soal makanan. Itu semacam isyarat kecil, tapi kuat--bahwa di tengah perbedaan cara pandang, masih ada ruang untuk duduk bersama, untuk menyambung hati.
Gereja yang selama ini dipersepsikan formal, megah, dan penuh protokol, mendadak terasa hangat. Bukan karena dogma yang dibahas, melainkan karena manusiawinya, dua pemimpinnya. Seolah bilang ke kita semua: perbedaan itu bisa dirangkul, asal ada kemauan untuk mendengar dan saling menghormati. Kadang, jalan menuju rekonsiliasi itu, ya, cukup lewat sepiring piza.
Sebatas yang saya tahu, tidak mudah menjadi pemimpin religius di zaman sekarang. Dunia sudah berubah, batas-batas agama sering kali jadi alasan konflik, dan wibawa keagamaan pun kerap diragukan. Namun, Fransiskus--dengan gayanya yang membumi--membuktikan bahwa agama tetap bisa jadi pelita di tengah gelap. Ia bukan hanya pemimpin Katolik. Ia milik semua yang percaya bahwa kasih, dialog, dan perdamaian masih mungkin diperjuangkan. Ia bukan hanya pemimpin yang bicara dari altar tinggi, tapi yang turun, mendengar, dan memeluk.
FRANSISKUS DAN PERSAUDARAAN YANG TULUS
Fransiskus bukan orang yang suka pidato panjang soal toleransi. Namun, lihat tindakannya: dua minggu setelah jadi Paus, ia mencuci kaki narapidana--di antaranya dua muslim dan dua perempuan. Pada 2019, ia terbang ke Jazirah Arab, bertemu Imam Besar Al-Azhar, dan menandatangani Dokumen Persaudaraan Manusia. Saya ingat waktu itu, banyak media menyebut itu peristiwa langka. Namun, bagi saya, itu bukan sekadar simbol. Ini Fransiskus yang menunjukkan bahwa agama bukan soal tembok, tapi jembatan.
Saat mengunjungi Indonesia pada 2024, Fransiskus juga tak kehilangan gaya. Ia memuji semboyan Bhinneka tunggal ika. Bahkan ada momen tak terlupakan saat dia bertemu Imam Besar Masjid Istiqal: Paus mencium tangan Imam Besar Masjid Istiqlal dan dibalas dengan ciuman kening oleh Imam Besar Masjid Istiqlal kepada Paus. Adegan itu viral dan saya yakin itu bukan setting-an kamera. Itu ketulusan yang memancar dari dua pemuka agama yang percaya bahwa perbedaan bukan untuk ditakuti, tapi dirayakan. Dialog ala Fransiskus bukan basa-basi diplomatik. Ia mengajarkan bahwa iman sejati justru diuji saat kita bertemu yang berbeda.
Yang tak kalah mengesankan, selama di Jakarta, ia tak banyak bicara soal kesederhanaan. Namun, dari sikapnya kita belajar. Ia memilih naik Innova--mobil yang biasa digunakan sebagai kendaraan travel di pelosok Sumatra, bukan limosin lapis baja. Mungkin buat Fransiskus kendaraan bukan simbol. Yang penting sampai, dan bisa menyapa. Seakan-akan ia ingin bilang: saya datang bukan untuk memberikan tontonan kemewahan, melainkan untuk menjalin perdamaian.
Dialog ala Fransiskus bukan basa-basi diplomatik. Ia mengajarkan bahwa iman sejati justru diuji saat kita bertemu yang berbeda. Yang paling saya suka dari gaya dialognya: ia tidak buru-buru menasihati. Ia hadir dulu. Duduk dulu. Mendengar dulu. Lalu bicara jika sudah waktunya. Di zaman yang semua orang sibuk berteriak, Fransiskus mengajarkan kekuatan hadir dalam hening.
KETIKA AGAMA BICARA LEWAT NURANI
Fransiskus bukan politikus. Namun, ia tahu betul: suara seorang Paus bisa mengguncang dunia. Pada 2014, ia diam-diam menghubungi Obama dan Raul Castro. Hasilnya? AS dan Kuba yang dingin-dingin saja selama 50 tahun akhirnya berdamai. Lalu pada Kongres AS, ia berdiri dan bertanya: “Mengapa senjata terus dijual demi uang yang berlumuran darah?” Pernyataan itu mengundang tepuk tangan, tapi juga refleksi mendalam.
Saya lihat gaya Fransiskus itu bukan gaya berpolitik, melainkan gaya mengingatkan. Ia tak menggertak, tak menggurui. Namun, ucapannya punya daya: seperti senter kecil yang menyala di ruang gelap. Bahkan, saat bicara soal konflik Ukraina, ia tidak terjebak pada siapa salah siapa benar. Ia cuma bilang: beranilah angkat bendera putih--karena damai jauh lebih penting dari menang.
Yang menarik, dia bukan hanya bicara damai saat ada kamera. Konsistensinya terasa, bahkan ketika ucapannya tidak populer. Ia bisa saja memilih aman--diam saja soal perang atau genosida. Namun, Fransiskus justru melangkah ke tengah, dan menyuarakan nurani. Hingga sebelum wafat, ia terus berkomunikasi dengan mereka yang terzalimi di Gaza. Ia mengajak kita semua untuk jujur pada hati sendiri: apa yang benar, bukan apa yang nyaman.
INJIL YANG JALAN KAKI
Bagi Fransiskus, iman itu bukan hanya soal misa dan dogma. Ia percaya bahwa Tuhan bisa hadir lewat tindakan sederhana: mencuci kaki, memeluk pengungsi, menyapa anak kecil. Ia juga pernah berkata: “Tuhan tidak pernah lelah mengampuni. Kita saja yang sering lelah minta ampun.” Bahkan saat lututnya sakit, ia bisa bergurau: “Saya bukan tua, hanya sedikit rusak di sana-sini.”
Gaya Fransiskus itu dekat dengan yang disebut para teolog sebagai teologi praksis. Itu bukan teologi yang tinggal di menara gading. Ini teologi yang mau turun ke jalan, duduk bareng rakyat kecil, dan menyeka air mata mereka. Beberapa menyebut pendekatannya mirip dengan teologi pembebasan. Mungkin benar. Namun, saya rasa Fransiskus tak terlalu peduli soal label. Ia lebih peduli bagaimana Injil bisa hadir di dapur orang miskin, di tenda pengungsi, atau bahkan di ruang tunggu rumah sakit.
Ia lebih suka mobil kecil Fiat daripada limosin mewah. Ia bawa sendiri tas kerjanya. Ia berseloroh bahwa para uskup harus 'berbau seperti domba'--karena tugas mereka bukan hanya mengajar, tapi hadir di tengah umat. Gurauan-gurauan ringan itu bukan sekadar lucu. Mereka ialah cara Fransiskus menyampaikan teologi dalam bahasa rakyat. Ia tak bicara berat-berat, tapi setiap kata dan tindakannya menggugah.
Ensikliknya, Laudato Si’, yang membahas tentang lingkungan, juga jadi bukti. Fransiskus tidak ingin agama bicara surga saja, tapi juga bumi. Ia ajak semua orang, lintas agama, untuk menjaga rumah bersama: planet ini. Bahkan, dalam isunya soal iklim, ia tidak pakai bahasa langit. Ia pakai bahasa sehari-hari: tentang sampah, soal sungai yang tercemar, dan udara yang makin panas. Itu yang membuatnya dekat: karena ia tidak bicara dari atas mimbar, tapi dari tempat kita duduk bersama.
Ia juga sering mengingatkan soal 'budaya membuang'--budaya yang menyingkirkan yang lemah, yang tak berdaya, yang tak menguntungkan. Ia menyebut kapitalisme tak terkendali sebagai 'tirani baru'. Namun, ia juga tahu: perubahan harus dilakukan pelan-pelan. Iman, baginya, bukan dogma yang dibekukan, tapi kompas yang terus bergerak. “Tuhan itu Tuhan kejutan,” ujarnya. Maka itu, tak heran kalau dalam setiap ucapannya, kita selalu diajak siap membuka diri. Fransiskus mengingatkan: moderasi bukan berarti kehilangan prinsip, melainkan cara menjaga agar prinsip tak menjelma jadi tembok.
MENGANTAR PULANG SANG SAHABAT
Sekarang, Fransiskus sudah tiada. Dunia kehilangan sosok yang bisa menatap mata siapa pun tanpa curiga, yang bisa memimpin dengan senyum dan kesederhanaan. Saya yakin, banyak orang--termasuk yang tak pernah masuk gereja--ikut merasakan duka.
Namun, saya juga yakin: warisan Fransiskus tak akan habis. Ia tinggalkan kita dengan contoh. Bahwa menjadi religius bukan soal menghakimi, melainkan memahami. Bukan soal menang debat, melainkan merangkul dengan empati. Bahkan di dunia yang makin bising ini, kehadirannya ialah ruang sunyi yang menyegarkan.
Mungkin, seperti dalam adegan dalam The Two Popes, kita semua butuh duduk di taman. Makan piza, mengobrol jujur, dan saling mengingatkan bahwa di balik dogma dan doktrin, ada satu hal yang tak boleh hilang: cinta. Mungkin itu yang akan selalu kita kenang dari Fransiskus--bahwa di tengah dunia yang sering lupa cara mencinta, ia datang sebagai pengingat yang lembut, dan pergi sebagai sahabat yang dirindukan.
“Truth may be vital, but without love, it is unbearable,” kata film The Two Popes. Fransiskus telah menunjukkan bahwa kebenaran iman, jika disampaikan dengan cinta dan kerendahan hati, akan sampai lebih jauh.
Warisan beliau ialah pelajaran bagi kita semua bahwa dalam membangun dunia yang lebih baik, kita tak selalu butuh suara keras. Kadang cukup satu senyum, satu pelukan, atau satu kehadiran yang sungguh-sungguh. Itulah gaya Fransiskus: sederhana, tapi dalam.