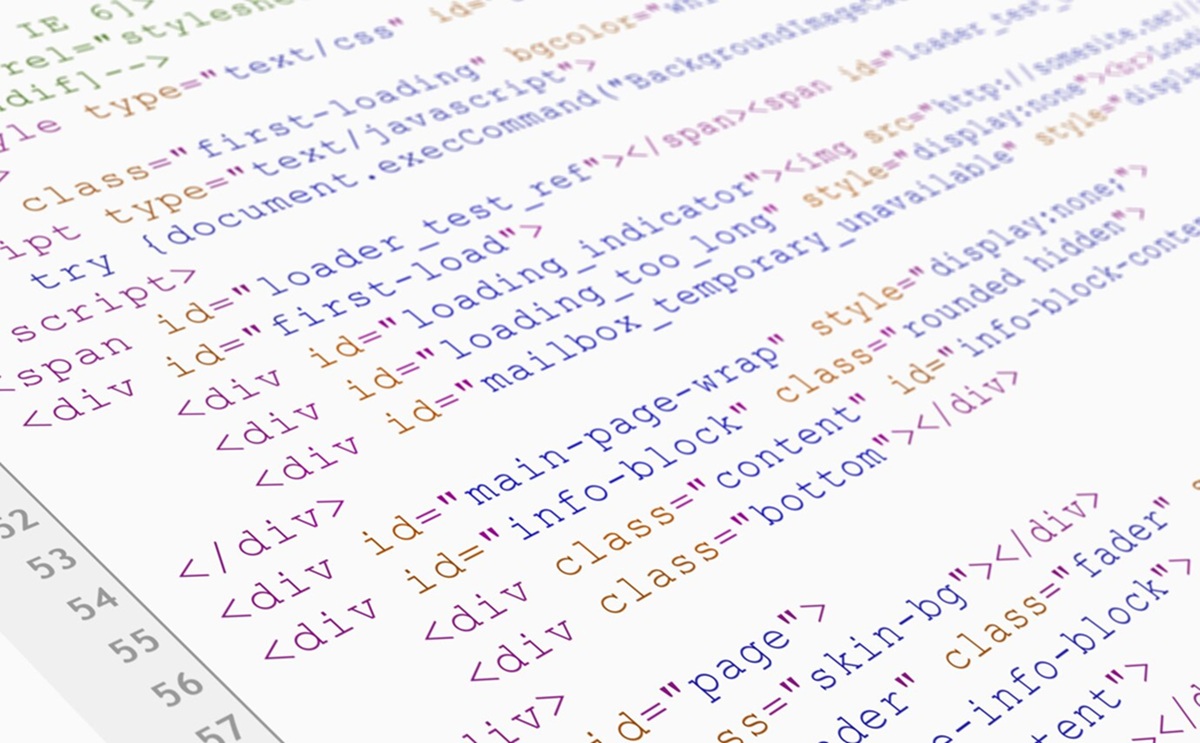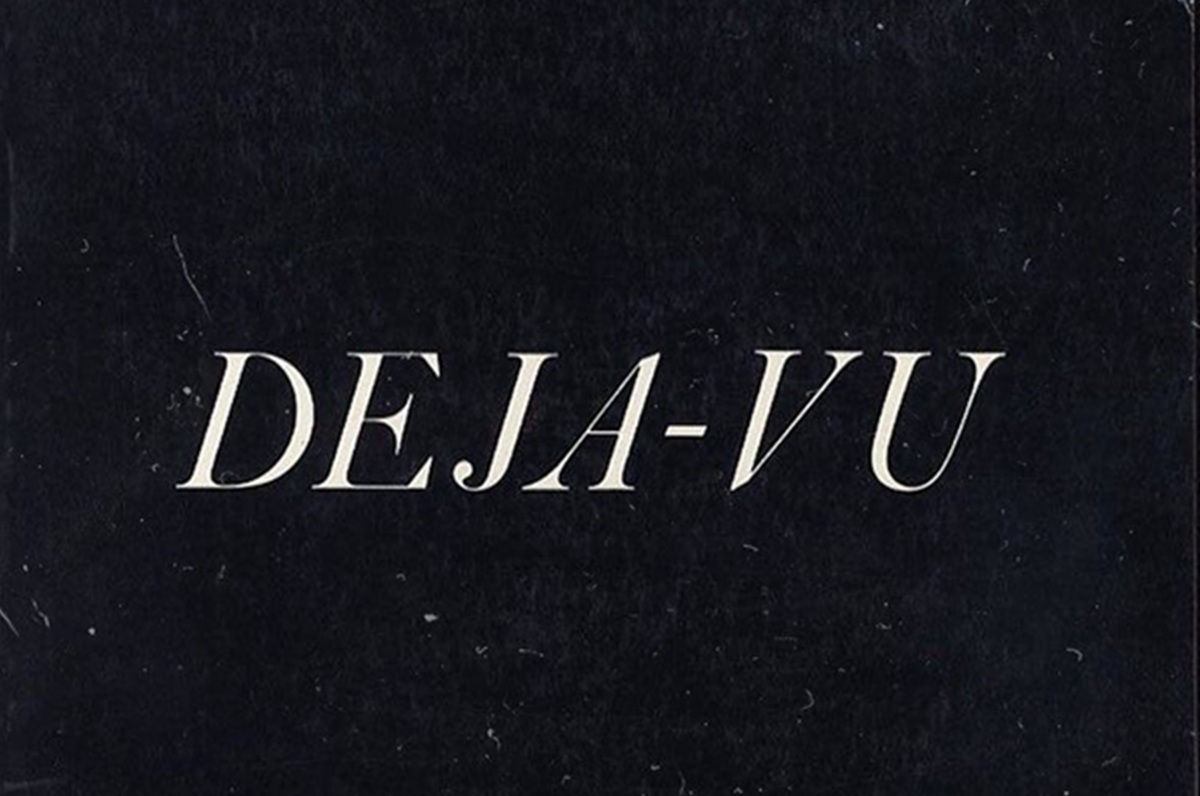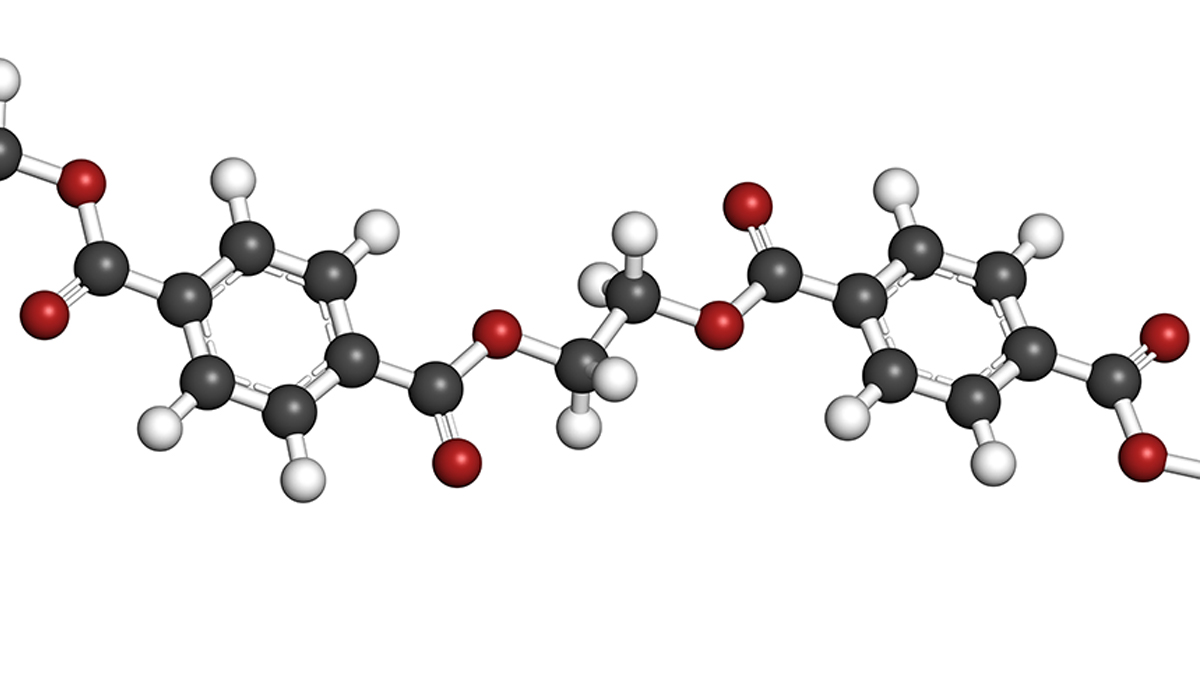Lokasi yang beberapa tahun lalu untuk eksplorasi geotermal di kawasan hutan Gunung Slamet.(MI/Lilik Darmawan)
Lokasi yang beberapa tahun lalu untuk eksplorasi geotermal di kawasan hutan Gunung Slamet.(MI/Lilik Darmawan)
TRAUMA warga Desa Karangtengah, Kecamatan Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah (Jateng), masih belum hilang ketika terjadi pencemaran air pada 2017 silam. Meski telah delapan tahun berselang, tetapi tragedi lingkungan itu benar-benar membekas dalam ingatan.
Pencemaran Sungai Prukut terjadi ketika ada eksplorasi panas bumi oleh PT Sejahtera Alam Energi (SAE). Eksplorasi untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Baturraden bermasalah besar karena berdampak pada puluhan ribu warga di sejumlah kecamatan di Banyumas.
Kini, PT SAE yang memiliki Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Panas Bumi tidak lagi terlihat aktivitasnya sejak beberapa tahun terakhir. Namun, masalah tetap saja hadir, bahkan masih terjadi sampai sekarang.
Lokasi yang dulunya hutan rimba sudah telanjur terbuka dan sekarang menyisakan infrastruktur jalan dan areal yang tak lagi ada pohon besarnya. Arealnya berada di kawasan lereng sebelah selatan yang secara administratif masuk wilayah Banyumas pada ketinggian sekitar 2.000 meter di atas permukaan laut (mdpl) dekat dengan tebing curam dan hulu Sungai Prukut.
Seorang sumber Media Indonesia menyebutkan, ada praktik penebangan liar. Ia mengetahui pada saat harus bermalam di sekitar kawasan tidak jauh dari lahan yang terbuka.
“Saya cukup terkejut sekitar jam 23.00 WIB ada suara truk yang datang melewati jalan. Kemudian, satu jam kemudian ada suara mirip senso yang berbunyi. Kegiatannya sampai kira-kira jam 03.00 WIB,” jelas sumber yang tidak mau disebutkan namanya itu.
Truk memang bisa sampai ke atas, karena infrastruktur jalan telah dibangun mulai dari kawasan perkebunan teh di Desa Pandansari, Kecamatan Paguyangan, Brebes. Ketika tahun 2017 silam, jalanan tersebut dibangun untuk pengangkutan peralatan eksplorasi.
Sumber tersebut tidak mengetahui secara persis, pohon apa saja yang ditebang dan dibawa ke mana. Namun yang pasti, sangat logis jika terjadi penebangan liar.
“Kalau akses sudah terbuka seperti ini, maka akan sangat gampang orang untuk datang. Jika berniat jahat melakukan penebangan juga mudah karena tinggal masuk ke hutan. Apalagi, memang tidak ada petugas lagi di sini,” ungkapnya.
Berdasarkan pemantauan Media Indonesia, areal yang telah terbuka kebanyakan ditumbuhi ilalang. Jalan yang telah dipadatkan dengan batu-batuan kecil ditumbuhi rumput. Ada beberapa peralatan seperti pipa pengeboran, kemudian ada bangunan yang telah terbengkalai. Telaga Dringo juga terlihat tidak terlalu banyak airnya. Di pinggiran danau yang sebelumnya ditumbuhi pepohonan besar, kini hanya tersisa rumput ilalang.
Tak hanya itu, karena ada lahan yang terbuka, sudah mulai ada tanaman tahunan seperti albasia, damar, dan pinus. Padahal, pohon seperti albasia bukanlah spesies yang biasanya tumbuh di hutan lindung. Kemungkinan besar, untuk pohon jenis kayu tahunan itu tidak muncul secara alami, melainkan sengaja ditanam. Karena aksesnya gampang sampai atas, sehingga kemudian malah dijadikan lahan.
Pegiat lingkungan dari Biodiversity Society (BS) Purwokerto Junianto yang juga warga Desa Sambirata, Kecamatan Cilongok, Banyumas, itu cukup tahu daerah yang dialihkan menjadi areal eksplorasi. Wilayahnya meliputi Telaga Dringo dan Ratamba. Dulu, sebelum terbuka, wilayahnya sangat rapat dengan pepohonan asli hutan tropis Gunung Slamet.
“Daerah yang terbuka itu sangat sulit dijangkau dari mana-mana, baik Banyumas, Brebes atau Tegal. Ekosistemnya juga unik, banyak sekali burung-burung khas. Apalagi ada Dringo, telaga alami di tengah hutan yang lebat,” katanya.
Ia menyoroti adanya kemungkinan para pemburu burung masuk secara mudah ke areal di ketinggian 2.000 mdpl, utamanya lereng barat daya. “Lokasi yang terbuka memungkinkan pemburu burung bisa lebih leluasa. Jelas saja, pengaruhnya sangat besar. Banyak burung yang sebelumnya ada di lokasi setempat, kini hilang entah ke mana,” kata dia.
Direktur Biodiversity Society Purwokerto Nur R Fajar mengatakan, terbukanya akses hingga ketinggian di atas 2.000 mdpl tentu menjadi masalah besar bagi ekosistem.
“Bayangkan saja, dari bawah sampai ketinggian 2.000 mdpl dapat diakses dengan sepeda motor atau mobil. Padahal, dulunya hutan lebat dan sangat sulit ditembus. Jelas saja, ini akan berpengaruh terhadap ekosistem. Apalagi, masyarakat juga dengan mudah dapat masuk,” ujarnya pada Rabu (9/4).
Menurutnya, konsekuensi logis dari terbukanya akses, maka akan meningkatkan illegal logging dan perburuan, misalnya burung atau primata yang bernilai ekonomi.
“Sebetulnya di areal tempat eksplorasi geotermal itu merupakan jantung hutan Gunung Slamet. Di situ ada ekosistem langka, karena ada telaga di ketinggian 2.000 mdpl. Di sekitar telaga tumbuh pepohonan yang lebat. Tetapi sekarang telah terbuka, bahkan telaga mengalami pendangkalan dan kering,” katanya.
Ia menduga, wilayah setempat juga menjadi habitat fauna unik dan khas Gunung Slamet. Misalnya katak pohon yang merupakan spesies baru di gunung tertinggi di Jateng itu yakni Zhangixalus faritsalhadi.
“Belum lagi dengan spesies burung khas seperti Teledekan Gunung (Cyornis banyumas) dan Poksai Kuda (Garrulax rufifrons). Kedua burung tersebut sudah tidak ditemukan lagi di sekitar kawasan yang kini tersebut tersebut,” kata Fajar.
Dampak Pencemaran
PT SAE memegang Izin Panas Bumi (IPB) berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1557 k/30/MEM/2010, yang kemudian diperbarui menjadi Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 4577k/30/MEM/2015. Luasannya mencapai 24.660 hektare (ha). Lokasi proyek meliputi lima kabupaten yaitu Banyumas, Purbalingga, Tegal, Brebes, dan Pemalang dengan potensi cadangan panas bumi sebesar 175 Megawatt (MW). Luasan hutan yang telah dibabat untuk aktivitas eksplorasi panas bumi luasnya mencapai kisaran 40 hektare (ha).
Pada saat dilaksanakan eksplorasi pada 2016-2017, bencana datang. Air sungai yang memiliki hulu di lereng Gunung Slamet yakni Sungai Prukut menjadi salah satu yang terdampak. Air yang jernih tiba-tiba berubah menjadi kecokelatan. Setelah dilakukan pemantauan, ternyata air berubah menjadi keruh akibat membawa sedimentasi dari areal hutan yang dibuka PT SAE.
Padahal, keberadaan Sungai Prukut sangat vital bagi puluhan ribu warga yang berada di desa-desa Kecamatan Cilongok, Banyumas. Di Dusun Karanggondang, Desa Sambirata, misalnya, warga tidak lagi mendapatkan suplai listrik dari pembangkit tenaga listrik mikrohidro (PLTMH).
“Agak aneh, geotermal yang akan menghasilkan listrik membuat PLTMH tidak berfungsi. Pemicunya adalah air yang mengandung sedimen sehingga berdampak pada turbin. Waktu itu, PLTMH tidak berfungsi karena airnya bercampur lumpur,” ungkap Junianto, warga setempat.
Tak hanya Sambirata, ada enam desa lainnya yang ikut terdampak yakni Karangtengah, Panembangan, Kalisari, Pernasidi, Cikidang, dan Karanglo. Di Desa Karangtengah, warga merasakan dampak sumber air bersih dan sumber pengairan bagi kolam-kolam miliknya.
“Sampai sekarang, kami masih trauma kejadian itu. Air yang biasanya mengalir bersih, tiba-tiba berubah menjadi cokelat dan tidak dapat menjadi sumber air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” kata Sutrisno, warga Desa Karangtengah.
Selain itu, lanjutnya, warga mengalami kerugian lantaran tidak dapat membudidayakan ikan. Sebagian besar kehilangan mata pencaharian sebagai pembudi daya.
“Kami kehilangan pendapatan dari budi daya ikan. Selain itu, kebutuhan air bersih yang sebelumnya hanya mengalirkan dari mata air, tidak bisa lagi. Kami harus membeli air bersih. Meski kemudian ada bantuan air bersih. Yang membuat kami trauma, itu berlangsung tahunan antara 2016-2017. Kalau sekarang ditanya, apakah warga sepakat PLTP dilanjutkan atau tidak, jelas kami menyatakan tidak,” tegasnya.
Di sektor wisata, air terjun Cipendok yang berada di desa setempat juga ditutup akibat warnanya menjadi kecokelatan. Selama berbulan-bulan, Curug Cipendok kehilangan pengunjung karena air Sungai Prukut yang masuk ke air terjun membawa sedimentasi dari pembukaan areal eksplorasi PLTP Baturraden.
Cerita trauma juga dirasakan oleh warga yang mempunyai usaha pembuatan tempe di Desa Kalisari. Kepala Desa Kalisari Hendar Susanto mengatakan desa setempat yang menjadi sentra perajin tempe juga terdampak.
“Warga kesulitan mengakses air bersih untuk proses pembuatan tempe pada saat air sungai berwarna coklat,” katanya.
Waktu itu, lanjut Kades, tidak hanya perajin tempe saja melainkan para pembudi daya ikan yang terdampak air bercampur lumpur.
“Setelah tidak ada aktivitas di atas (PLTP Baturraden), pencemaran sungai yang berwarna coklat sudah tidak ada lagi. Warga di Kalisari bisa melanjutkan usaha budi daya ikan dan pembuatan tempe,” ujarnya.
Gerakan Bersama
Dampak pencemaran akibat eksplorasi PLTP Baturraden tidak hanya mendapat perhatian dari warga, melainkan juga masyarakat sipil. Mereka bergerak dengan mengatasnamakan Save Slamet. Anggotanya bisa dari siapa saja dan profesi apapun. Inti gerakannya tegas, menolak PLTP Baturraden.
“Paling utama gerakan masyarakat sipil yang tergabung dalam Save Slamet adalah menolak PLTP Baturraden,” tegas pegiat Save Slamet, Hendy yang ditemui pada Rabu (9/4).
Ia menegaskan bahwa hutan Gunung Slamet harus diselamatkan dari perusakan karena digunakan untuk PLTP Baturraden.
“Ketika terjadi pencemaran air, kami bersama warga melakukan penolakan dengan menggelar demo berkali-kali. Kami tidak mau hutan Gunung Slamet rusak. Selain itu, mendampingi warga yang terkena dampak pencemaran,” katanya.
Hendy mengatakan hingga sekarang sikap Save Slamet tetap tegas yakni melakukan penolakan terhadap PLTP Baturraden. Apalagi, mereka masih mengkhawatirkan dampak yang muncul jika tidak segera ada rehabilitasi lahan dan revegetasi hutan.
“Dari pemantauan yang kami lakukan, lahan terbuka cukup luas. Ada aliran-aliran air bendungan-bendungan kecil untuk menahan air masuk ke hulu Sungai Prukut. Yang jadi masalah adalah, apakah bendungan kecil-kecil semacam itu akan mampu selamanya menahan. Kalau tidak ada bahaya pencemaran lumpur bahkan banjir bandang,” ujarnya.
Senada dengan Hendy, aktivis Komunitas Peduli Slamet Purwokerto Dani Armanto juga mengungkap kekhawatirannya. Peristiwa tercemarnya Sungai Prukut saat eksplorasi beberapa tahun lalu sebetulnya menjadi peringatan serius terjadinya kerusakan lingkungan.
“PLTP Baturraden dapat memicu bencana. Dari identifikasi risiko di lereng sisi timur, ada bendungan-bendungan atau dam kecil. Kalau suatu waktu jebol, akan dapat memicu adanya banjir bandang. Ini yang betul-betul perlu diperhatikan,” katanya.
Kondisi hutan Gunung Slamet, lanjutnya, sebetulnya sangat rentan. Adanya kawasan yang terbuka dan tidak segera ada rehabilitasi, maka akan memunculkan banyak persoalan. Bisa saja, kemudian ditanami dengan pohon invasif yang tidak sesuai pohon rimba sebelumnya. Apalagi jika ditanam pohon kayu tahunan.
“Maka kami berharap, seluruh elemen masyarakat tetap harus peka dan memantau perkembangan PLTP Baturraden. Konsolidasi diperlukan karena ada ancaman bagi masyarakat,”kata dia.
Dani juga menyinggung keberadaan PLTP Baturraden saat ini, karena ketidakjelasan mengenai proyek tersebut. Tetapi, dia menegaskan bahwa sikapnya pasti menolak PLTP.
“Ketidakjelasan itu terlihat dari kawasan yang dulunya menjadi wilayah eksplorasi, tidak lagi ada portal maupun penjaganya. Dan tentu saja sangat rentan karena bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab masuk ke hutan dan melakukan penebangan liar,” ujarnya.
Informasi lainnya yang dia terima adalah adanya pergantian kepemilikan saham dalam PT SAE. Sepengetahuan Dani, investor PT SAE yang sebelumnya dari Jerman, kini sudah menjual sahamnya. Yang terakhir muncul nama PT Nirwan Suci Abadi. “Nah, dengan bergantinya kepemilikan itu, semakin tidak diketahui bagaimana nasib PLTP Baturraden ke depannya,” kata dia.
Kepala Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Banyumas Dedy Noerhasan yang dikonfirmasi menyatakan belum dapat informasi mengenai PLTP Baturraden sejak gagalnya eksplorasi.
“Pemkab tahu adanya eksplorasi, namun kemudian tidak ada kabar sampai sekarang. Saya sudah cek juga ke teman-teman lain. Jawabannya sama, mereka juga tidak tahu kabarnya,” jelas dia.
Secara terpisah, Kepala Seksi (Kasi) Energi Cabang Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Jawa Tengah wilayah Slamet Selatan Saptono Purwo Pranggoro juga tidak mengetahui persis kabar PLTP Baturraden.
“Saya dengar kabar terakhir sudah lama, kisaran tahun 2021. Waktu itu, ada informasi dari PT SAE mengenai eksplorasi yang bakal dilanjutkan. Karena gagal di Banyumas, maka akan geser ke wilayah Brebes. Tentu saja, sesuai dengan WKP-nya. Setelah itu, saya tidak mendengar lagi,” ungkapnya.
Siapa Bertanggung Jawab?
Setidaknya ada areal hutan telah dibabat untuk eksplorasi dengan luasan sekitar 40 ha. Para aktivis lingkungan meminta kejelasan mengapa setelah gagalnya eksplorasi tidak ada upaya penghutanan kembali.
Administratur Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyumas Timur Mochamad Risqon mengatakan pihaknya berjanji akan menindaklanjuti informasi mengenai bekas areal eksplorasi yang dibiarkan begitu saja. “Terima kasih informasinya, kami akan tanyakan kelanjutannya,” ungkap Risqon.
Dia mengatakan areal yang terbuka tersebut sebagian masuk ke wilayah KPH Banyumas Timur dan sebagian lainnya KPH Pekalongan Barat. “Saya sudah cek PPKH (Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan) yang izinnya untuk eksplorasi panas bumi telah habis tahun 2023 lalu. Tetapi sampai sekarang belum ada perpanjangan,” ujarnya.
Media Indonesia juga telah melakukan konfirmasi terkait pembangunan PLTP Baturraden dengan mengirimkan surel resmi ke Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, tetapi hingga berita ini diturunkan belum ada jawaban.
Kajian Dampak Lingkungan
Sementara pakar hukum lingkungan Universitas Wijaya Kusuma (Unwiku) Purwokerto Elly Kristanti Purwendah mengatakan bahwa sebetulnya proyek geotermal atau panas bumi menjadi bagian penting bagi pemerintah untuk mendorong energi terbarukan. Namun, yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah apakah proses eksplorasi sudah memenuhi ketentuan yang berlaku atau belum.
“Yang jadi pertanyaan adalah apakah proses awal melalui kajian yang cukup dan tidak menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan. Jika nantinya akan dilanjutkan, diperlukan kajian yang komprehensif dengan melibatkan berbagai stakeholders yang ada dengan konsep pentaheliks,” katanya.
Namun sebaliknya, kalau proyek PLTP berhenti, tentu saja harus ada yang bertanggungjawab untuk menyelesaikan persoalan lingkungan. Dalam konteks ini adalah perusahaan yang mendapat konsesi dan pemerintah. “Tanggung jawab yang diemban adalah mengembalikan ke kondisi semula sebelum ada eksplorasi PLTP Baturraden,” tegasnya.
Jika masyarakat merasa bahwa ada kerugian lingkungan akibat eksplorasi tersebut, warga dapat mengajukan gugatan. Dalam konteks hukum lingkungan, gugatannya bukanlah ganti rugi melainkan pengembalian kondisi lingkungan.
“Dalam hukum lingkungan ada prosedur hukum yang disebut Citizen Lawsuit (CLS) atau hak gugat warga. Dalam beberapa perkara lingkungan, putusan CLS beberapa kali memberikan dampak perbaikan bagi tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam,” jelasnya.
Dia mencontohkan, CLS Pencemaran Udara Jakarta memiliki kaitan sangat erat dengan hak atas lingkungan hidup sebagai hak asasi. Dalam kasus ini, salah satu dalil yang diajukan oleh penggugat adalah pelanggaran HAM yang muncul dari kegagalan tergugat yakni pemerintah untuk memenuhi kewajibannya terkait lingkungan hidup berupa pencemaran udara.
“Saya kira prosedur ini dapat ditempuh kalau memang warga merasa ada kerugian lingkungan akibat adanya eksplorasi yang kini belum jelas mau dilanjutkan ada tidak. Masyarakat dapat menuntut adanya pemulihan lingkungan yang dinilai rusak,” tandas Elly. (LD/E-4)