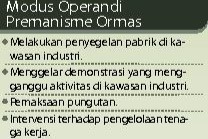(Dokpri)
(Dokpri)
SEJAK Jorge Mario Bergoglio berdiri di balkon Basilika Santo Petrus pada malam tanggal 13 Maret 2013 dan hanya menyapa dengan sapaan sederhana, "Buonasera," dunia tahu bahwa arah baru Gereja Katolik sedang dimulai. Tak perlu banyak kata atau simbolisme megah. Pilihannya untuk tidak mengenakan jubah merah papal yang biasanya dikenakan oleh para pendahulunya adalah sinyal awal: Gereja harus kembali menjadi milik orang kecil.
Sepuluh tahun lebih berlalu sejak malam itu. Hari ini, dunia mengenalnya sebagai Paus Fransiskus, seorang pemimpin spiritual global yang telah dengan tekun memposisikan diri bukan di atas umat, melainkan di tengah mereka, terutama mereka yang terpinggirkan.
Gereja untuk kaum miskin
Paus Fransiskus membangun kembali imajinasi kolektif tentang apa itu Gereja: bukan institusi kekuasaan, tetapi komunitas pelayanan. Dalam banyak kesempatan, ia menyuarakan impian akan sebuah "Gereja yang miskin dan untuk orang miskin." Kalimat ini bukan retorika. Ia wujudkan melalui langkah kaki yang merendah: mengunjungi pengungsi di Lampedusa, memeluk penderitaan di Lesbos, hingga tinggal di rumah tamu sederhana alih-alih istana apostolik.
Kunjungan ke Pulau Lampedusa pada 2013 menjadi contoh nyata. Di sana, ia tidak hanya meratap atas ratusan pengungsi yang tewas di Laut Mediterania, tetapi juga mengecam 'globalisasi ketidakpedulian'—sebuah istilah yang menjadi frasa moral bagi dunia modern yang mulai kehilangan empati.
Di Lesbos, Yunani, ia tidak hanya memberi penghiburan bagi pengungsi Suriah. Ia melakukan tindakan revolusioner dengan membawa dua belas pengungsi kembali ke Vatikan. Bukan sebagai tamu, melainkan sebagai keluarga.
Kesederhanaan yang menggugah nurani
Ketika para pemimpin dunia berlomba menunjukkan kekuasaan lewat kemewahan, Paus Fransiskus justru menanggalkan simbolisme itu. Ia tinggal di kamar sederhana, berjalan kaki dalam kompleks Vatikan, berbicara langsung kepada para pekerja, dan bahkan dikenal menggunakan mobil tua seperti Renault 4.
Tindakan-tindakan ini, meskipun tampak kecil, justru menjadi teguran moral bagi dunia yang semakin materialistis bahwa kesucian sejati lahir dari kesederhanaan, bukan kemewahan.
Lebih dari sekadar aksi karitatif, kasih Paus Fransiskus pada kaum papa berakar pada visi keadilan sosial. Ia menjadi suara keras terhadap sistem ekonomi yang menciptakan ketimpangan. Dalam ensiklik Laudato Si’ (2015), ia menyampaikan pesan profetik: kerusakan lingkungan dan kemiskinan saling terkait. Sistem ekonomi yang merusak bumi adalah sistem yang sama yang menindas manusia.
Di bawah kepemimpinannya, Vatikan membentuk program nyata seperti pusat layanan kesehatan bagi tunawisma di sekitar Basilika Santo Petrus, menyediakan mandi, potong rambut, hingga pengobatan. Ia menciptakan Hari Kaum Miskin Sedunia agar Gereja tidak sekadar berdoa, tetapi turun tangan membantu mereka yang dilupakan dunia.
Warisan seorang gembala
Warisan Paus Fransiskus tidak akan diukur dari jumlah ensiklik yang ia tulis atau jumlah kunjungan pastoral yang ia lakukan. Warisannya adalah kesaksian hidup. Ia tidak hanya berbicara tentang Kristus—ia berusaha hidup seperti Kristus: membasuh kaki mereka yang kotor, menyapa yang tersisih, dan memanggil mereka saudara.
Di tengah dunia yang semakin gersang secara moral, sosok seperti Paus Fransiskus menjadi lentera nurani. Ketika banyak pemimpin dunia sibuk berdebat dari ruang-ruang mewah, ia justru berlutut di depan penderitaan, mengangkat yang kecil, dan memanggil semua untuk kembali pada kasih sejati.
Sebagaimana tertulis dalam Matius 25:40, "Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara-Ku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk Aku."
Jika sejarah nanti menoleh ke belakang dan mencatat jejaknya, Paus Fransiskus tak hanya akan dikenang karena kotbahnya yang menggugah. Ia akan dikenang karena bagaimana ia memilih untuk hidup. Dan dunia akan mengenangnya selamanya sebagai: Paus Kaum Papa.