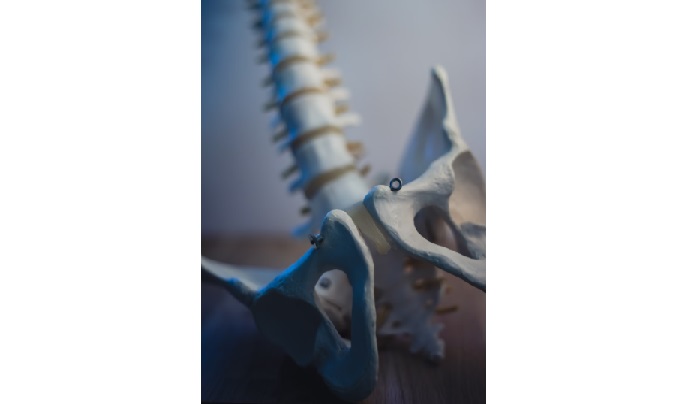Dr. H. Muhammad Bahrul Ilmie, S.Ag. M.Hum, Dosen IAINU Kebumen(Doc pribadi)
Dr. H. Muhammad Bahrul Ilmie, S.Ag. M.Hum, Dosen IAINU Kebumen(Doc pribadi)
BELAKANGAN ini, semakin ramai pembicaraan terkait Permohonan Pengujian Undang- Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 keMahkamah Konstitusi (MK) oleh sebagian kecil organisasi masyarakat, dalam hal ini merasa memiliki alas hak (kewenangan) yang diberikan oleh hukum obyektif, bahkan merasa mewakili masyarakat luas.
Sejak awal masuknya permohonan, sudah dapat diduga, akan hadir rentitan dari permohonan tersebut dengan amicus curiae sebagai bentuk tekanan yang akan mempengaruhi hasil dari aksi sekaligus intervensi terhadap kasus yang sedang disidangkan, karena dibuat dan diposisikan pada isu kepentingan umum, kebebasan sipil yang diperdebatkan bahkan pada putusan hakim nantinya akan berdampak luas terhadap hak-hak masyarakat.
Dan ini sungguh akan menarik banyak pihak, terutama Lembaga Amil Zakat (LAZ) kecil masyarakat, masih tahap perkembangan yang seolah-olah LAZ adalah korban dari politik hukum negara melalui pengaturannya, meskipun data lapangan telah pada perputaran pengeloaan dana zakat (pengumpulan dan pendistribusian) menunjukkan lebih besar pada LAZ dari pada BAZNAS. Sementara LAZ yang dikelola ormas Islam Indonesia terbesar seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sangat luas wawasannya dan berpandangan obyektif.
UU Pengelolaan Zakat, meski sudah mengalami revisi yang kedua, namun bukan berarti eksistensinya telah sempurna, tanpa masalah dan memuaskan semua pihak, sehingga saat ini kembali masuk daftar program legislasi nasional sebagai Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029 yang disiapkan oleh DPR-RI dengan urutan ke-18 (delapanbelas).
UU Pengelolaan Zakat sebagai hukum positif yang dibentuk melalui proses politik yang dibuat dalam rangka melaksanakan konstitusi, yang memberi dasar sekaligus juga bermuatan "norma abstrak" pada filsafat kenegaraan. UU sebagai dokumen atau naskah hukum yang mesti dijalankan sekaligus ditegakkan adalah gagasan yang disepakati oleh lembaga legislatif (DPR) dan eksikutif (Presiden) sebagai jelmaan politik hukum (kehendak negara) guna mencapai sasaran yang dikehendakinya.
Sejak awal setiap UU, sebelum menjadi naskah politik seringkali melalui tahapan naskah akademik. Para perancang sangat menyadari bahwa peraturan perundangan terkait dengan zakat hanya mengatur hal yang bersifat manajemen pengelolaan, tidak mengatur hal yang bersifat hukum abadinya sebagaimana sudah ditegaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan kemudian diperjelas oleh Nabi-Nya Muhammad SAW dalam ucapan, perbuatan dan ketetapannya.
Berbagai gagasan hukum dalam peraturan manajemen pengelolaan zakat, dapat dicermati bahkan dipelajari secara mendalam pada prosesnya ketika berupa naskah politik, para anggota fraksi komisi VIII sangat luar biasa, terutama fraksi-fraksi nasionalis seperti GERINDRA, DEMOKRAT bahkan PDIP sangat mewarnai dengan masing-masing argumentasinya, meski mereka semua sangat menyadari apa saja yang disepakati tertulis dalam naskah tidak selalu dapat diterima sama atau dengan baik oleh setiap orang anggota masyarakat, terlebih makna yang disampaikan bukan dalam kata atau simbol melainkan berada dalam pikiran perancang politik, bagaimana cermatnya makna yang ada dapat dialihkan kepada masyarakat, begitu halnya sejauhmana kecermatan pembaca menginterpretasikan kata-kata dalam peraraturan perundangan.
Zakat telah dipahami dan dimodifikasi sedemikian rupa sebagai salah satu filantropi (derma sosial) Islam, kemudian dihubungkan dengan pembangunan manusia (human development), baik pada konteks beragama maupun bernegara. Pada semua dimensi yang terkandung dalam ajaran zakat seperti nilai privat-publik, vertikal-horizontal, serta ukhrawi- duniawi, bila secara komprehensif dapat diaktualisasikan dengan baik dan benar.
Pelaksanaan hukum Islam, terutama terkait zakat di Indonesia dalam sejarahnya, telah mengalami gangguan sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda hingga pasca kemerdekaan. Zakat mengalami masa kebangkitan setelah pasca reformasi, ditandai adanya pertemuan kehendak berwujud kesadaran baru negara dan didukung oleh para intelektual muslim untuk mengoptimalkan potensi zakat guna menopang pencapaian tujuan bernegara, yaitu membangun kesejahteraan (welfare state).
Indonesia, benar bukan negara Islam tapi adalah tipikal negara bangsa (nation state) atau kebangsaan. Berdasarkan konstitusinya, UUD 1945 dan hasil amandemennya Indonesia menganut prinsip negara hukum (rechtsstaat atau ther rule of law) atau berdasarkan atas hukum, yang juga menganut konsepsi (ajaran) kedaulatan Tuhan, kedaulatan negara, kedaulatan rakyat dan sekaligus kedaulatan hukum.
Bila ditelisik secara mendalam pada sejarahnya, harta (dana) zakat telah dijadikan oleh Nabi SAW sebagai poros dan sumber keuangan atau pendanaan "negara Islam Madinah", karena zakat sebagai sumbangan wajib dari orang-orang muslim, di samping sumbangan lainnya (seperti jizyah atau pajak) sebagai pendapatan negara, dan kesemuanya disimpan pada Bayt al-mal (Perbendaharaan Umum, the Publik Treasury).
Artinya negara sebagai "amilin" memiliki kewenangan atau otoritas penuh atas tata kelola zakat, hal ini sebagaimana sejak zaman Nabi SAW, diteruskan masa kekhalifahan hingga negara-negara Islam, bahkan negara bangsa modern, dan sistem tersebut hingga sekarang tetap eksis, artinya tetap sesuai dengan kontekstual masa kini, dan eksistensinya tidak terlepas oleh logika "wahyu" atau syari'ah, bahwa satu-satunya yang memiliki alas hak terhadap pengelolaan zakat adalah negara, bukan masyarakat.
Dan itulah Missi kemanusiaan Islam melalui Q.S. at-Taubah (9) ayat (60), yang mentargetkan kepada 8 (delapan) kelompok sasaran, 1 (satu) kelompok sebagai amil, yaitu negara atau penguasa dan 7 (tujuh) kelompok yaitu fakir, miskin, mu'allaf, riqab, gharim. fi sabilillah dan ibn sabil sebagai hal yang mesti mendapat perhatian.
Pengelolaan zakat sebagaimana bunyi Pasal 3 UU Nomor 23 Tahun 2011, Pengelolaan zakat adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Inilah tujuan kehendak negara melalui fraksi-fraksi Komisi VIII DPR-RI.
Berangkat dari kewenangan negara atas pengelolaan zakat, karena negara memiliki sistem manajemen dan sumber daya (alat) yang baik, maka sangat beralasan jika konsep pengelolaan atau manajemen zakat menekankan pada empat kegiatan pokok, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan zakat.
Kewajiban zakat itu sejalan dengan kewajiban pajak, sehingga kewenangan negara dengan berbagai kewajibannya juga telah mempertegas eksistensinya sebagai pemilik atas hak publik yang mutlak (absolut) sebagaimana hak penarikan pajak atas masyarakatnya.
Guna memenuhi tujuannya, pengelolaan zakat yang dibebankan pada BAZNAS sebagai lembaga non-struktural negara sebagaimana hal-hal terkait hukum Islam dan umatnya: BAZNAS dalam kontrol negara dan masyarakatnya, dan UPZ serta LAZ masyarakat dihadirkan sebagai mitra kerjanya, yang diharapkan juga mengembangkan sistem pengelolaan zakat yang modern dan profesional, menghimpun dan mengelola dana zakat secara efektif dan efisien, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat, hingga dapat mengembangkan program- program pemberdayaan ekonomi mustahik, yang kesemuanya adalah untuk pencapaian tujuan bernegara.
Pada pihak masyarakat muslim (muzakki) diharapkan akan terjadi peningkatan kesadaran dan kepatuhan terhadap ajaran Islam untuk mengeluarkan sebagian harta miliknya (zakat). Melalui zakat terbangun kualitas hidup masyarakat (mustahik), hadirnya kualitas hidup akan berdampak pada kehidupan masyarakat yang lebih harmonis dan berkeadilan sosial dan ekonomi.
Besar dan luasnya tugas dan wewenang negara yang diberikan pada BAZNAS, kemudian ada pemahaman bahwa zakat tidak sesuai dengan konsep konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang mencerminkan tidak sesuai dengan kebebasan beragama, seolah BAZNAS adalah lembaga superbody bahkan superioritas yang memutilasi hak masyarakat untuk mengelola zakat di Indonesia.
Anggapan ini, dapat diduga karena ketidakpahaman sistem hukum Islam modern yang diintegrasikan dalam sistem hukum nasional, yang padanya tidak terlepas oleh logika "wahyu" yang bersifat suci, absolut, mutlak, abadi dan sakral.
Konteks ini, ada baiknya dipahami lagi untuk kemudian tidak menuju pada kepentingan kapitalisme, konglomerasi zakat dan keadilan bagi rata. Bahkan Pasal 5, 6, dan 7 UU terlebih pengelolaan zakat telah dipahami seolah-olah bermuatan tidak adil karena membatasi hak-hak individu umat Islam untuk mengelola zakat, dikarenakan tidak sesuai dengan hak Individu.
BAZNAS dianggap sebagai lembaga superbody dan kosep ini tidak sesuai dengan nilai-nilai syari'ah sekaligus melanggar konstitusi. Hal yang harus dipahami bahwa UU No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan terbentuknya BAZNAS sangat sesuai dengan kehendak dan nilai yang terkandung dalam bunyi Pasal 29 UUD 1945 bahwa kebebasan menjalani nilai-nilai agama yang dianut. (Adv)