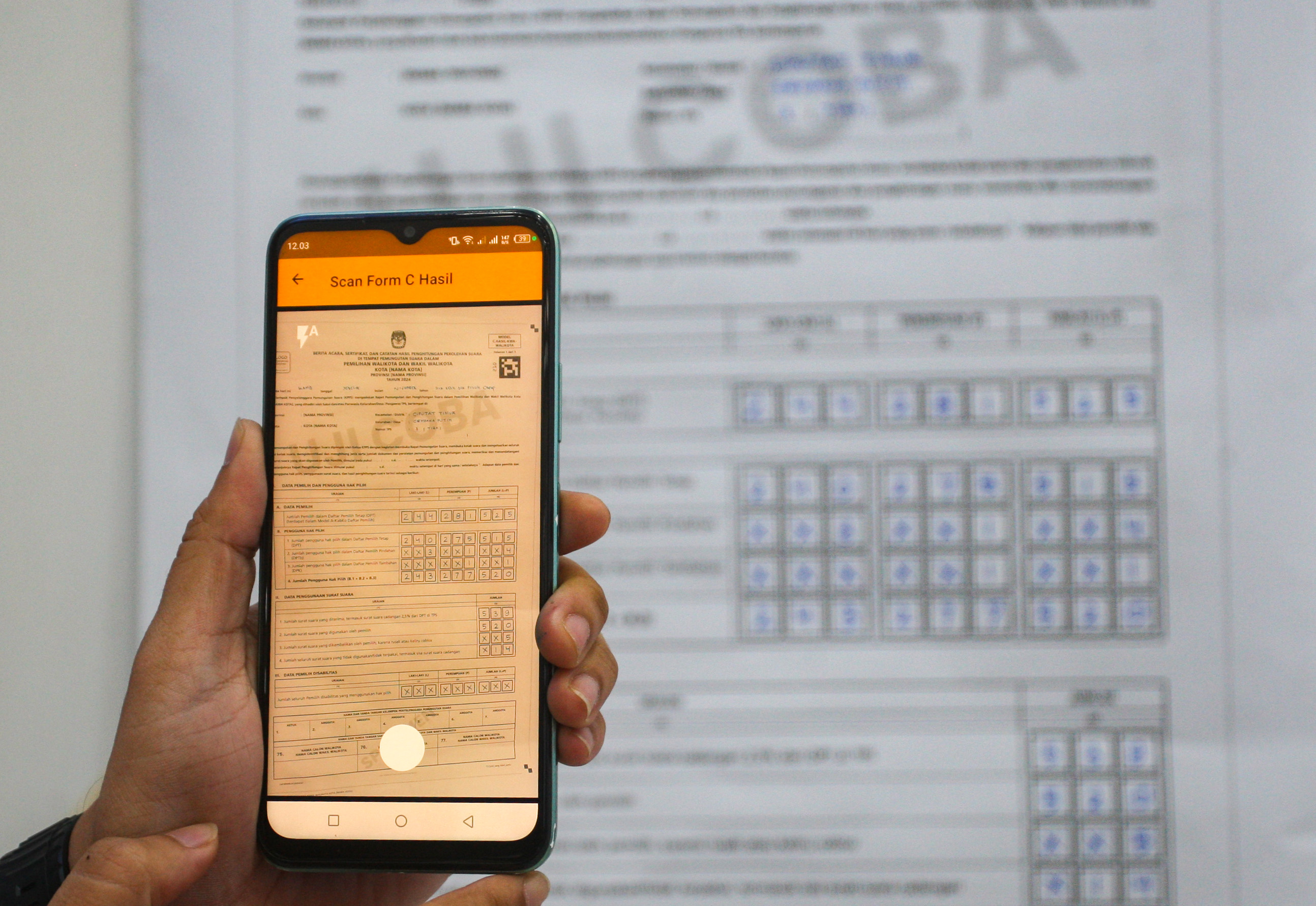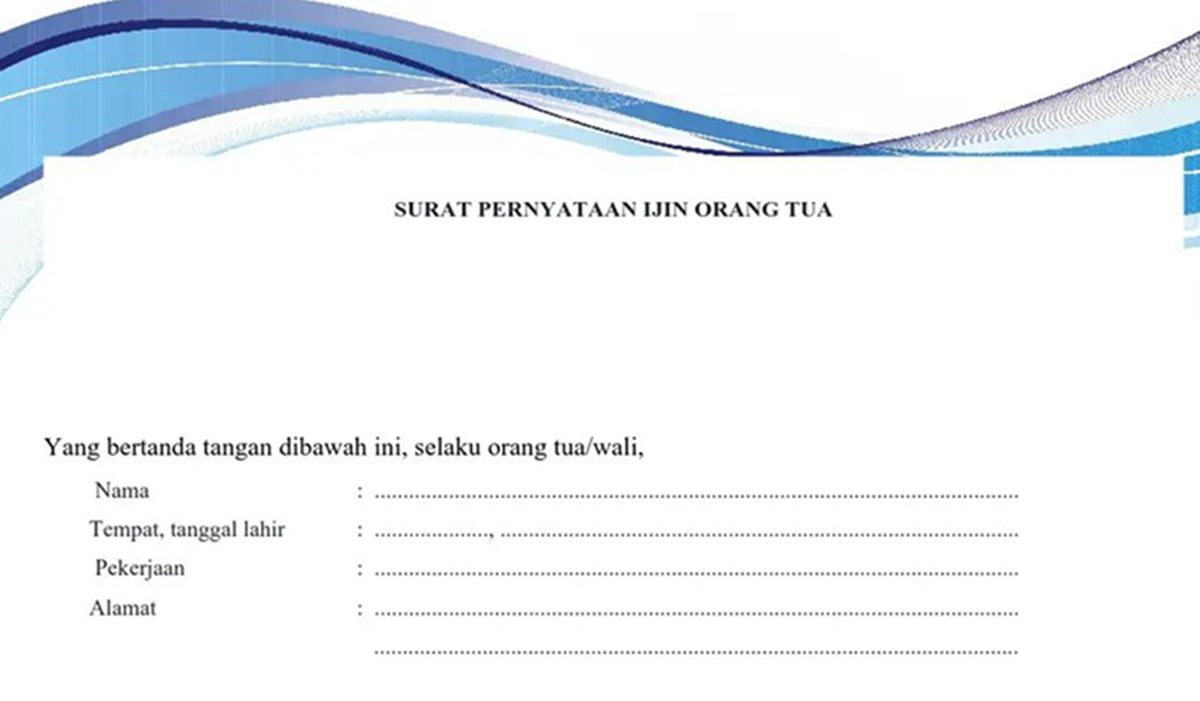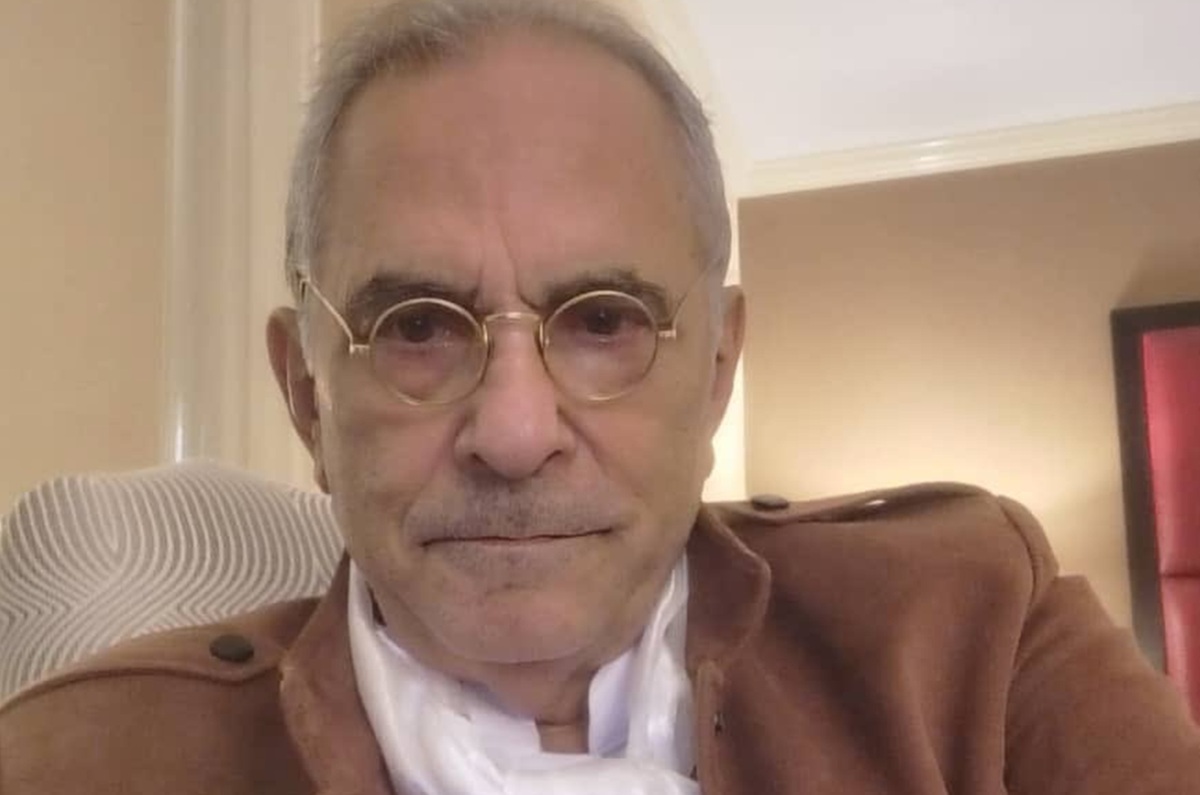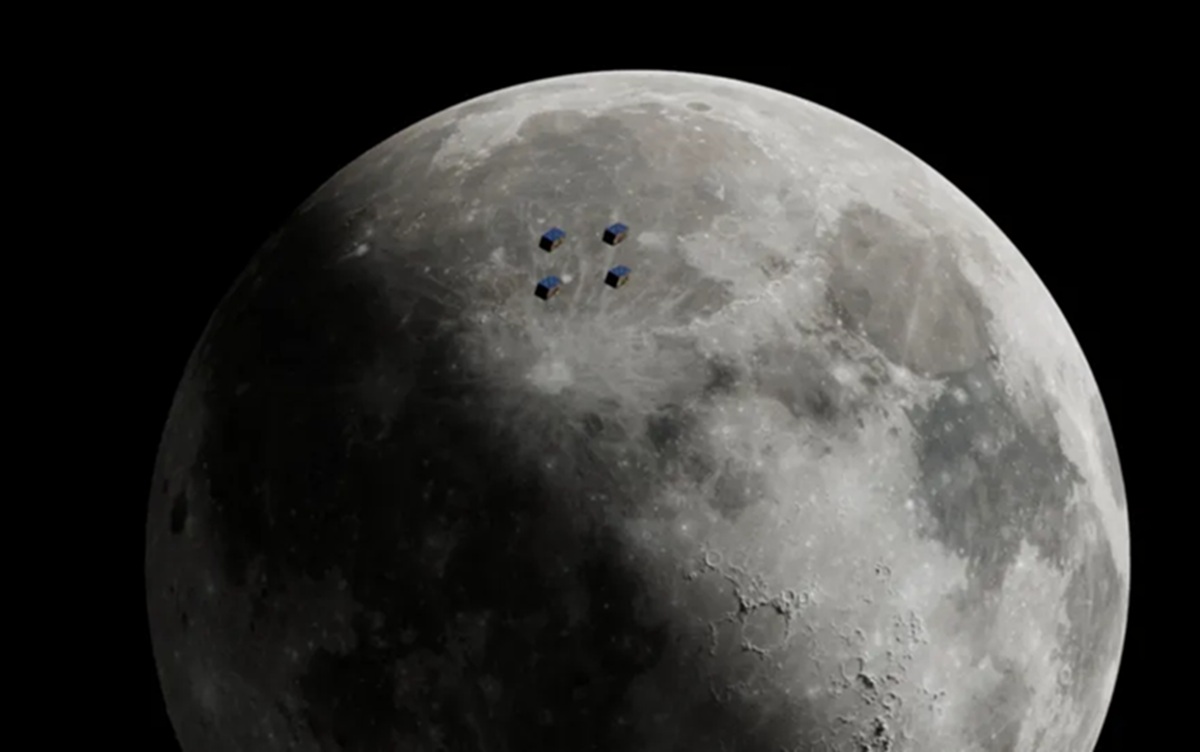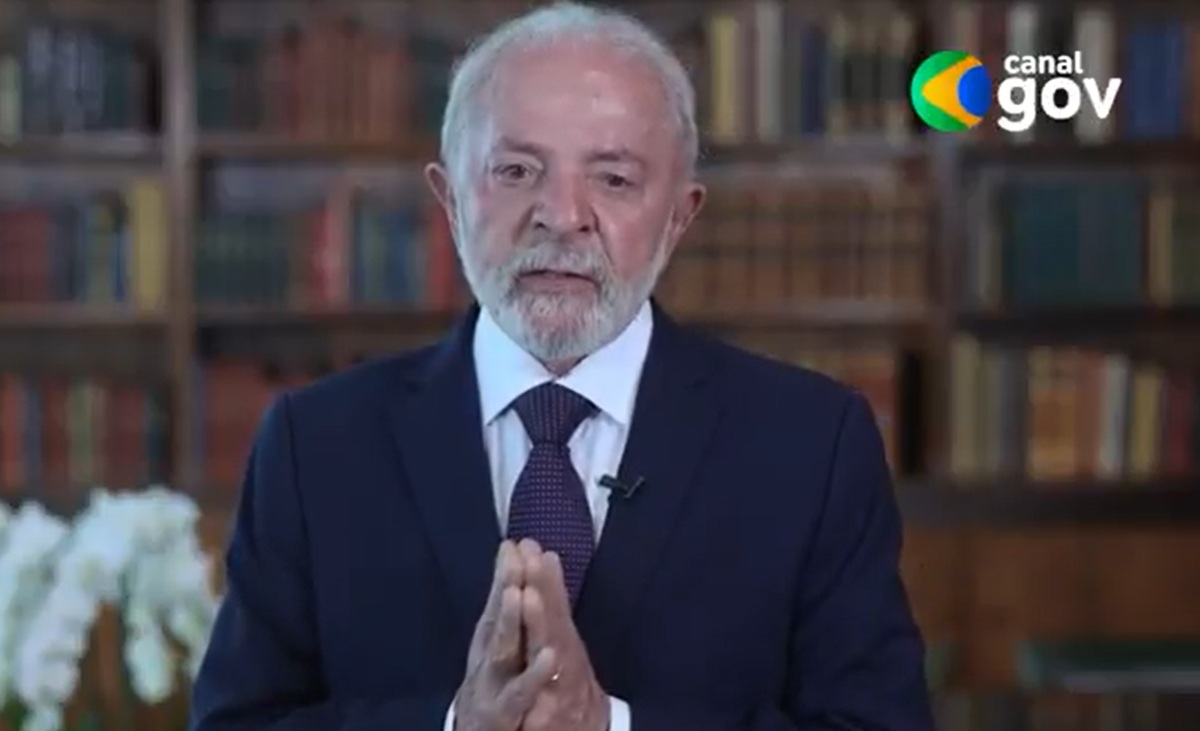(Dok. Lab 45)
(Dok. Lab 45)
DI sudut-sudut ingatan kolektif bangsa ini, setiap 21 April masih terpatri kuat sosok Raden Ajeng Kartini. Ia bukanlah sekadar nama dalam buku sejarah, melainkan juga bara api emansipasi yang menyala-nyala. Surat-suratnya ialah jendela jiwa seorang perempuan yang mendambakan kesetaraan, pendidikan, dan kebebasan bagi kaumnya.
Namun, lebih dari sekadar romantisme masa lalu, warisan Kartini hari ini justru terasa begitu mendesak, relevan, bahkan getir ketika kita menelisik belantara patriarki yang masih mencengkeram perempuan Indonesia di abad ke-21 ini.
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
Kekerasan terhadap perempuan, alih-alih menjadi narasi usang, justru menjelma menjadi epidemi sunyi yang merusak kemanusiaan. Dari ranah domestik hingga ruang publik, perempuan terus menjadi korban kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi. Statistik kekerasan yang dirilis oleh Komisi Nasional (Komnas) Perempuan hanyalah representasi kecil dari trauma mendalam yang dialami jutaan perempuan yang hak asasinya dirampas dan tubuhnya diobjektifikasi oleh budaya patriarki yang permisif.
Ironisnya, di tengah hiruk pikuk pembangunan, tubuh perempuan sering kali menjadi medan pertempuran ideologi, komoditas seksual, dan pelengkap statistik pembangunan yang mengabaikan pengalaman subjektif mereka.
Minimnya pelibatan perempuan dalam pembangunan dan pemerintahan juga menjadi tragedi laten yang menghambat kemajuan bangsa. Suara dan perspektif perempuan, yang mewakili separuh populasi, terpinggirkan dalam pengambilan keputusan. Lihatlah representasi jumlah perempuan di berbagai lembaga, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif masih minim sekali.
Ruang kekuasaan didominasi narasi maskulin yang kerap abai terhadap isu-isu spesifik perempuan, dari kebijakan kesehatan reproduksi, perlindungan terhadap kekerasan seksual, penurunan angka kematian ibu dan anak, pemberdayaan ekonomi mikro perempuan, hingga representasi yang adil dalam lembaga publik.
Partisipasi politik perempuan bukan hanya soal angka, melainkan juga tentang menghadirkan kebijaksanaan, keadilan, dan perspektif holistik dalam tata kelola negara. Tanpa keterlibatan aktif perempuan, melalui pengetahuan dan pengalaman mereka yang berbeda dan unik, pembangunan akan pincang dan cita-cita masyarakat yang adil akan sulit terwujud, seperti hari ini bahkan isu kebijakan afirmasi perempuan atau kuota Perempuan mulai ditanggapi dengan sinis dan dingin.
Dalam konteks global, gerakan perempuan telah mencapai kemajuan signifikan. Namun, sebagaimana dianalisis oleh Susan Faludi dalam bukunya Backlash: The Undeclared War Against American Women (2006), kemajuan perempuan sering kali memicu gelombang balik resistensi yang kuat. Faludi memaparkan bagaimana media, budaya populer, dan wacana politik secara halus atau terang-terangan mereduksi pencapaian perempuan, menanamkan kembali ideologi patriarki dan menyalahkan perempuan atas kesulitan yang mereka alami.
Fenomena backlash itu tidak terbatas pada Amerika Serikat, tetapi juga terlihat di berbagai negara, termasuk Indonesia, dan mewujud dalam berbagai bentuk. Pertama, revitalisasi stereotip gender. Meskipun perempuan telah memasuki berbagai bidang pekerjaan dan pendidikan, stereotip tradisional tentang peran perempuan sebagai ibu rumah tangga dan pengurus domestik sering kali dihidupkan kembali.
Media dan budaya populer dapat memainkan peran dalam memperkuat stereotip ini, membatasi aspirasi perempuan dan meremehkan kontribusi mereka di luar ranah domestik. Misalnya, narasi yang berlebihan tentang ‘kodrat wanita’ atau idealisasi peran ibu tunggal yang ‘kuat’, tapi terbebani secara tidak adil dapat menjadi bentuk backlash.
Kedua, politisasi tubuh perempuan. Tubuh perempuan sering kali menjadi fokus perdebatan politik dan ideologis, terutama terkait dengan isu-isu seperti kesehatan reproduksi, aborsi, dan pakaian. Pembatasan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi atau upaya untuk mengatur cara berpakaian perempuan ialah contoh bagaimana tubuh perempuan dijadikan medan pertempuran ideologi, merampas otonomi mereka atas diri sendiri.
Di beberapa negara, termasuk wacana konservatif di Indonesia, regulasi ketat terkait dengan moralitas dan peran gender sering kali menargetkan tubuh dan seksualitas perempuan. Masih suburnya berbagai peraturan bias gender yang mengontrol sikap dan tubuh Perempuan di beberapa daerah.
Ketiga, meremehkan pencapaian perempuan. Ketika perempuan mencapai posisi kepemimpinan atau meraih kesuksesan dalam bidang yang didominasi laki-laki, sering kali muncul upaya untuk meremehkan pencapaian mereka atau mengatribusikannya pada faktor lain selain kemampuan dan kerja keras mereka. Misalnya, komentar seksis atau anggapan bahwa keberhasilan perempuan hanya karena ‘kuota’ atau ‘keberuntungan’ ialah manifestasi dari backlash.
Keempat, peningkatan kekerasan berbasis gender: ironisnya, kemajuan perempuan dalam ruang publik terkadang diiringi oleh peningkatan kekerasan berbasis gender, baik secara fisik maupun daring. Hal itu dapat dilihat sebagai upaya untuk ‘menghukum’ perempuan yang melanggar batas-batas tradisional dan mempertahankan dominasi laki-laki melalui ketakutan dan intimidasi. Data Komnas Perempuan di Indonesia secara konsisten menunjukkan tingginya angka kekerasan terhadap perempuan, baik di ranah domestik maupun publik, yang mengindikasikan adanya resistensi terhadap emansipasi. Kekerasan yang terjadi akhir-akhir ini yang dimuat oleh berbagai media menunjukkan indikasi meningkatnya kekerasan terhadap perempuan baik pelecehan maupun pembunuhan.
Kelima, erosi kebijakan pro perempuan. Di beberapa negara, tekanan politik dan sosial dapat menyebabkan erosi kebijakankebijakan yang bertujuan meningkatkan kesetaraan gender. Misalnya, penundaan atau pembatalan rancangan undang-undang yang melindungi hak-hak perempuan atau pemotongan anggaran untuk program-program pemberdayaan perempuan ialah contoh konkret dari backlash dalam ranah kebijakan. Di Indonesia, Rancangan Undang-Undang RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) tidak kunjung diterbitkan kendati sudah dua dekade diperbincangkan. Padahal, RUU inilah jantung pekerja domestik yang sebagian besar dihuni oleh perempuan.
Senada dengan Faludi, Naomi Wolf melalui analisisnya yang tajam dalam The Beauty Myth: How Images of Beauty Are Used Against Women (1990) membongkar mitos-mitos patriarki yang tersembunyi di balik norma sosial. Ia mengajak kita untuk melihat bagaimana konstruksi sosial tentang kecantikan, seksualitas, dan peran gender membatasi potensi perempuan dan melanggengkan ketidaksetaraan.
Dalam semangat Wolf, kita perlu mempertanyakan secara radikal narasi-narasi dominan yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Konstruksi patriarki yang merasionalisasi kekerasan, membatasi partisipasi, dan membungkam suara perempuan harus dibongkar. Misalnya, standar kecantikan yang tidak realistis yang dipromosikan oleh media dapat dilihat sebagai alat patriarki untuk mengalihkan perhatian perempuan dari isu-isu politik dan sosial yang lebih penting sekaligus menciptakan rasa tidak aman dan ketergantungan pada industri yang mengomersialkan kecantikan.
PANGGILAN ABADI UNTUK TERUS BERJUANG
Warisan Kartini bukanlah sekadar romantisme kebaya dan surat-surat usang masa lalu, melainkan panggilan abadi untuk terus berjuang demi emansipasi perempuan dan relasi gender yang setara. Di tengah maraknya kekerasan, minimnya representasi, dan gelombang balik resistensi yang nyata, semangat Kartini harus terus menyala dalam diri setiap individu yang mendambakan keadilan. Kita tidak bisa lagi berpuas diri dengan capaian-capaian semu. Kita harus berani menyelisik akar permasalahan, menantang norma-norma patriarki yang merugikan, dan menciptakan ruang yang aman dan setara bagi seluruh perempuan Indonesia.
Perjuangan Kartini belum usai. Bara emansipasi yang ia nyalakan penting untuk terus kita kobarkan, menjadi suluh penerang di tengah belantara patriarki kontemporer. Itu bukan hanya tugas perempuan, melainkan juga tanggung jawab kolektif seluruh bangsa untuk mewujudkan cita-cita luhur kemerdekaan yang sesungguhnya: kemerdekaan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.
Saatnya bagi perempuan untuk tidak lagi menjadi objek, tetapi subjek aktif dalam pembangunan bangsa dengan suara yang didengar, hak yang dihormati, dan tubuh yang aman dari segala bentuk kekerasan. Kartini telah memulai, kini giliran kita untuk menuntaskannya.