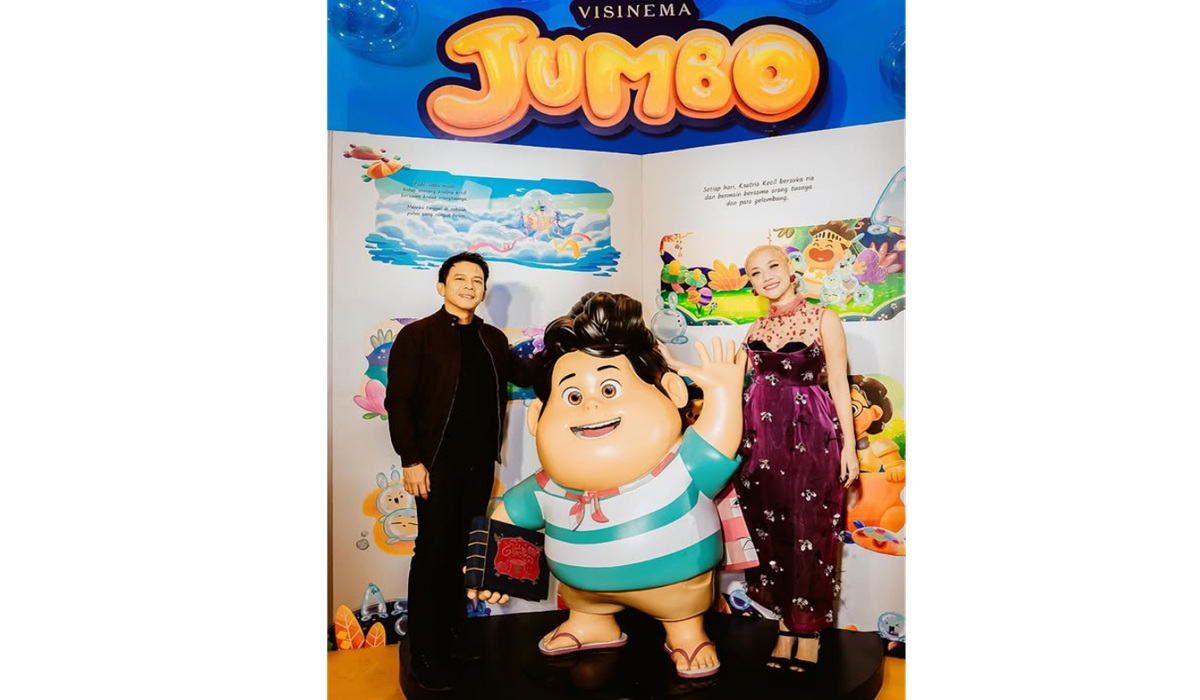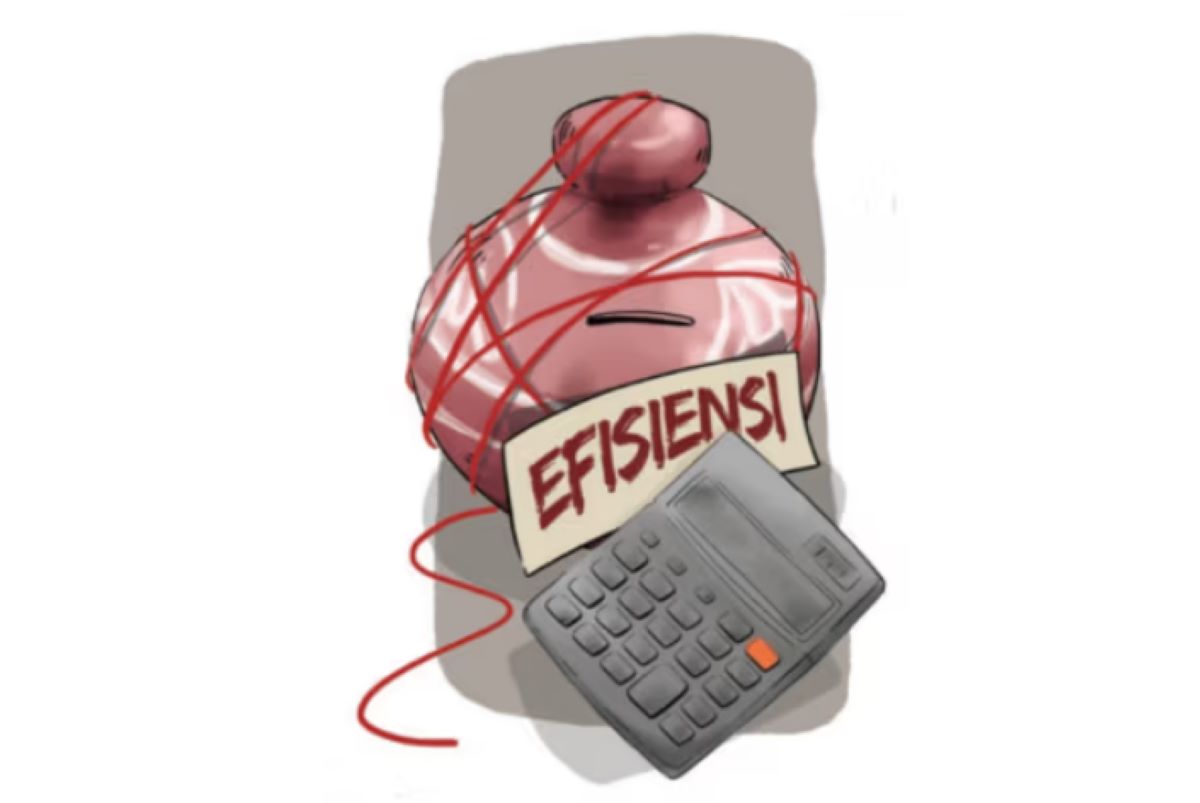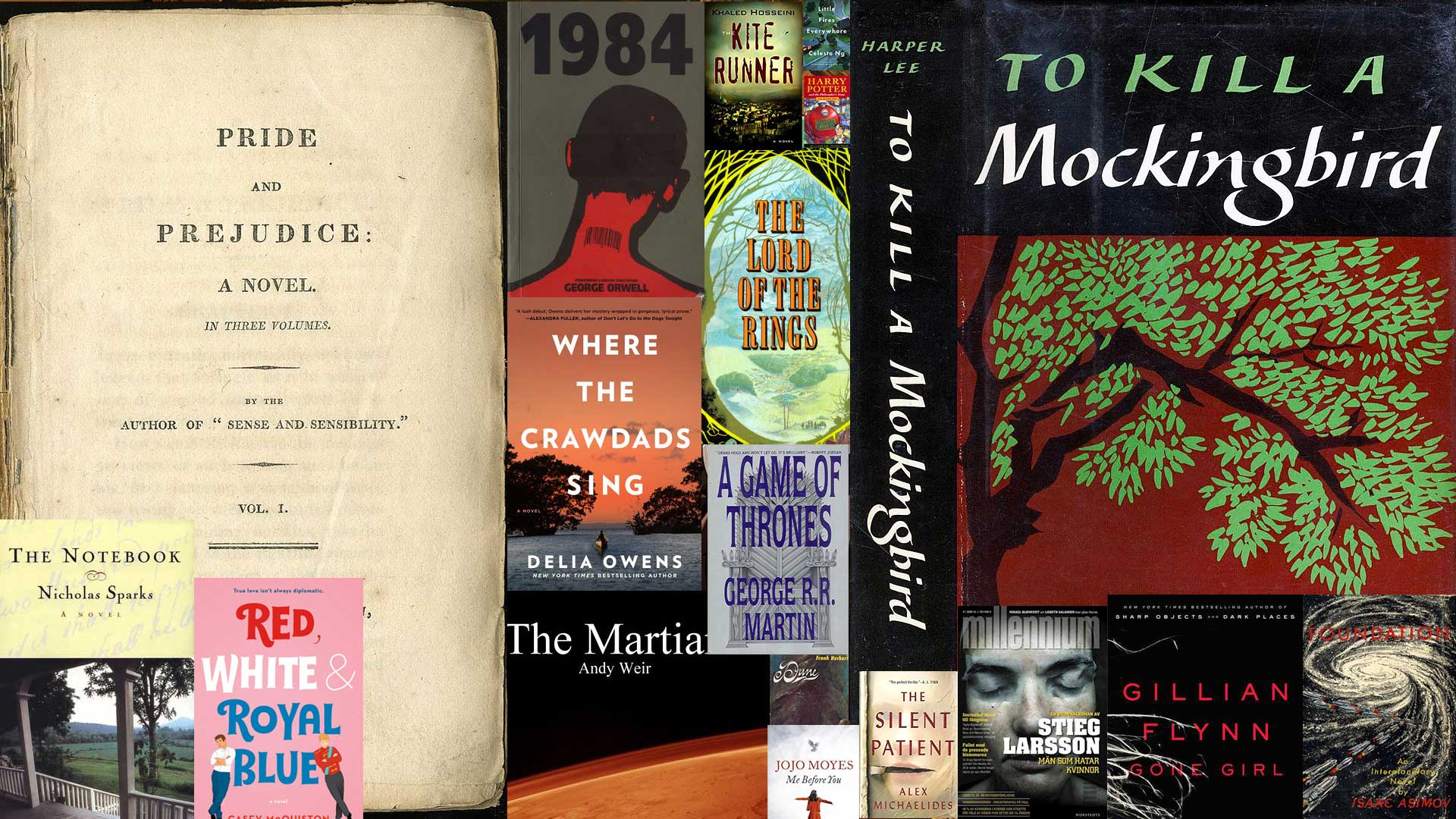Imam Khomaeni Hayatullah.(DOK PRIBADI)
Imam Khomaeni Hayatullah.(DOK PRIBADI)
Hari Pendidikan Nasional setiap 2 Mei seharusnya menjadi momentum refleksi akbar: sudah sejauh mana pendidikan Indonesia membentuk manusia seutuhnya?
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengangkat tema “Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu Untuk Semua”, disertai logo tiga sosok dan sebuah bintang yang menyiratkan pesan bahwa pendidikan ialah upaya kolektif, inklusif, dan penuh semangat untuk mencapai bintang – simbol tertinggi dari ilmu pengetahuan, karakter, dan kemajuan bangsa. Dari logo dan tema ini, kolektif dan inklusif atau semesta dan semua, menjadi sorotan dalam pendidikan Indonesia. Sebuah gagasan mulia yang jika terwujud akan memajukan pendidikan Indonesia.
Hardiknas kembali hadir di tengah janji-janji besar Asta Cita yang menjanjikan revolusi pendidikan menuju Indonesia emas. Namun, justru di saat inilah masyarakat perlu mengajukan pertanyaan penting: mengapa negara memilih membangun Sekolah Unggulan Garuda atau Sekolah rakyat, sementara ribuan sekolah “biasa” masih menghadapi krisis dasar—dari guru yang digaji tak layak hingga sarana yang menyedihkan?
Program hasil terbaik cepat terbaik yang beririsan dengan kegiatan pendidikan, peserta didik ataupun pendidik ialah Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil, Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi, Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, dan tenaga kesehatan), TNI/POLRI, dan pejabat negara. Dari ketiga irisan ini, yang sudah jelas terlaksana ialah program Makan Bergizi Gratis (MBG), sementara wacana sekolah unggulan ditambah sekolah rakyat menjadi program yang malah dikerjakan oleh kementerian lain, bukan oleh kemdikdasmen. Kemendiktisaintek dan Kementerian sosial memang menyatakan akan melakukan koordinasi penuh dengan kemendikdasmen terkait sekolah unggulan garuda maupun sekolah rakyat, namun apakah kolaborasi akan berhasil, ataukah malah akan menjadi sekolah khusus seperti sekolah kedinasan tiap Kementerian yang sudah ada di Tingkat perguruan tinggi.
Niat hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai, peribahasa yang mewakili kekhawatiran public menyikapi adanya sekolah berasrama ini.sekolah rakyat dengan kurikulum fleksibel yang bersifat personal? Pun sekolah unggulan, walau sudah sering dipromosikan oleh Ibu Stella Wamendiktisaintek akan menggunakan kurikulum internasional, mengapa ada perbedaan diantara kedua sekolah ini dan sekolah biasa?A pakah keduanya akan menjadi lembaga elite baru, seperti halnya sekolah kedinasan atau program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) di masa lalu? Apakah ini tidak akan mengulang kembali kekeliruan dengan menciptakan eksklusivitas dalam sistem pendidikan yang seharusnya merata?
Niat baik ingin mencipatkan sekolah yang dapat menghasilkan lulusan terbaik untuk melanjutkan Pendidikan di perguruan tinggi terbaik di dunia, serta memutus mata rantai kemiskinan menjadi tujuan dua sekolah ini didirikan, namun belum dilaksanakan saja public sudah menyangsikan program ini. belum lagi adanya rencana keduanya merupakan sekolah asrama (ada juga yang non-asrama), akan membuat implementasi kedua program ini menjadi tanda tanya.
Pemerintah kini mengusung program Sekolah Unggulan Garuda dan Sekolah Rakyat. Sekolah ini sekilas menawarkan solusi: menjaring siswa berprestasi tinggi dan membantu anak-anak miskin ekstrem. Namun jika dilihat lebih dalam, program ini berpotensi memperbesar ketimpangan sosial. Mereka yang berada di tengah—baik secara ekonomi maupun intelektual—seringkali terpinggirkan. Tidak miskin cukup untuk mendapat bantuan, tidak cemerlang cukup untuk meraih keistimewaan. Kelas menengah ialah fondasi stabilitas bangsa, namun dalam sistem hari ini, menjadi di tengah justru terasa menjadi paling berat: terhimpit biaya, terpinggirkan peluang, terlupakan dalam kebijakan. Maka, apakah masih relevan memaksakan program dua sekolah ini.
Sayangnya, kenyataan di lapangan memperlihatkan bahwa banyak cita-cita luhur itu masih tersandung oleh realitas pahit. Kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di berbagai perguruan tinggi negeri membuat akses pendidikan tinggi terasa makin jauh bagi rakyat kebanyakan. Tragedi keracunan massal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengingatkan kita bahwa bahkan hak dasar anak untuk belajar dalam keamanan pun belum sepenuhnya terjamin. Keterlambatan pembayaran gaji guru honorer pun mencederai prinsip keadilan, serta permasalahan Pendidikan di wilayah 3T yang tidak kunjung selesai.
Artinya, jalur pendidikan menuju mobilitas sosial sejak awal sudah tidak setara. Anak-anak dari wilayah pinggiran, khususnya 3T sudah tertinggal langkah bahkan sebelum ikut perlombaan. Banyak hal pokok yang belum dipenuhi oleh negara melalui pemerintah, anehnya malah ada ide akrobatik baru untuk mengambil jalan pintas. Alih-alih memberikan pendidikan murah untuk perguruan tinggi, walaupun ini masih kebutuhan tertierari, pemerintah getol mempersiapkan segelintir orang untuk mengejar universitas terbaik dunia. Alih-alih memberikan kualitas pendidikan merata, pemerintah malah mengambil yang kelompok miskin desil 1 & 2 untuk diselamatkan.
Dari uraian ini, ada satu kelompok sebenarnya yang selalu dilupakan, dinestapakan mungkin. Kelompok menengah. Mereka yang tidak terlalu pintar dan tidak terlalu kaya, tidak terlalu bodoh dan tidak terlalu miskin. Mereka akan tetap berada di sekolah biasa, yang akan pendidikannya itu-itu saja.
Maka pendidikan gagal menjadi alat mobilitas sosial. Mereka hidup dalam stagnasi: tidak jatuh, tapi juga tidak bisa naik.
Kedua sekolah ini dikhawatirkan memunculkan elitisme pendidikan, yang mana yang paling disorot ialah mereka yang paling cemerlang dalam akademis dan paling meralarat dalam finasial, sementara mereka yang di Tengah akan terpinggirkan. kembalinya elitisme pendidikan. Dengan akses yang terbatas, tes berlapis, dan kemungkinan fasilitas mewah, sekolah ini berpotensi menjadi lembaga prestisius yang memisahkan “mereka yang layak dibina” dan “mereka yang cukup puas di pinggir”. Ini mengingatkan pada kegagalan program RSBI yang akhirnya dibatalkan Mahkamah Konstitusi karena menciptakan diskriminasi.
Sehingga refleksi yang sama-sama direnungkan, ke mana arah pendidikan kita dan untuk siapa sebenarnya? Apakah seluruh warga negara Indonesia, atau mereka yang masuk kualifikasi saja? Jika kita sedikit menapak tanah, terlihat jelas jarak pendidikan antara pulau jawa dan luar jawa, alih-alih mengejar deficit perbedaan, narasi yang dimunculkan ialah akan ditambahnya jurang baru yang memperlebar, hal ini terjadi karena sekolah yang biasa akan kembali dilupakan. Para lulusannya akan sulit mengejar sekolah Impian atau universitas tujuan.
Karena hakikat perlombaan untuk kenyamanan hidup bisa ditentukan sejak dari sekolah dasar. Mereka yang masuk sekolah dasar favorit akan lancar menuju sekolah menengah pertama, menuju sekolah menengah atas dan berlanjut di perguruan tinggi. Mereka yang gagal masuk sekolah favorit, ataupun tergelincir dan melanjutkan ke sekolah favorit, hidupnya akan menjadi kelas menengah. Dan melahirkan anak yang akan menjadi kelas menengah dan seterusnya, syukur jika tidak masuk ke kelas bawah/miskin.
Kelas menengah yang tersisih
Jika Anda semua sering melihat curhan hati beberapa pengguna twitter/X, dalam tema kalahnya kaum menengah, sering muncul curhatan menyatakan mereka hidup dalam kehimpitan, mereka tidak miskin, karena memiliki kecukupan, namun jelas dalam menjalani hidup akan sangat sulit, karena memang pas-pasan dan juga tidak mendapat subsidi dari negara. Latar belakang kaum menengah ini sangat banyak, seperti ASN golongan 1 atau 2, pelaku usaha kecil dan mikro, para nelayan, petani dan lainnya. Seperti contoh, anak ASN tidak berhak mendapat bantuan KIP, karena memang salah satu persyaratannya bukan dari keluarga ASN atau PNS, sementara gaji mereka tentu sangat pas-pasan.
Makin terbuka jurang mereka untuk tidak melanjtkan pendidikan karena UKT yang mahal. Atau mereka yang belajar dengan giat, namun ternyata kemampuan akademiknya begitu saja, dengan nilai kelulusan standar, atau jika diperkuliahan IPK mereka tentu tidak sebatas 2.3 tetapi tidak cumlaude, maka terputus kesempatan mereka mencari pekerjaan yang sudah membatasi denga standar minimal IPK 3.0, seperti itu juga beasiswa pendidikan LPDP yang syaratnya IPK di 3.0 ke atas. Data Kemendikbud terakhir menunjukkan bahwa rata-rata IPK mahasiswa nasional masih berada pada kisaran 2.89–3.10, artinya banyak yang berada tepat di ambang bawah. Tidak malas, tetapi juga tidak cukup cemerlang untuk masuk radar kebijakan afirmatif.
Demikian nestapanya kelas menengah di negeri tercinta kita ini. tentu akan sangat menyebalkan jika opini ini dibalas dengan survivior bias yang menyatakan, “Ada kok orang miskin yang rajin jadi pinter trus dapat kerja, dapat beasiswa”, dan ada yang lain. Narasi ini problematis. Ia mengabaikan kenyataan struktural dan hanya fokus pada kisah pengecualian. Tentu ada yang berhasil, tetapi jumlahnya tidak cukup signifikan untuk menjadi dasar kebijakan. Kebijakan publik tidak bisa dibuat berdasarkan cerita inspiratif semata.
Karena, sekali lagi hal kasuistik demikian sayangnya sedikit sekali kisahnya, lebih banyak mereka kelas menengah yang bisa sekolah hanya sampai SMP dan SMA, lalu bekerja, dan berlanjut siklus hidupnya kepada anak turunan mereka. Menjadikan kisah pengecualian sebagai norma untuk merespons kegagalan sistemik ialah bentuk ketidakadilan baru. Mereka tidak miskin, tapi tidak terlalu kaya untuk keluar dari siklus ini.
Adanya Krisis sistemik yang menyasar kelas menengah hari demi hari. Seakan tidak selesai dan tidak ingin diselesaikan. Mereka tidak mendapat tax amnesty dan tidak mendapat BLT, dan tentunya mereka wajib bayar pajak. Anehnya pajak mereka tidak dirasakan oleh anak mereka.
Sistem selektif berbasis prestasi ekstrem atau kemiskinan ekstrem justru menciptakan kasta pendidikan. Dan yang terjebak di tengah akan terus menjadi kelas menengah yang stagnan, sulit bergerak, dan makin tertekan.
Pada akhirnya, pertanyaan penting harus kembali diajukan: untuk siapa pendidikan nasional ini dibangun? Jika hanya untuk mereka yang sesuai kriteria tertentu, maka cita-cita keadilan sosial dan kemajuan bersama akan tinggal jargon. Pendidikan seharusnya membuka jalan bagi semua, bukan hanya bagi yang ‘beruntung’ secara indeks atau indikator.
Akhir kata, semoga hardiknas ini menjadi momentum untuk meratanya pendidikan bagi semua.