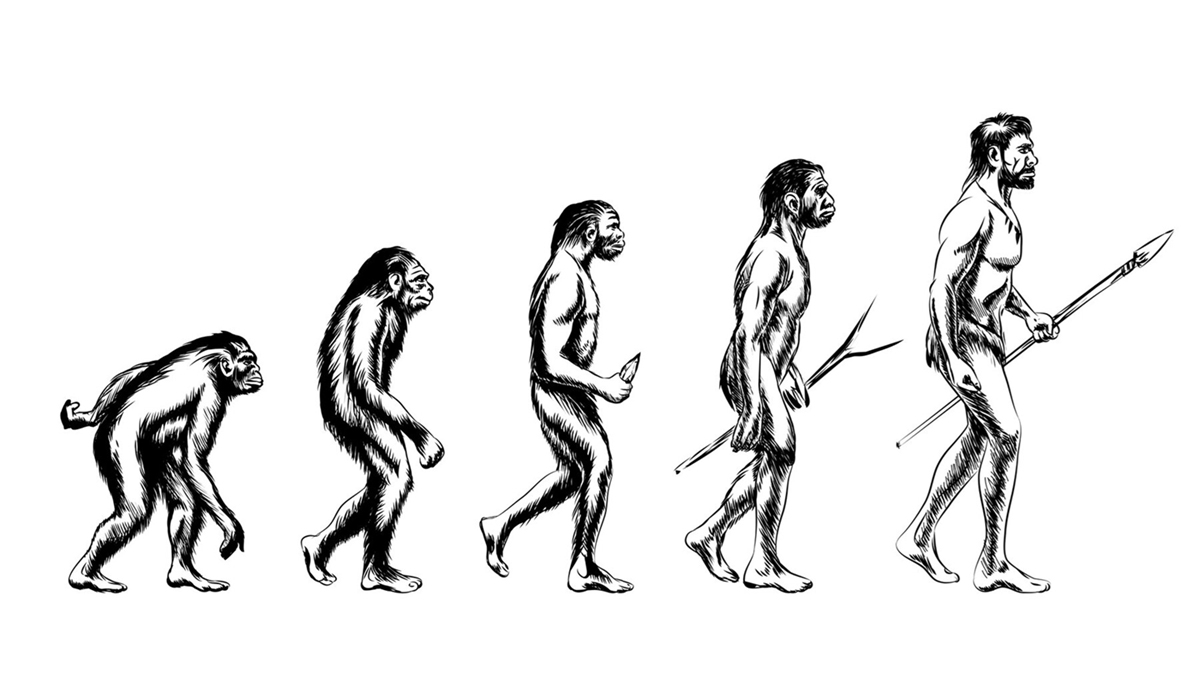(MI/Duta)
(MI/Duta)
SETIAP 21 April, kita kembali mengenang sosok Raden Ajeng Kartini, seorang pelopor pembebasan perempuan yang memperjuangkan hak atas pendidikan yang merdeka dan adil. Di tengah peringatan Hari Kartini, semangat perjuangannya hendaknya menjadi cermin bagi kita untuk mengevaluasi kembali sistem pendidikan di negara kita.
Apakah pendidikan kita telah memanusiakan, seperti yang diinginkan Kartini, atau justru semakin membelenggu generasi muda? Pertanyaan ini mengingatkan kita pada tantangan besar yang dihadapi pendidikan Indonesia, di mana anak-anak sering kali masih dipandang sebagai objek yang harus diisi dengan pengetahuan, bukan sebagai subjek yang aktif dalam proses pembelajaran.
Namun, justru dari cara pandang itulah akar persoalan pendidikan kita bermula. Ketika sistem pendidikan tidak mampu berdiri tegak sebagai ruang yang merdeka, maka ia mudah terombang-ambing oleh arus kebijakan, selera politik, dan tren internasional. Lembaga-lembaga resmi yang seharusnya menjadi nakhoda pun sering kehilangan arah.
Sementara itu, rakyat—yang mestinya menjadi subjek utama pembangunan bangsa—hanya bisa mengelus dada, menyaksikan kapal besar bernama pendidikan nasional terus berlayar tanpa kompas. Di kejauhan, negeri-negeri lain tampak melaju dengan tujuan yang terukur dan arah yang jelas, sementara kita, seperti menunggu badai untuk menuntun kita secara ajaib ke pelabuhan impian.
KURIKULUM KITA: CERMIN KRISIS TUJUAN PENDIDIKAN
Kondisi pendidikan di Indonesia hari ini bukanlah sesuatu yang hadir tiba-tiba. Ia tumbuh dari sejarah panjang kehidupan sosial yang dipenuhi kebingungan kolektif tentang arah hidup dan berbangsa. Dalam kebingungan itulah, falsafah Pancasila—sebagai dasar negara—kehilangan makna sejatinya.
Selama lebih dari tiga dekade, sistem pendidikan kita berjalan dalam skema yang kaku dan otoriter. Pendidikan yang bersifat top-down itu tak menyediakan ruang untuk berpikir bebas, berdialog, atau bertanya. Dalam kerangka itulah, siswa diposisikan semata sebagai objek—bukan subjek—yang harus dibentuk sesuai cetakan kekuasaan.
Kurikulum yang dikembangkan pun hanya menjadi instrumen teknis untuk menghasilkan individu-individu yang seragam dan mudah dikendalikan. Tidak ada tempat bagi diskusi kritis atau pengembangan pemikiran mandiri, karena tujuan utamanya ialah menghasilkan manusia-manusia patuh.
Keberhasilan pendidikan dinilai melalui alat tunggal: ujian nasional. Ujian ini bukan hanya memutuskan nasib siswa melalui cap 'lulus' atau 'gagal', tapi juga menjadi palu evaluasi bagi sekolah dan kepala sekolahnya. Sistem ini menciptakan tekanan besar demi mempertahankan keseragaman, bahkan hingga ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
Dampaknya, lulusan dari sistem ini tumbuh menjadi individu mekanistik—mampu menjalankan perintah teknis, tetapi miskin empati dan nurani. Pendidikan tidak melatih mereka untuk berpikir tentang orang lain, apalagi tentang keadilan sosial. Sebaliknya, mereka diarahkan untuk fokus pada diri sendiri, menyelesaikan tugas pribadi, dan tidak mengganggu 'tatanan' sosial yang sudah ada.
Dalam kerangka ini, sikap kritis menjadi sesuatu yang mencemaskan karena bisa memunculkan perubahan. Maka, cukup jadilah individu yang 'baik-baik saja', yang hanya mengikuti aturan dan membiarkan urusan besar diselesaikan segelintir elite yang mengaku tahu segalanya.
Ironisnya, pendidikan kita kini tengah memanen hasil dari benih-benih kegelapan itu. Model pendidikan kita—yang tak memberi ruang dialog, imajinasi, atau keberanian berpikir—bahkan lebih usang daripada sistem pendidikan zaman Yunani kuno. Mungkin jika Socrates masih hidup, ia akan terheran-heran melihat bagaimana manusia modern masih menggunakan pendekatan pendidikan yang ia kritik habis-habisan di masanya. Ia percaya bahwa pendidikan sejati adalah pendidikan dialogis—di mana pertanyaan menjadi jantung pembelajaran dan manusia ditumbuhkan kesadarannya agar mampu menciptakan peradaban yang lebih baik.
Sebaliknya, sistem pendidikan kita hari ini justru melahirkan manusia-manusia yang melihat ilmu dan keterampilan semata sebagai alat untuk mencapai kekuasaan. Bagi mereka, belajar hanyalah jalan pintas untuk memperoleh kekuasaan, pengaruh, atau kekayaan—bukan untuk memperdalam nurani atau mengasah akal. Maka, tak mengherankan jika banyak dari mereka hanya terobsesi memuaskan keinginan perut—urusan duniawi yang dangkal—tanpa pernah menyentuh ruang hati atau kepala. Dua ruang terakhir itu nyaris tak tersentuh dalam sistem pendidikan yang menekankan hafalan dibandingkan perenungan, dan ketaatan dibandingkan keberanian berpikir.
MENATA ARAH
Selama dunia belum berakhir, harapan untuk memperbaiki pendidikan masih terbuka lebar. Kita masih memiliki ruang untuk kembali pada niat tulus dan arah yang benar. Bagi para pendidik dan pemikir yang benar-benar peduli akan masa depan bangsa, kerja keras adalah keniscayaan.
Di tengah dominasi sistem pendidikan negeri yang kaku, birokratis, dan terobsesi pada keseragaman, harapan besar kini tertuju pada sekolah-sekolah swasta dan komunitas pendidikan alternatif. Mereka diharapkan mampu menjadi ruang tumbuh yang lebih merdeka bagi generasi muda, tempat pendidikan dijalankan dengan kesadaran dan keikhlasan, bukan semata demi memenuhi regulasi atau akreditasi.
Tak bijak jika kita terus membiarkan kapal besar bernama pendidikan ini terombang-ambing tanpa arah di lautan ketidakpastian. Namun, bersikap acuh atau bahkan destruktif tentu juga bukan pilihan. Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan ajaran agama, sudah seharusnya kita bergandengan tangan. Menutup celah-celah kebocoran di tubuh sistem, sambil terus mengayuh dayung perubahan.
Tujuan kita bukan melawan badai, tetapi mencari dermaga tempat generasi muda bisa berlabuh dengan aman dan tumbuh dengan utuh.
Sudah waktunya arah pendidikan kita berbalik—menempatkan siswa sebagai pusat dan pelaku utama pembelajaran. Kurikulum dan buku ajar hanyalah sarana, bukan tujuan. Tugas utamanya ialah menumbuhkan daya pikir kritis dan reflektif, bukan menjejalkan hafalan. Sayangnya, di tengah riuhnya perdebatan soal sistem dan kebijakan, kita kerap melupakan inti sejati pendidikan: anak-anak itu sendiri, para pembelajar terbaik yang seharusnya menjadi perhatian utama.
YB Mangunwijaya mengingatkan kita bahwa guru bukan pencipta potensi, melainkan penolong kelahiran—seperti bidan yang membantu proses alami berjalan dengan selamat. Potensi anak sudah ada sejak awal; tugas pendidikan ialah menemukannya, merawatnya, dan membiarkannya tumbuh. Di sinilah roh sejati pendidikan hadir: bukan pada tumpukan data atau ujian, tapi pada relasi manusiawi yang menumbuhkan nalar, rasa, dan makna.