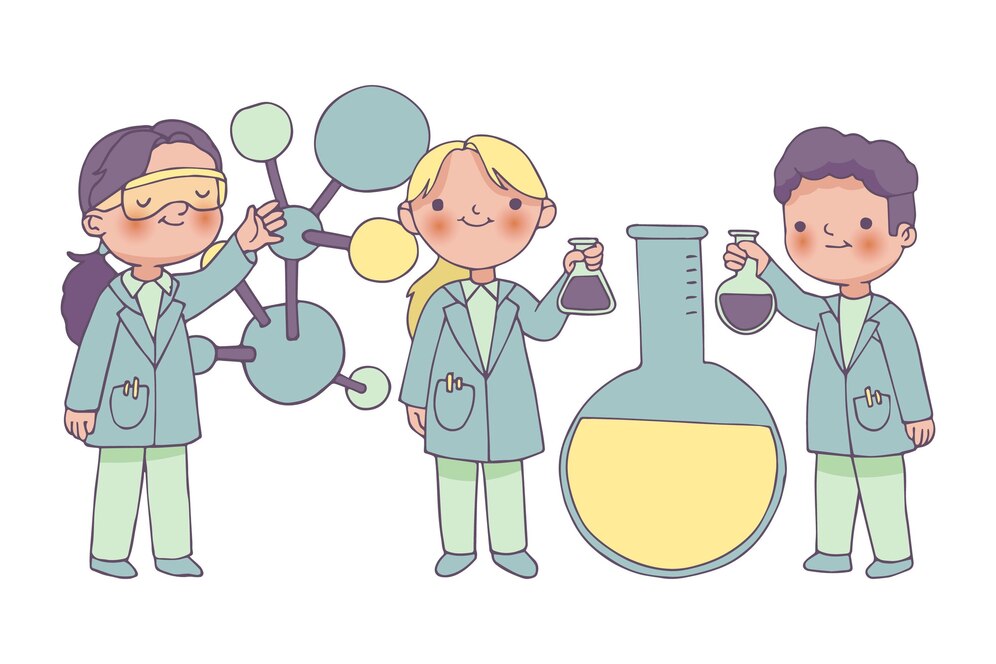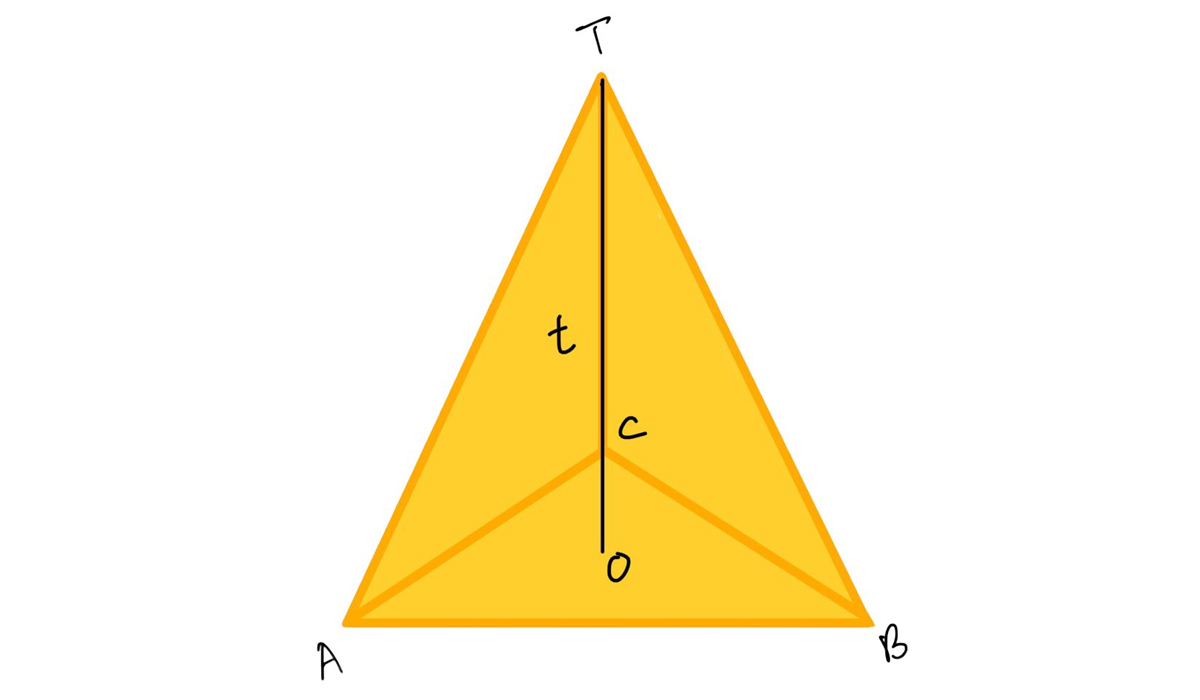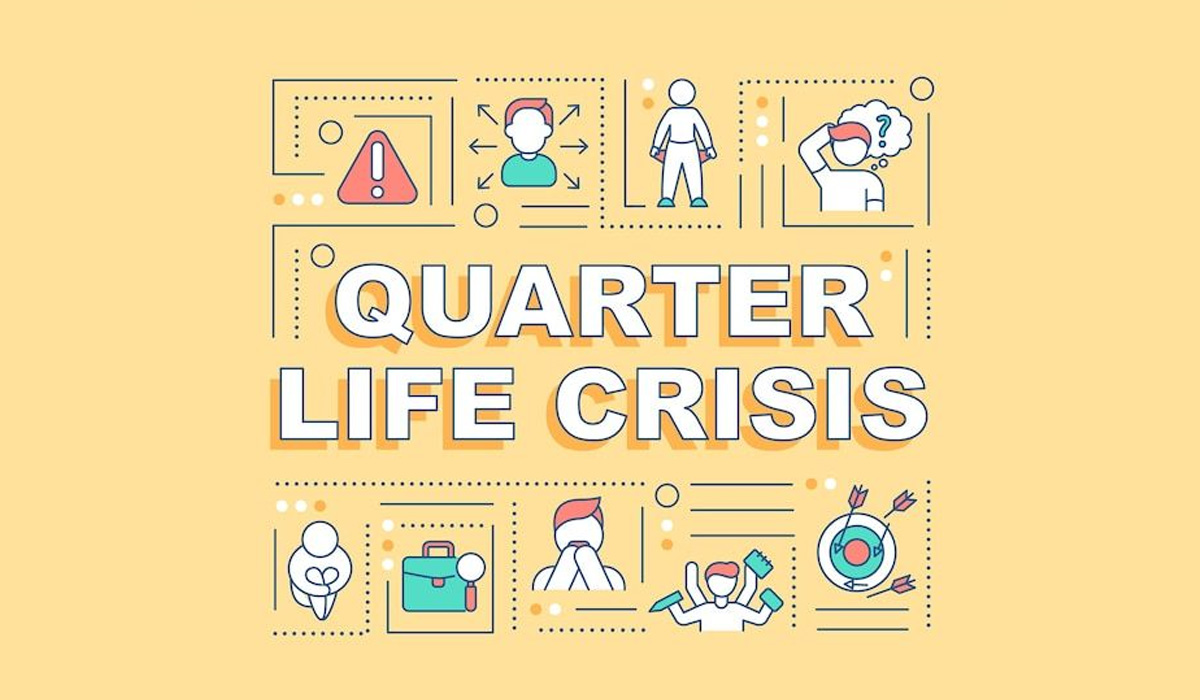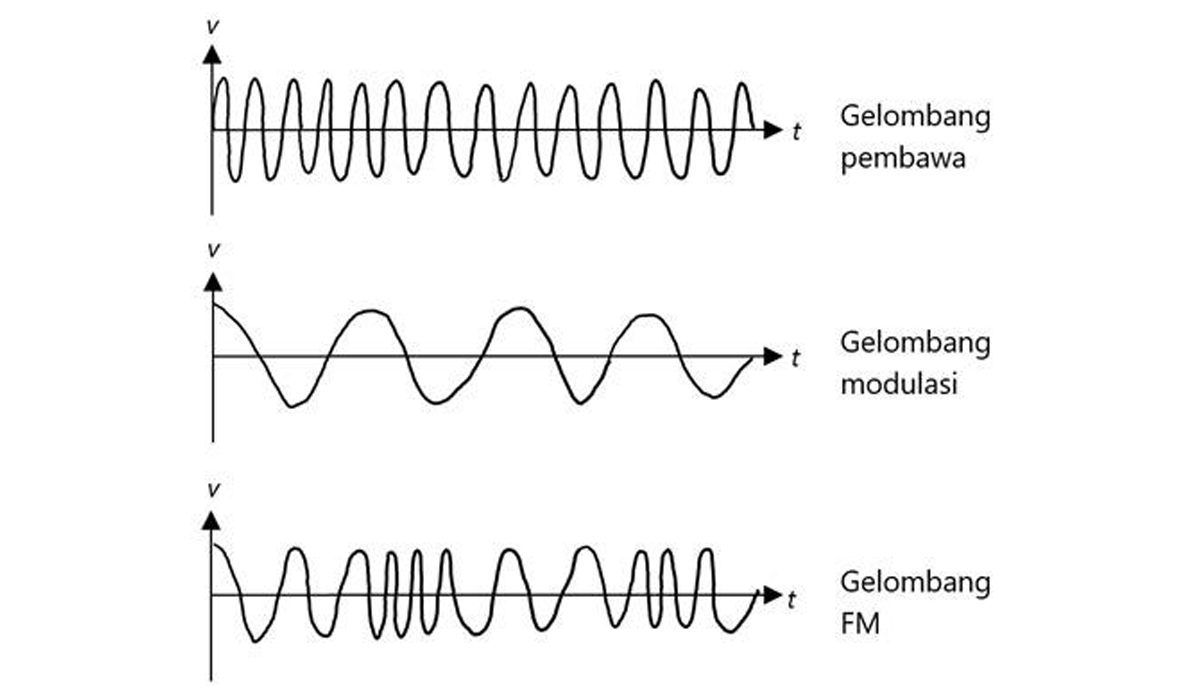MI/Duta(Dok. Pribadi)
MI/Duta(Dok. Pribadi)
DALAM buku Tractatus Logico Philosophicus, Ludwig Wittgenstein menulis, “Tentang apa yang tidak dapat kita bicarakan, kita harus berdiam diri.” Namun, di dunia Chairil Anwar, keheningan justru dilawan dengan kata-kata. Puisi lahir dari keterdesakan untuk berbicara saat dunia membisu.
Di tengah krisis literasi, menulis menjadi bentuk perlawanan sunyi, menjaga kemanusiaan dalam bahasa yang kian kehilangan makna di ruang pendidikan formal. Di sebuah kelas di Aceh, seorang siswa membacakan puisinya tentang ibu, gempa, dan harapan menjadi guru—dengan kejujuran yang menyentuh. Puisinya akan diterbitkan, bukti bahwa literasi masih bisa menemukan ruang untuk bertumbuh.
Di saat yang sama, di banyak sekolah lain di negeri ini, siswa masih sibuk menyalin kalimat di papan tulis. Buku yang mereka kenal hanyalah LKS, dan menulis berarti menyalin dan menjawab soal. Membaca? Kadang hanya tugas. Di negeri yang merayakan Hari Puisi Nasional, banyak anak yang bahkan tak tahu cara menikmati puisi.
Inilah paradoks kita hari ini: kata-kata diagungkan dalam seremoni, tapi sering diabaikan dalam praktik pendidikan. Kita mengenang Chairil Anwar dan puisi-puisi perjuangannya, tapi kita lupa bahwa perjuangan literasi hari ini jauh lebih senyap dan kompleks—berhadapan dengan sistem yang masih menomorduakan bacaan bermakna dan pembelajaran yang jarang memberi ruang ekspresi.
Hari Puisi Nasional yang kita peringati setiap tahun seharusnya lebih dari sekadar nostalgia. Ia adalah alarm. Tanda bahwa bangsa ini sedang krisis dalam hal paling mendasar: kemampuan membaca, menulis, dan berpikir.
Namun, di tengah krisis ini, masih ada ruang-ruang kecil yang menyalakan lentera harapan. Sekolah-sekolah seperti Sekolah Sukma Bangsa membuktikan bahwa menulis bisa menjadi budaya. Bahwa membaca bisa dirayakan. Dan bahwa puisi—seperti yang pernah ditulis Chairil—masih bisa menjadi senjata perlawanan, bukan dengan amarah, tetapi dengan kesadaran.
LITERASI: TANTANGAN DAN PERJUANGAN ABAD 21
Literasi merupakan salah satu kunci penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Berdasarkan hasil survei PISA 2018, kemampuan membaca siswa Indonesia masih sebatas menghafal, belum mencapai pemahaman. Ini bukan sekadar angka PISA 2018 yang menempatkan Indonesia di peringkat ke-72 dari 77 negara, melainkan potret nyata ruang kelas yang kehilangan kepekaan terhadap makna kata.
Literasi tidak lagi cukup dipahami sebagai kemampuan membaca permukaan. Literasi modern mencakup kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, dan menyampaikan gagasan secara efektif (UNESCO, 2017). Maka, membangun budaya literasi adalah perjuangan zaman ini—dan salah satu ujung tombaknya ialah guru.
Sekolah dan guru tidak bisa hanya berfungsi sebagai penyampai materi. Mereka harus menjadi penggerak literasi. Bukan sekadar menugasi siswa membaca dan menulis, tetapi juga menciptakan ruang-ruang hidup di mana kata-kata memiliki makna, refleksi, dan kekuatan untuk mengubah cara berpikir.
SEKOLAH SUKMA BANGSA: BUDAYA LITERASI SEBAGAI GERAKAN
Dalam lanskap pendidikan yang masih didominasi oleh pengajaran hafalan dan capaian nilai kognitif, Sekolah Sukma Bangsa mengambil jalan berbeda. Sejak awal, sekolah ini membangun budaya belajar yang meletakkan literasi sebagai jantungnya. Bagi mereka, membaca dan menulis bukan sekadar keterampilan, tetapi cara berpikir dan bertumbuh.
Budaya literasi di sekolah ini tidak hadir sebagai program tambahan, melainkan ditanamkan dalam denyut harian kehidupan sekolah. Program seperti Reading Day
menjadi momen mingguan yang dinantikan siswa. Bukan hanya karena mereka membaca buku, tetapi karena mereka membaca dalam suasana yang hidup dan penuh dialog. Siswa boleh memilih buku yang mereka suka, mendiskusikannya, bahkan mengadaptasinya ke dalam puisi, drama, atau cerita gambar.
Dari budaya membaca, siswa kemudian didorong menulis. Bukan sekadar menulis karena tugas, tapi karena mereka punya cerita. Program Siswa Menulis memberikan ruang bagi anak-anak untuk mengekspresikan pengalaman, imajinasi, dan keresahan mereka. Yang lebih luar biasa, karya-karya ini tidak berhenti di laci atau map portofolio—mereka diterbitkan dan dirayakan melalui acara tahunan bernama Kenduri Buku.
Di sinilah pendidikan literasi mencapai bentuk idealnya: ketika membaca menjadi kebiasaan dan menulis menjadi ekspresi jati diri. Namun, transformasi semacam ini tidak mungkin terjadi tanpa peran sentral guru.
GURU MENULIS: GURU SEBAGAI PEMIKIR DAN PRODUSEN PENGETAHUAN
Di Sekolah Sukma Bangsa, guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai penulis dan pemikir dalam dunia pendidikan. Melalui Program Guru Menulis, para pendidik didorong menulis esai, opini, refleksi pembelajaran, hingga artikel ilmiah yang dipublikasikan di media massa dan Jurnal Sukma, yang menjadi wadah bagi mereka untuk berbagi praktik baik, studi kasus, dan hasil penelitian tindakan kelas, memperkuat peran mereka sebagai praktisi reflektif.
Aktivitas ini membangun kepercayaan diri mereka, menguatkan identitas sebagai praktisi reflektif, dan menjadikan mereka produsen pengetahuan, bukan sekadar pelaksana kebijakan.
Selain itu, guru-guru di sekolah ini juga terlibat dalam pengembangan buku ajar lintas disiplin, yang ditulis dengan pendekatan kontekstual dan humanis, memastikan materi ajar sesuai dengan kebutuhan dan pengalaman siswa, bukan sekadar terjemahan kurikulum.
Dengan demikian, Program Guru Menulis tidak hanya menghasilkan karya-karya bermutu, tetapi juga mengubah cara guru memandang diri mereka, dari sekadar pelaksana kebijakan menjadi agen perubahan yang membangun warisan berpikir bagi siswa dan masyarakat.
Di tengah krisis literasi, tantangan terbesar bukan hanya rendahnya kemampuan membaca, tetapi juga ketidaksiapan sistem pendidikan untuk memberi ruang ekspresi yang bermakna. Program literasi di Sekolah Sukma Bangsa menunjukkan bahwa menulis bukan sekadar keterampilan, tetapi juga cara untuk berbicara, mengungkapkan pengalaman, dan membangun dunia baru.
Namun, kita harus bertanya, apakah kita sudah menciptakan lingkungan di mana kata-kata memiliki kekuatan untuk mengubah? Guru dan sekolah harus berperan sebagai agen perubahan, memastikan literasi bukan hanya tugas, tetapi juga perlawanan sunyi yang mempertahankan hakikat berpikir dan merasa.
Sekolah dan guru harus memilih: menjadi penggerak yang menumbuhkan dunia baru atau membiarkan ruang-ruang belajar terus membisu. Karena, di dunia yang kian bising, menulis tetaplah cara paling sunyi untuk bertahan.