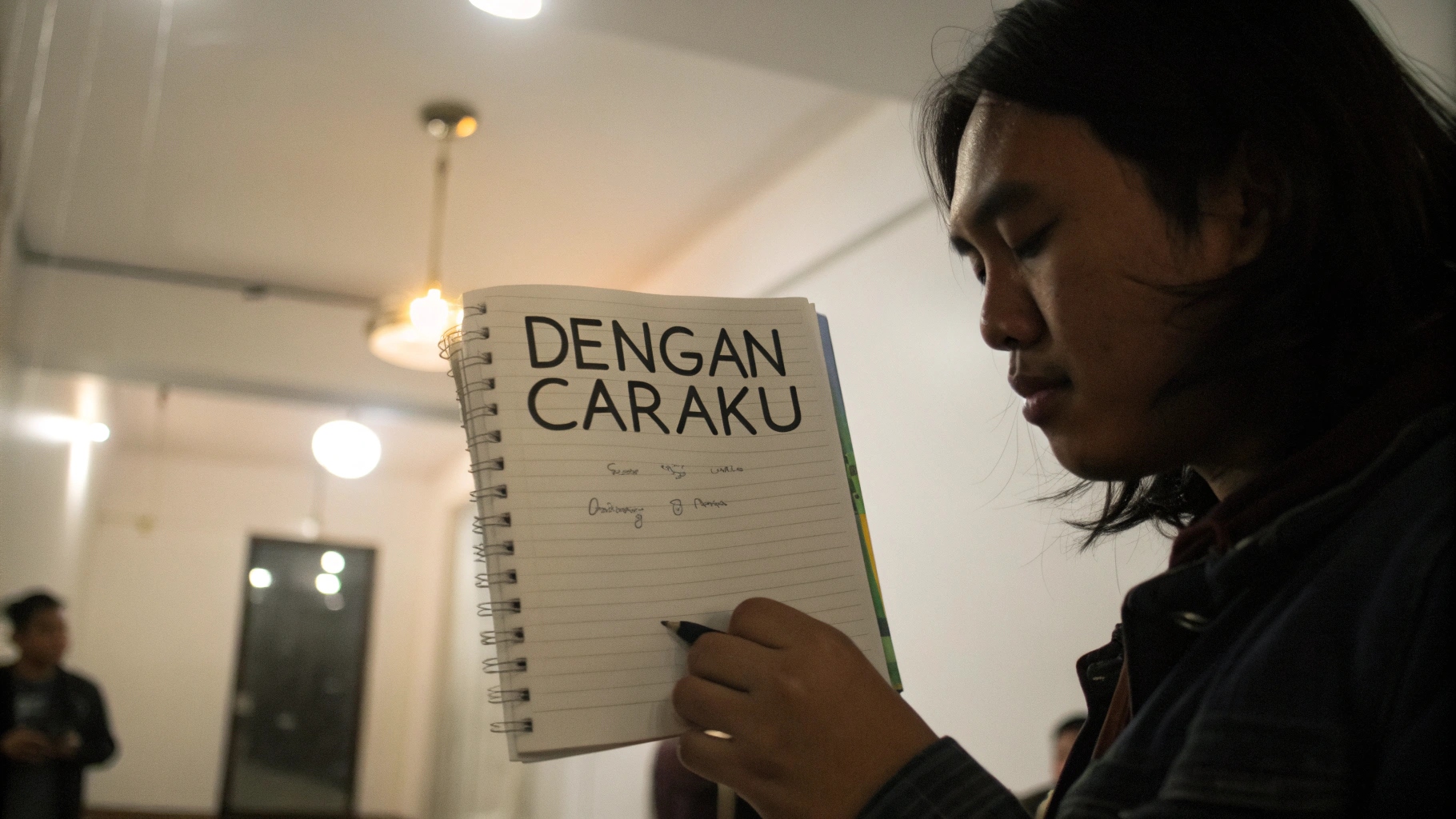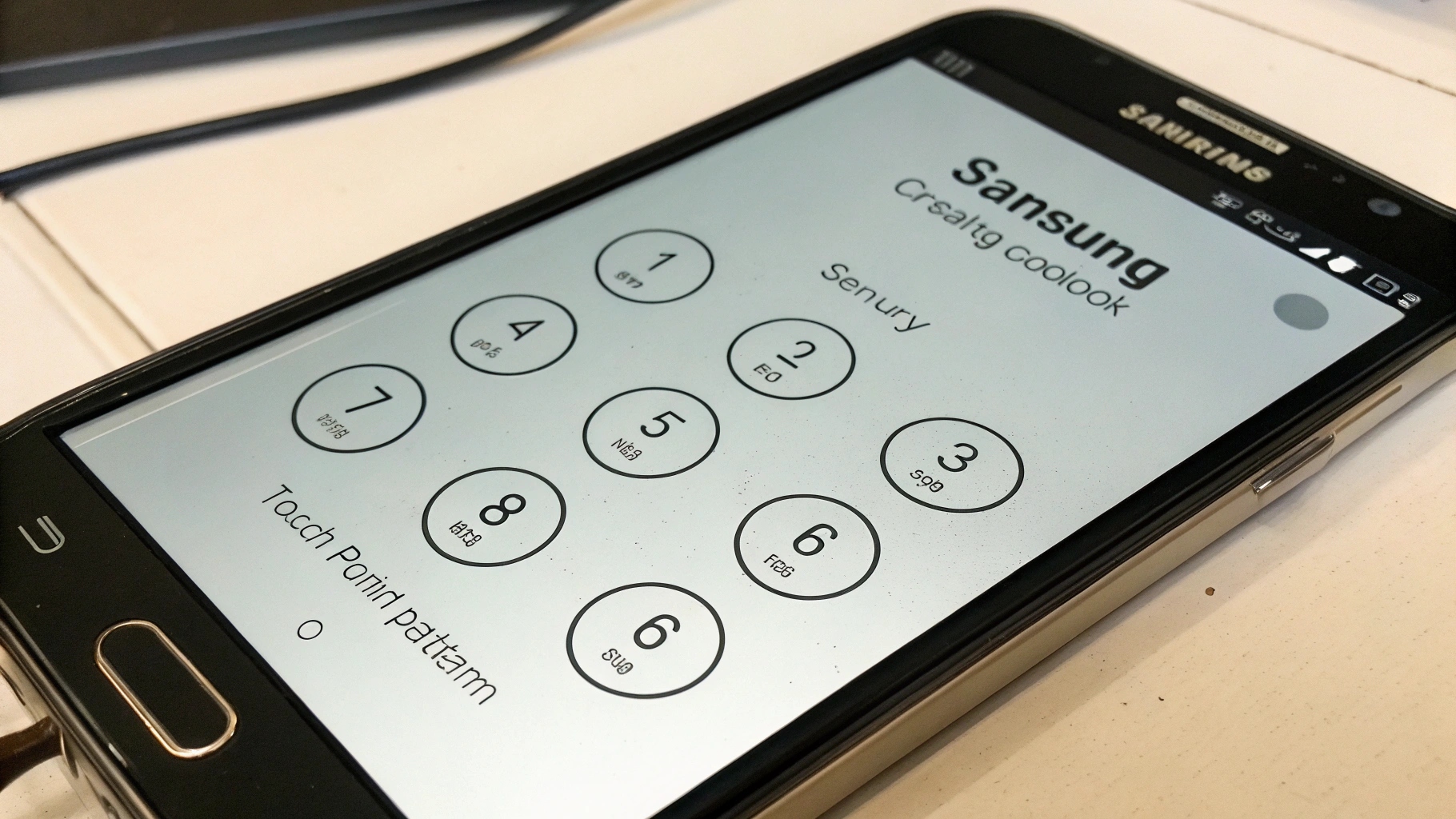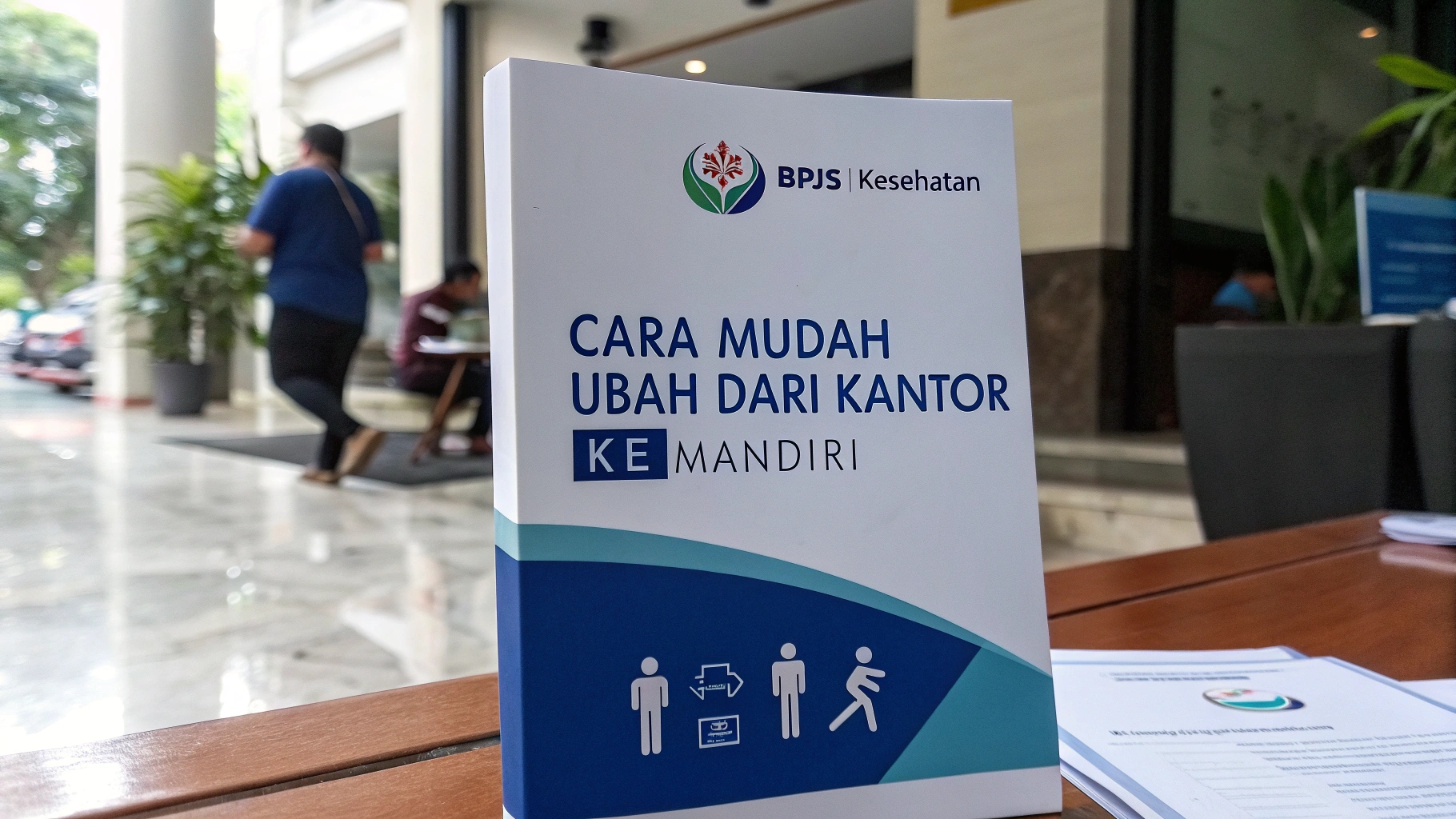(Dok. Pribadi)
(Dok. Pribadi)
RILIS terbaru Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 pada awal Mei lalu menunjukkan indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat ke angka 80,51% (berdasarkan metode keberlanjutan) dan 92,74% (berdasarkan metode cakupan Dewan Nasional Keuangan Inklusi/DNKI). Sejalan dengan itu, data DNKI (2023) mencatat bahwa penggunaan akun keuangan terus meningkat dari 59,7% pada 2014 menjadi 88,7% pada 2023.
TANTANGAN
Kemudian, untuk mencapai pembangunan ekonomi yang inklusif, pemerintah telah menargetkan inklusi keuangan mencapai 98% pada 2045 (RPJPN), dengan target jangka menengah sebesar 93% (RPJMN 2025-2029). Meskipun angka-angka itu menggembirakan, terdapat dua tantangan penting.
Pertama, tingkat literasi keuangan dalam SNLIK 2025 masih tertinggal di angka 66,5%. Artinya, masih terdapat masyarakat yang telah memiliki akun, tapi belum tentu memahami produk keuangan yang dimilikinya. Kedua, apakah jumlah rekening yang telah merambah mayoritas penduduk Indonesia saat ini membawa perubahan substansial atau dampaknya sudah cukup signifikan bagi kesejahteraan masyarakat?
Inklusi keuangan memang disebut sebagai fondasi penting dalam pencapaian 8 dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030, mulai dari pengentasan masyarakat dari kemiskinan, ketahanan pangan, kesehatan, kesetaraan gender, hingga pertumbuhan ekonomi dan pengurangan ketimpangan. Bahkan, riset IMF (2018) menunjukkan bahwa kenaikan 1% indeks inklusi keuangan dapat meningkatkan pendapatan per kapita sebesar 0,14% dan menurunkan kemiskinan sebesar 1,4%.
Namun, beberapa riset terakhir yang dilakukan Ozili (2021), Prabakhar (2021), dan Bernards (2021) mengingatkan bahwa inklusi keuangan tidak otomatis menjadi solusi permasalahan ekonomi dan kesejahteraan. Jika tidak dikelola dengan hati-hati, inklusi keuangan berisiko memperlebar ketimpangan, terutama jika akses dan manfaatnya hanya dinikmati kelompok tertentu, atau jika literasi dan perlindungan konsumen diabaikan.
Faktanya, pertumbuhan ekonomi global selama beberapa dekade terakhir justru diiringi oleh stagnasi pendapatan kelas menengah-bawah serta ketimpangan yang meningkat (Hall dkk, 2019). Ini menunjukkan bahwa inklusi keuangan saja tidak cukup untuk mengatasi permasalahan kesejahteraan. Sebab, globalisasi dan finansialisasi ekonomi membuat kekayaan semakin terkonsentrasi di kelompok tertentu.
Program inklusi keuangan di beberapa negara saat ini cenderung menekankan tanggung jawab individu dalam keputusan finansial. Program literasi dan inklusi sering kali berakhir pada pembukaan akun atau rekening dengan mudah, tetapi tidak diiringi dengan edukasi mengenai biaya dan risiko yang dihadapi di sektor keuangan.
Meskipun semakin mempermudah akses keuangan, digitalisasi dan inovasi teknologi finansial juga membawa tantangan baru: kelompok rentan yang belum digitally literate atau sangat bergantung pada uang tunai justru semakin terpinggirkan (Ozili, 2021). Jika tidak diimbangi dengan literasi dan perlindungan, agenda ini justru menjadi penghalang bagi kelompok rentan tersebut untuk terinklusi.
Di samping itu, praktik inklusi keuangan berpeluang memperkuat eksklusi sosial jika tidak memperhatikan situasi masyarakat rentan. Salah satunya ialah fenomena poverty premium, di mana individu dengan pendapatan rendah justru membayar lebih mahal untuk layanan keuangan dasar karena kurangnya akses ke layanan yang terjangkau, seperti pinjaman yang lebih mahal biayanya daripada individu dengan pendapatan lebih tinggi (Prabhakar, 2021).
Kemudian, penekanan pada literasi keuangan sebagai solusi utama atas keterbatasan dalam akses keuangan. Pendekatan ini menempatkan aspek pemahaman individu terhadap keuangan, tetapi belum memperhatikan determinan struktural penyebab eksklusi keuangan, seperti rendahnya pendapatan, instabilitas pasar tenaga kerja, dan ketimpangan sosial.
BEBERAPA RISET
Karena itu, beberapa riset menekankan supaya inklusi keuangan tidak berujung pada ‘finansialisasi kemiskinan’. Sebab, sering kali dampak dari inklusi keuangan menghilang setelah beberapa tahun akibat perubahan prioritas program pemerintah atau terjebak pada pemenuhan agenda quick-wins. Padahal, penting untuk dilihat bagaimana kemiskinan memengaruhi pengambilan keputusan finansial sebagai penyebab eksklusi keuangan.
Untuk menjawab tantangan ini, ekonom Oxford, Kate Raworth (2017), memperkenalkan ekonomi donat (doughnut economy) dan konsep economics of mutuality dengan menawarkan dogma prioritisasi kesejahteraan manusia, dan kelestarian bumi di atas pertumbuhan ekonomi yang kurang terkontrol. Konsep ini mendorong keseimbangkan fondasi sosial (pemenuhan kebutuhan dasar) dan menjaga alam.
Salah satu konsep yang sejalan dengan ekonomi donat ini ialah universal basic income (UBI) dan universal basic services (UBS), yang menempatkan negara sebagai aktor utama peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar fasilitator pasar. Program inklusi finansial yang dilakukan beriringan dengan pemenuhan akses dan hak terhadap layanan dasar publik (seperti perumahan, kesehatan, pendidikan) kepada seluruh masyarakat (Prabhakar, 2021). Melalui dua kebijakan ini, kesejahteraan dapat meningkat, yang pada akhirnya memberikan masyarakat kemampuan secara finansial untuk memilih produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan berbagai kebutuhannya.
LITERASI KEUANGAN
Inklusi keuangan yang dikelola dengan baik dan dibarengi dengan program pemerataan akses dasar serta peningkatan pendapatan sejatinya mampu menurunkan ketimpangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih adil. Kuncinya ialah memastikan akses yang adil, literasi yang memadai, serta perlindungan konsumen yang optimal. Di sini pemerintah perlu berperan aktif, tidak hanya berupaya mencapai target angka, tetapi juga sebagai pelindung kelompok rentan serta pemberi akses yang inklusif dan berkelanjutan.
Menuju 2045, target inklusi keuangan 98% perlu dimaknai lebih dari pencapaian administratif. Ia harus instrumen nyata untuk menurunkan ketimpangan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan pendapatan per kapita secara nyata. Inklusi keuangan sejati adalah inklusi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia. Ini hanya bisa dicapai jika literasi keuangan bersama kesejahteraan seluruh masyarakat diutamakan sebagai fondasi ekosistem keuangan nasional.