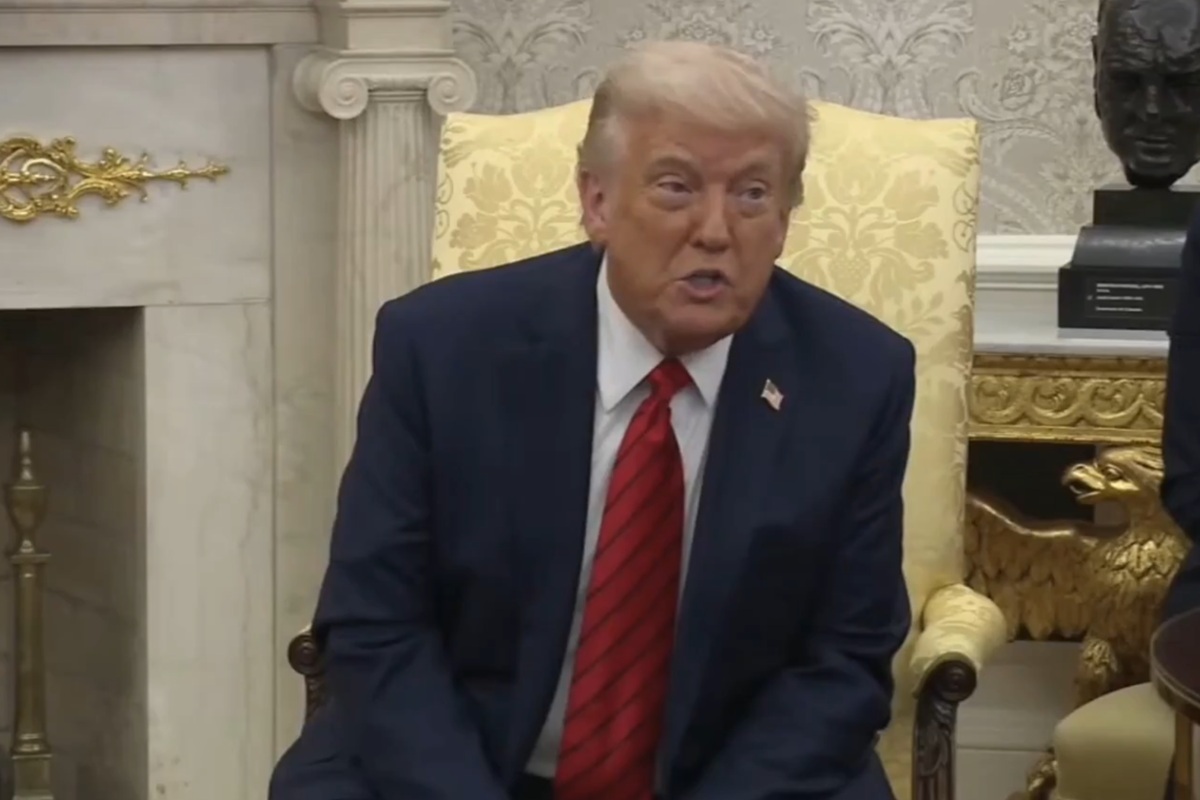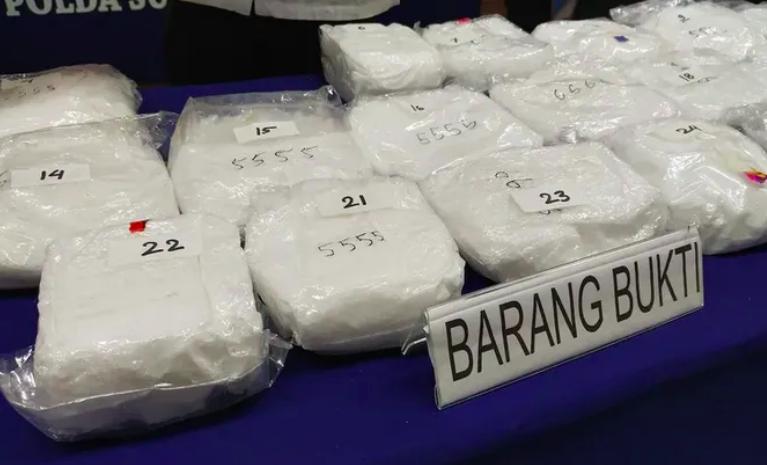(MI/Duta)
(MI/Duta)
BAPA Suci, Paus Fransiskus, pada 21 April 2025, tepat pada hari Senin Paskah, telah wafat. Saya selalu yakin bahwa seseorang bisa ‘memilih’ hari kematiannya. Bapa Suci telah memilih hari kematian itu pada Senin Paskah. Pada hari Minggu Paskah, Hari Raya Kebangkitan Tuhan Yesus, Bapa Suci masih sempat tampil untuk memberi berkat Urbi et Orbi dan menyampaikan ucapan selamat Paskah kepada peziarah yang hadir di pelataran Santo Petrus.
Bapa Suci masih sempat mewartakan Kabar Sucika Paskah itu dengan suara terengah-engah. Hari Senin beliau mengembuskan napas terakhir, dan dengan itu ia pun ‘bangkit’ dan terlahir kembali dalam hidup baru yang kekal. Hal itu berbeda dengan seorang Romo Yesuit lain, Pierre Teilhard de Chardin, yang memilih wafat tepat hari Minggu Paskah pada 1955. Bapa Suci ini memilih untuk tetap mewartakan Kabar Sukacita Paskah pada Minggu Paskah dan baru wafat pada Senin. Ini sangat luar biasa.
Tentang beliau ini ada banyak hal yang bisa dicatat. Akan tetapi, di sini, saya hanya memfokuskan diri pada tiga poin berikut ini.
JANGAN LUPA ORANG MISKIN
Pertama, terkenallah sebuah cerita saat ia akan terpilih menjadi paus. Konon di dalam konklaf, Kardinal Jorge Bergoglio (JB) duduk berdambingan dengan seorang kawannya, kardinal dari Brasil, Sao Paolo, bernama Kardinal Nunes. Konon dalam Konklaf 2005, Kardinal JB ini menempati urutan kedua di bawah Kardinal Ratzinger yang kemudian menjadi paus dengan mengambil nama Paus Benediktus XVI. Paus Benediktus kemudian mengundurkan diri pada 2013. Dan, yang terpilih dalam Konklaf 2013 ialah Kardinal JB.
Saat semakin jelas bahwa nama dialah yang akan keluar, kawannya Kardinal Nunes tadi, seorang Fransiskan (OFM)m mencondongkan badan kepadanya dan berbisik, “Kawan, jika nanti sudah terpilih jadi paus, jangan lupa akan orang miskin.”
Beberapa waktu kemudian setelah terpilih, Kardinal JB mengatakan bahwa saat kawannya itu membisikkan pesan itu, ia (Kardinal JB) sudah tahu persis harus memilih nama kepausan apa? Pada waktu itu dunia kaget. Ia memilih nama Fransiskus. Itu pun bukan Fransiskus Xaverius, misionaris agung Yesuit yang terkenal itu dan kurang lebih sezaman dengan Santo Ignatius Loyola. Orang menduga, itu Fransiskus Xaverius, karena JB adalah Jesuit. Ternyata tidak. Fransiskus itu adalah Fransiskus dari Asisi.
Jadi, ada dua kejutan sekaligus. Pertama, dia adalah Yesuit pertama yang diangkat menjadi paus. Kedua, Yesuit pertama yang menjadi paus ini justru memilih nama Fransiskus, dan ini juga pertama kalinya nama Fransiskus dipakai sebagai nama paus. Luar biasa, bukan.
GEREJA KAUM MISKIN
Kedua, mengapa harus ingat akan orang miskin? Mungkin kita mengira bahwa kepedulian JB akan orang miskin baru muncul agak belakangan saja dalam hidupnya. Tidak. Kepedulian dan perhatian JB akan orang miskin sudah menjadi pokok karya layanan pastoral dia, bahkan sejak masih sebagai imam muda dan hal itu terus berlanjut sampai ia menjadi senior dan menjabat sebagai pejabat tinggi baik di dalam Serikat dan juga dalam Gereja Argentina.
Sejak muda ia sudah memilih untuk bekerja dan bahkan tinggal di daerah kantong kemiskinan. Ia tidak tinggal di istana megah dan mewah uskup. Sama seperti sosok pastor bonus (gembala yang baik), ia tinggal di tengah-tengah dan bersama dengan dombanya. Ia rela berbau ‘domba’ agar ada relasi kedekatan dan relasi saling ‘mengenal’ antara domba dan gembala. Tidak ada jarak (distansi). Tidak ada keterasingan (alienasi). Ia bahkan tidak malu berlumpur dan berkubang bersama dengan domba-dombanya.
Jika kemudian, saat sudah menjadi paus, ia pernah mengatakan bahwa dirinya menyukai gereja yang berlumur lumpur dan kubangan daripada gereja elite dan megah tetapi tidak merakyat, tidak mengumat. Gerakan dan tendensi itu sudah ia lakukan sejak masa mudanya sebagai imam Yesuit. Karena itu, ketika Kardinal Nunes mengingatkan dia agar tetap ingat akan orang miskin, menjelang terpilih menjadi paus dalam Konklaf 2013, Kardinal Nunes sebenarnya bukan membisikkan sebuah program mengawang, melainkan hanya menegaskan kembali agenda yang sudah biasa mereka lakukan, yakni tetap bersama orang miskin.
Hal menarik yang juga perlu saya sampaikan, bahwa jika para uskup Amerika Latin dalam CELAM (FABC-nya Amerika Latin) memilih teologi pembebasan dalam sidang mereka di Medelin tahun 1968 dan kemudian ditegaskan kembali di Puebla 1979 dengan orientasi dasar preferential option for the poor, maka JB justru memilih jalan berteologi yang lain yaitu teologi rakyat (teologi kerakyatan), people’s theology (teologia del pueblos) yang terutama sekali dibidani oleh Lucio Gera dan Rafael Tello. Tentang hal ini harus ditulis sebuah artikel khusus karena cukup panjang juga detail problematiknya.
Namun, di sini saya hanya menekankan satu hal. Teologi rakyat menghargai rakyat dan apa yang disebut popular religion itu. Tidak mengherankan jika Paus dipengaruhi oleh Gera sehingga pemikiran teologis Gera masuk juga dalam Evangelii Gaudium. Jika teologi pembebasan (Gutierrez dan Boff dll) menekankan preferential option FOR the poor, maka teologi kerakyatan ini lebih menekankan preferential option WITH the poor. Ini pun panjang, tidak cukup diuraikan di sini. Semoga pada kesempatan lain.
MENYERUKAN HARAPAN EKOLOGIS
Sekarang saya mau omong tentang poin ketiga. Dua tahun setelah terpilih menjadi paus, tahun 2015, Paus Fransiskus menerbitkan ensikliknya yang berjudul Laudato Si. Dalam ensiklik itu ia menaruh perhatian yang sangat besar terhadap krisis ekologi.
Dalam rangka kesadaran akan krisis ekologi yang sangat parah itu, dengan lantang ia menyerukan gerakan pertobatan ekologis (ecological conversion). Ibu bumi meratap sangat pedih dan sedih. Ratap ibu bumi itu, menurut Boff, kawannya juga, adalah ratap orang miskin. Karena itu, Paus menyerukan gerakan pemulihan lagi rumah kita bersama (ekologi).
Jika selama ini kita selalu omong dalam teologi tentang harapan eskatologis (eschatological hope), maka inilah saatnya kita omong tentang harapan ekologis (ecological hope). Bagaimana peluangnya? Tiada lain jalannya ialah tobat ekologis.
Jika selama ini kita hidup sebagai penjahat-penjahat ekologis (ecological criminals, bajingan ekologis), yang merampok, menjarah ibu kita sendiri, bumi, mother earth, maka inilah saatnya kita mengubah perilaku itu, tidak lagi menjadi penjahat ekologis, melainkan sahabat ekologis untuk bisa membangun peradaban kasih, kebudayaan cinta. Nah, itu caranya. Tidak ada cara lain, sebab kerusakan ekologi kita sudah sangat parah, sudah menjadi the inconvenient truth dalam bahasa Al Gore itu.