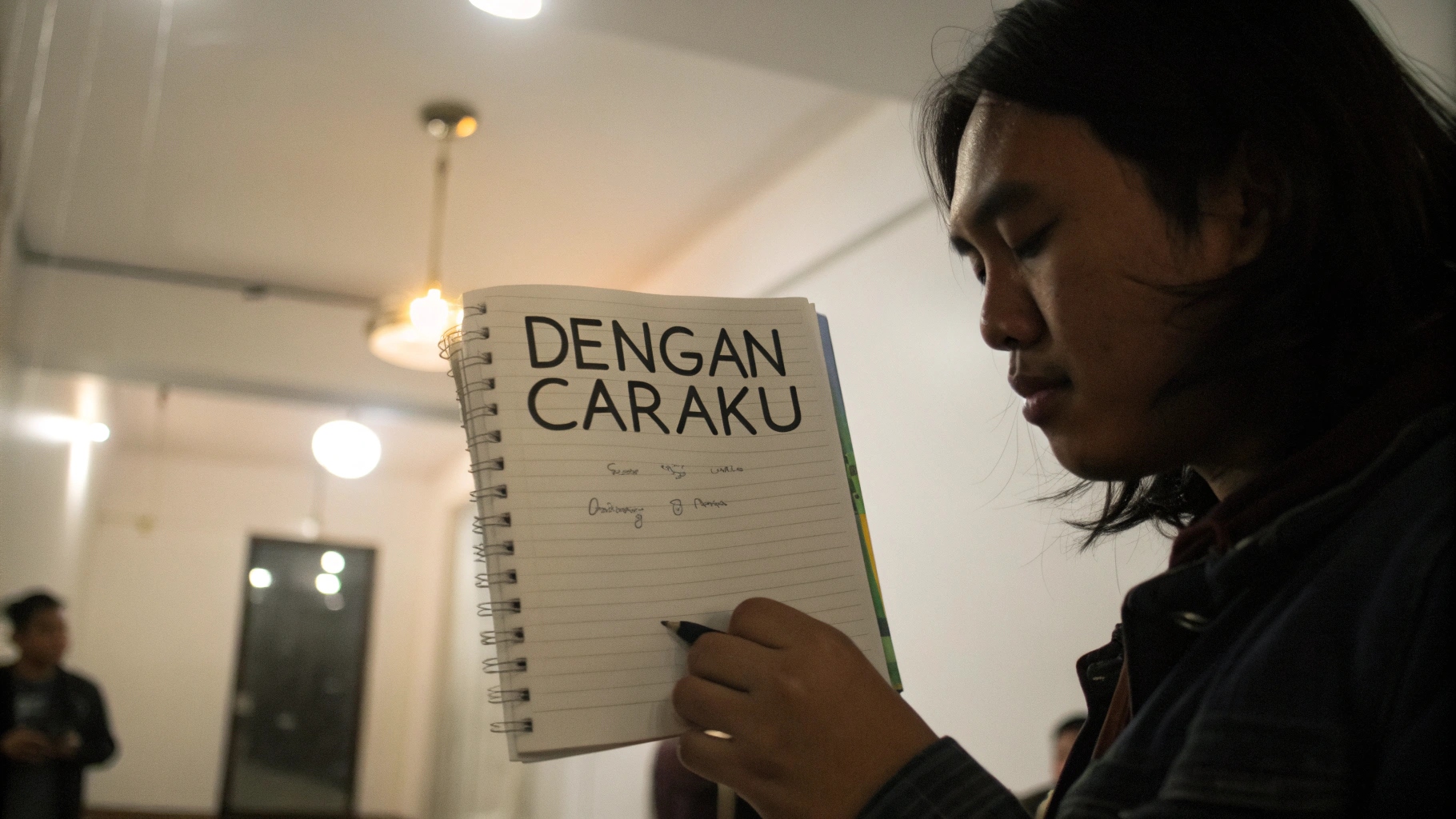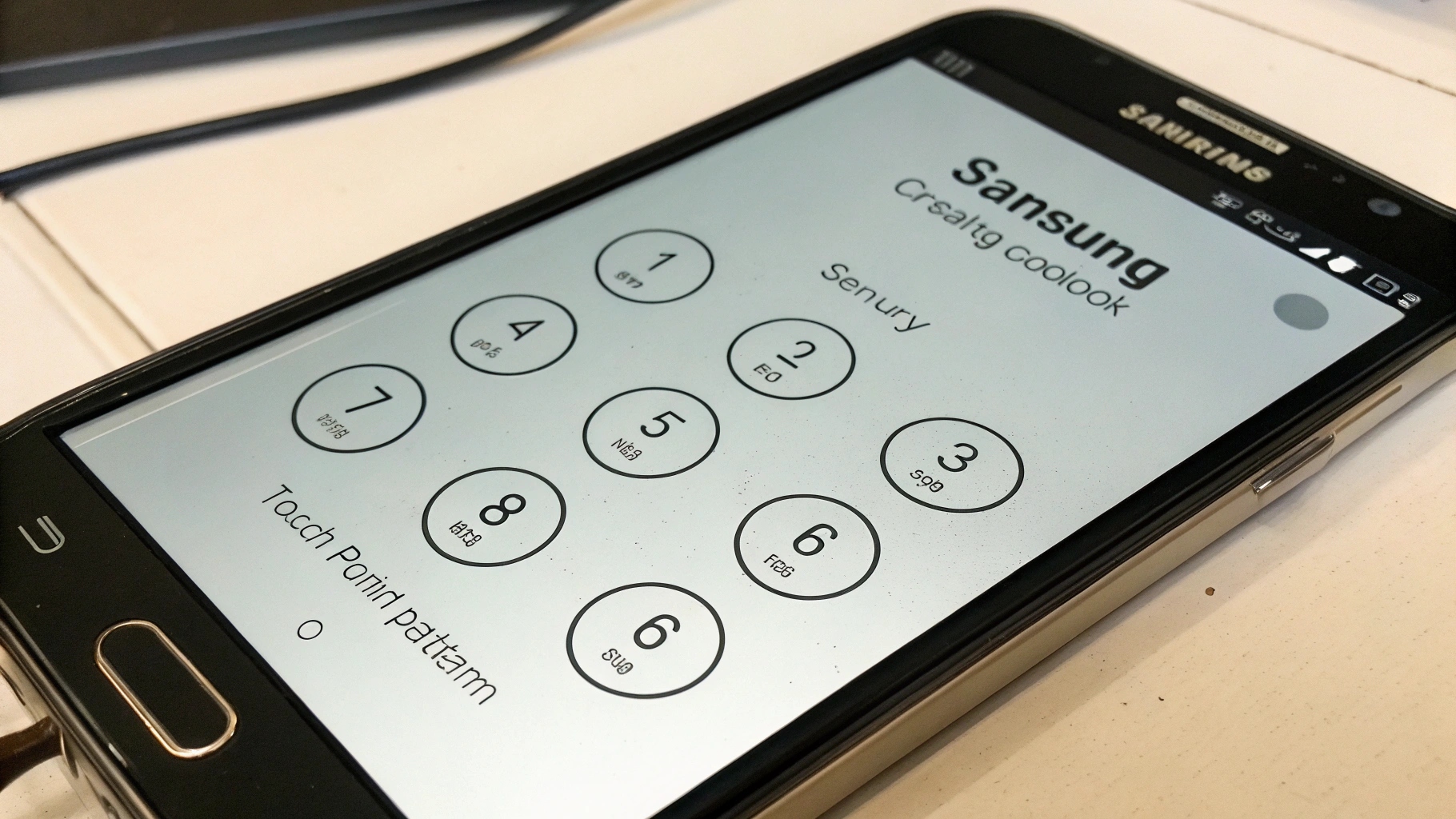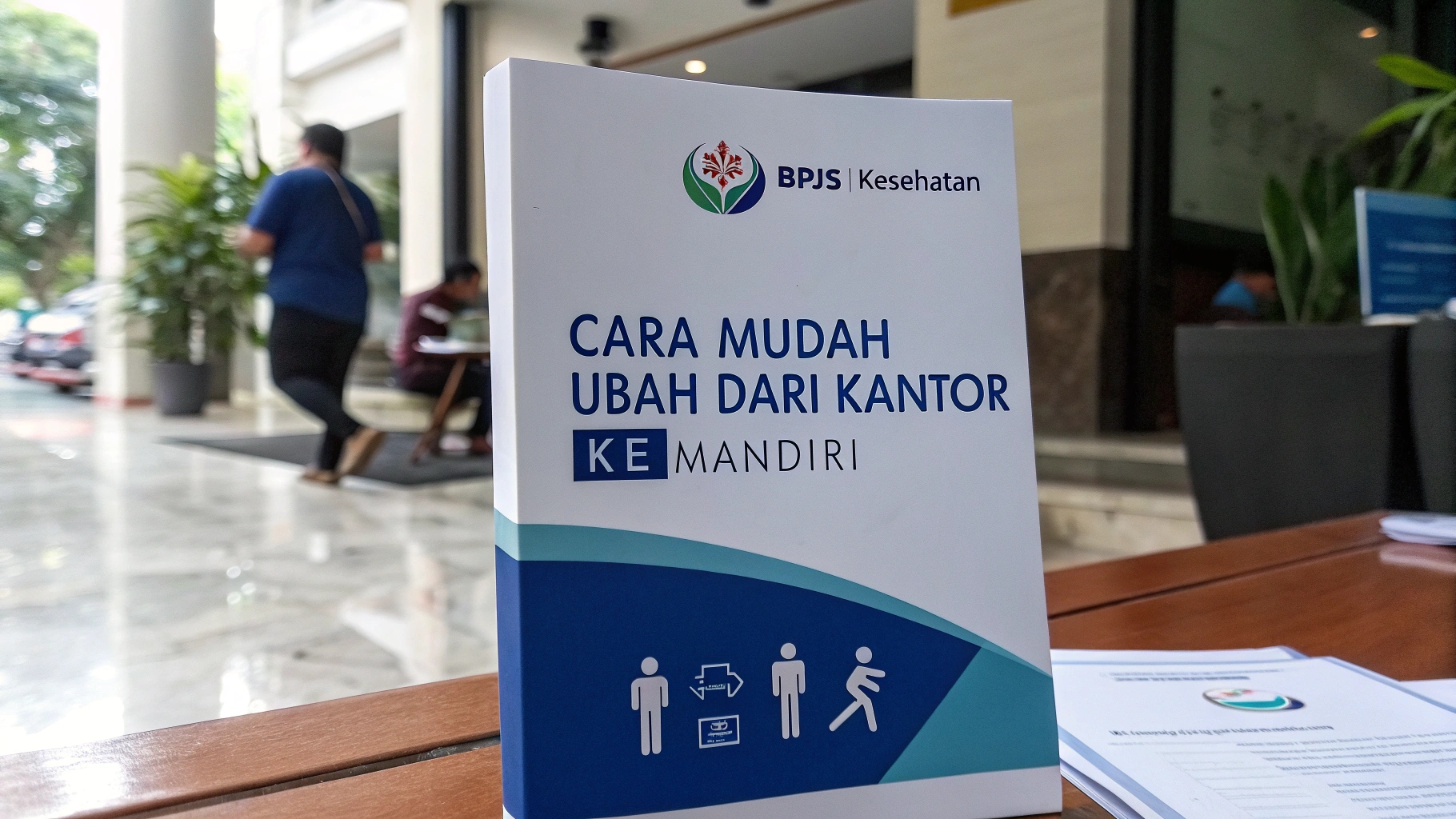Ilustrasi(Antara)
Ilustrasi(Antara)
Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Wahyu Askar, mengungkapkan metode pengukuran kemiskinan yang digunakan Badan Pusat Statistik (BPS) saat ini sudah berusia hampir 50 tahun. Metode tersebut mengacu pada data tahun 1976, sehingga tidak mengalami perubahan signifikan selama lima dekade terakhir.
Padahal, di saat yang sama, banyak negara telah secara aktif meninjau dan memperbarui pendekatan mereka terhadap pembangunan dan program percepatan pengentasan kemiskinan. Hal ini penting karena dinamika sosial dan ekonomi terus berkembang dan tidak bisa disamakan dengan 50 tahun lalu.
"Selama 50 tahun itu tidak ada perubahan yang signifikan mengenai pengukuran data kemiskinan dari BPS," ujar Media dalam webinar 'Sebenarnya Ada Berapa Juta Orang Miskin dan Menganggur di Indonesia?', pada Rabu (28/5).
Dia menuturkan BPS sendiri masih menggunakan pendekatan garis kemiskinan, yang dihitung berdasarkan kebutuhan makanan dan non-makanan. Sederhananya, survei dilakukan dengan mencatat pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan seperti pasta gigi, sabun, transportasi, serta untuk makanan seperti sayur dan telur. Total pengeluaran ini kemudian dibandingkan dengan garis kemiskinan. Jika di bawah garis tersebut, maka rumah tangga dikategorikan sebagai miskin.
"Pendekatan ini telah digunakan sejak tahun 1984, dengan basis data dari tahun 1976. Pertanyaannya kini: apakah metode ini masih relevan digunakan di masa sekarang?" kata Media.
Dia menyebut pada tahun 1970-an, sekitar 70% konsumsi rumah tangga difokuskan pada makanan. Saat itu belum ada ponsel, internet, layanan atau dompet digital, biaya hobi, sewa fasilitas olahraga, dan kebutuhan lainnya juga belum menjadi pengeluaran rutin seperti sekarang. Kini, porsi konsumsi non-makanan telah meningkat signifikan dan bahkan menjadi kebutuhan esensial.
Media kemudian menuturkan BPS menggunakan pengeluaran rumah tangga sebagai indikator utama karena data pendapatan cenderung tidak akurat. Namun pendekatan ini dianggap tidak sesuai dengan realitas saat ini. Seseorang bisa memiliki pengeluaran tinggi, misalnya Rp10-15 juta/bulan, meskipun pendapatan tetap rendah misalnya Rp3 juta/bulan. Dana tersebut bisa didapat dari utang, pinjaman online (pinjol), atau bantuan orang tua.
"Nah, masalah ini seperti cicilan, tidak tercatat dalam data BPS karena yang dihitung hanya pengeluaran saja. Karena pengeluaran yang tinggi tidak mencerminkan kemampuan finansial riil," terangnya.
Kasus sebaliknya, di mana orang kaya bisa saja memiliki gaya hidup yang sederhana dengan makan di warteg, misalnya. Lalu, ada juga pengeluaran pribadi sering kali ditanggung oleh perusahaan atau orang lain, sehingga tidak tercatat dalam survei BPS.
"Akibatnya, terjadi ilusi penurunan kemiskinan, di mana angka statistik tidak mencerminkan kenyataan di lapangan," pungkas Media.
Perbedaan mencolok antara data BPS dan World Bank memperkeruh persepsi publik. BPS mencatat hanya 8,5 persen penduduk Indonesia sebagai miskin (24 juta jiwa), sementara World Bank menyebut hingga 60,3 persen (172 juta jiwa) masuk kategori miskin menurut standar US$6,85 per kapita per hari. Meski metodologi keduanya berbeda, selisih ini menimbulkan kebingungan dan memperlemah kepercayaan publik terhadap data. (E-3)