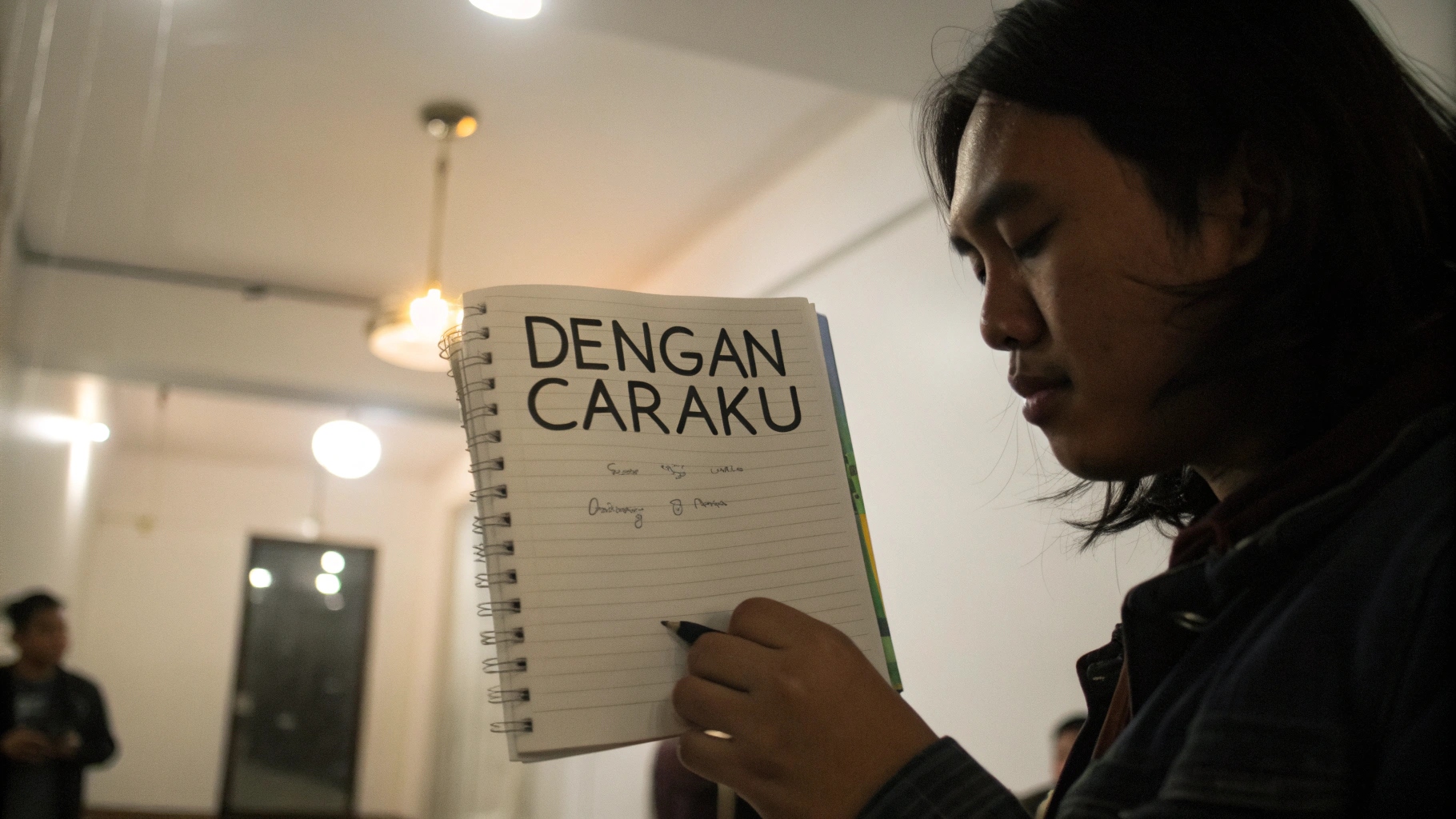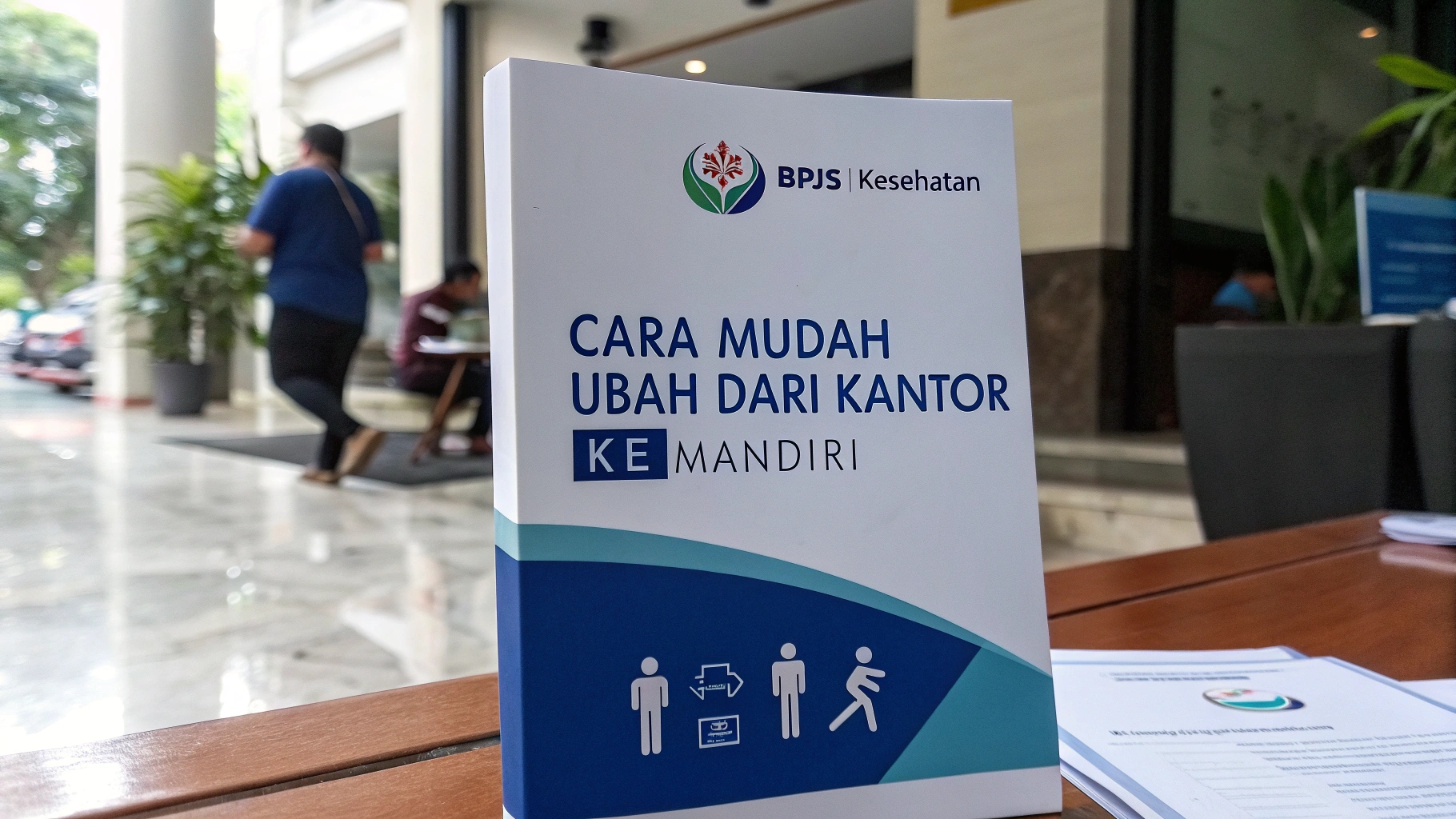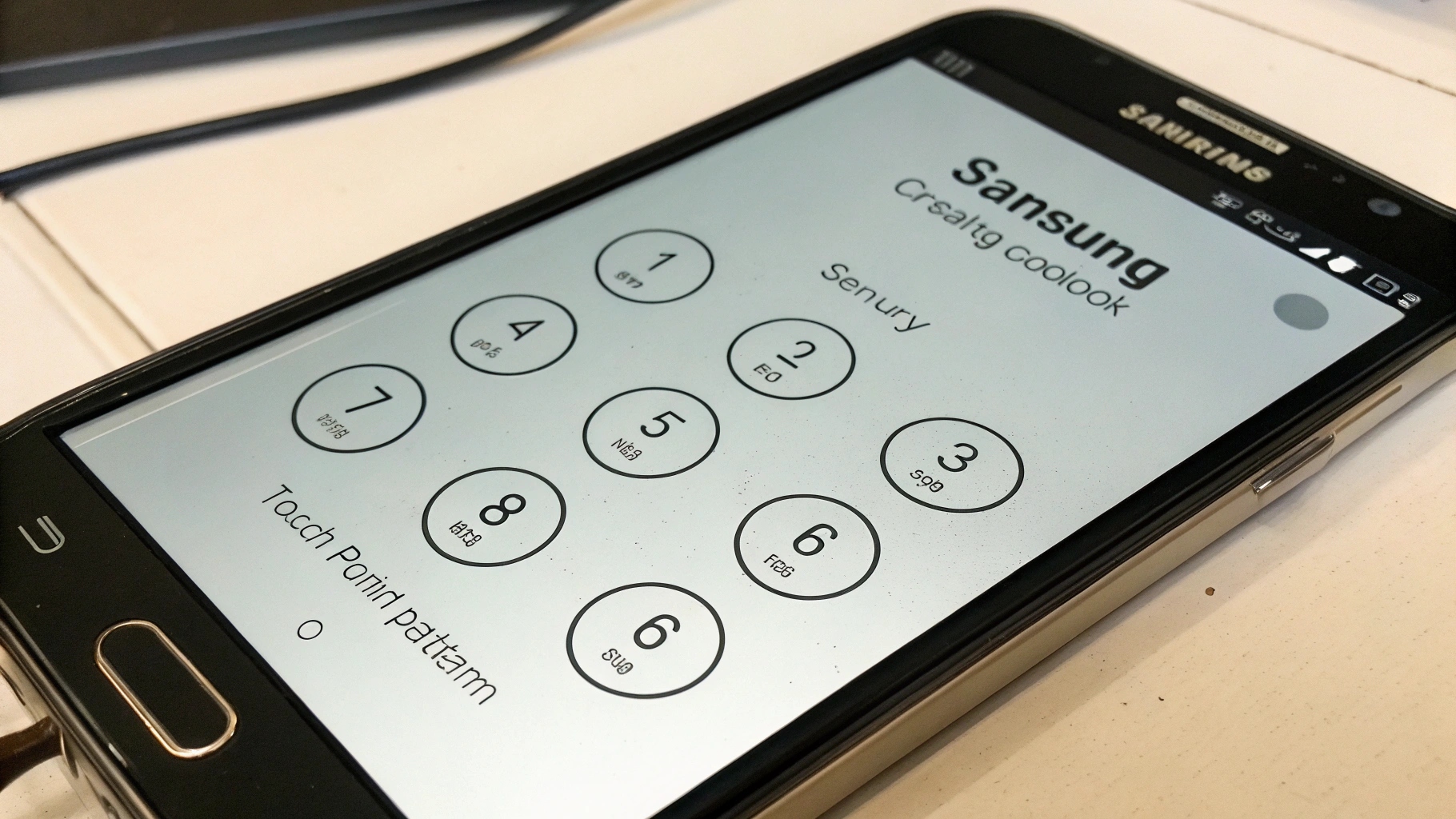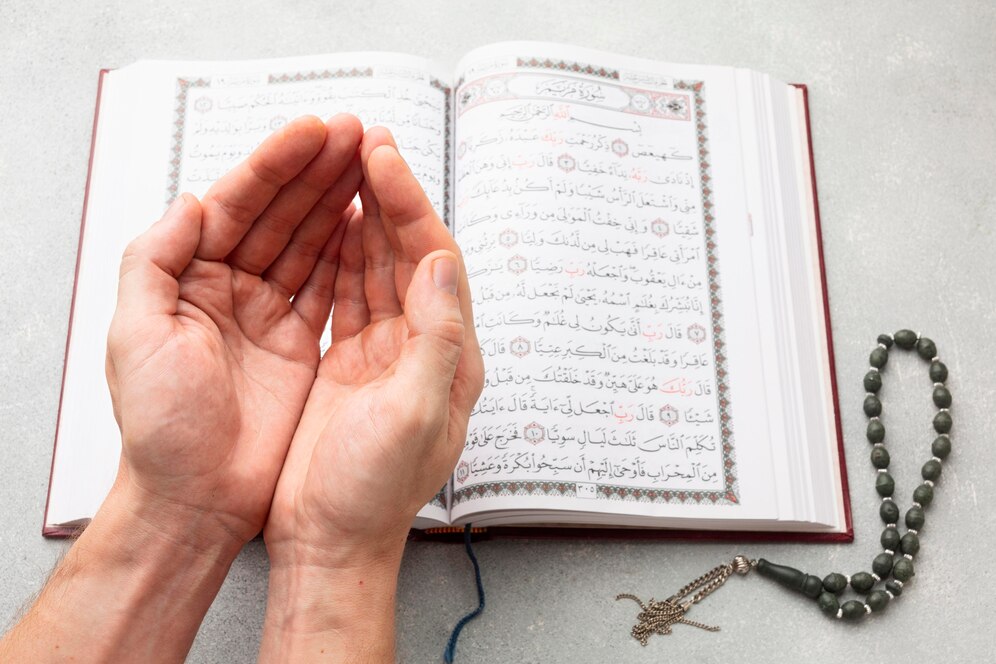Hafidz Muksin, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikdasmen(Dok Badan Bahasa)
Hafidz Muksin, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikdasmen(Dok Badan Bahasa)
APA arti anggaran pendidikan triliunan rupiah jika masih ada ribuan anak yang tidak mampu mengeja namanya sendiri? Pertanyaan ini mencuat saat publik dikejutkan oleh kabar bahwa ratusan siswa SMP di Buleleng, Bali, belum bisa membaca (CNN Indonesia, 15/4/2025). Di tengah era digital dan ledakan informasi, ironi ini menggambarkan jurang yang menganga dalam dunia pendidikan kita.
Sayangnya, ini bukan kasus tunggal. Skor literasi membaca Indonesia dalam survei Programme for International Student Assessment (PISA) 2022 hanya mencapai 359—angka terendah sepanjang sejarah partisipasi kita, dan jauh tertinggal dari negara tetangga. Data Asesmen Nasional (AN) pun tidak lebih menggembirakan: hanya setengah dari peserta didik yang memenuhi standar kompetensi literasi minimum.
Rendahnya kemampuan literasi ini tidak bisa disikapi dengan penyesalan dan saling menyalahkan. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk bergerak—dengan hati, dengan data, dan strategi berkelanjutan. Literasi bukan sekadar kemampuan teknis membaca, melainkan fondasi berpikir dan dasar bagi semua proses belajar—dari memahami pelajaran matematika hingga menjelajahi dunia melalui sains dan sosial.
Oleh karena itu, gerakan literasi harus hadir di ruang kelas dan ruang keluarga. Gerakan ini harus hidup dalam buku cerita yang disukai anak dan sesuai jenjangnya, guru yang terlatih, serta orang tua yang ikut mendampingi. Kita membutuhkan ekosistem yang menyuburkan kegemaran membaca sejak usia dini.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) bergerak aktif menyemai literasi dari hulu ke hilir. Melalui Program Buku Bacaan Bermutu untuk Literasi Indonesia, sebanyak 716 judul buku cerita anak telah diproduksi dan dipilih secara ketat.
Buku-buku ini mencakup cerita rakyat, fabel, dan kisah petualangan yang merangsang imajinasi, hasil karya penulis dan ilustrator lokal, serta terjemahan dari bahasa daerah dan asing. Tujuannya: memberi akses bacaan yang layak dan relevan bagi anak-anak di seluruh penjuru negeri.
Distribusi buku pun dilakukan secara masif. Pada 2022, lebih dari 15 juta eksemplar buku dikirim ke sekolah dasar, khususnya di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Angka ini terus meningkat—hingga 2024, jumlah buku yang disalurkan mencapai lebih dari 21 juta eksemplar. Kini, setidaknya 20.558 sekolah telah menerima kiriman buku. Sekolah-sekolah yang dulu kekurangan bahan bacaan kini mulai memiliki perpustakaan yang hidup kembali, dan sudut baca yang ramai oleh anak-anak.
Namun, buku tidak bisa bekerja sendiri. Literasi tidak tumbuh dari halaman yang diam, melainkan dari interaksi yang hangat. Oleh karena itu pula, Badan Bahasa menyediakan modul pemanfaatan buku yng digunakan untuk pelatihan literasi bagi guru, pustakawan, dan komunitas. Pelatihan ini mencakup metode kreatif, seperti membaca nyaring (read aloud), pengelolaan pojok baca, dan lomba mendongeng.
Melalui Balai Bahasa berkolaborasi dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP), dan Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) di seluruh Indonesia, pelatihan dilakukan di berbagai wilayah. Guru-guru didampingi agar mampu mengintegrasikan kegiatan membaca ke dalam pembelajaran. Tujuannya bukan hanya agar siswa membaca lebih banyak, tetapi agar mereka mencintai kegiatan membaca itu sendiri.
Gerakan literasi juga menyentuh rumah dan komunitas. Program penyuluhan literasi keluarga digulirkan agar orang tua memahami pentingnya membacakan buku cerita di rumah. Di desa-desa, taman bacaan masyarakat (TBM) menjadi ruang inspirasi baru. Terlebih hadirnya program bantuan pemerintah bagi pegiat literasi di seluruh pelosok negeri, telah menguatkan peran TBM dalam menumbuhkan budaya literasi di masyarakat.
Dampak dari kerja kolektif ini mulai terlihat. Di berbagai sekolah, terutama di daerah yang sebelumnya nyaris tidak tersentuh bahan bacaan, perpustakaan yang dulu sepi kini hidup kembali. Di sekolah yang menerima 1.600 buku bacaan bermutu tersebut, terlihat para siswa meminjamnya dengan antusias. Jam istirahat tidak lagi dihabiskan dengan gawai, melainkan diisi dengan membaca mandiri.
Survei Kemendikdasmen pada siswa kelas 1 sampai 3 di sekolah penerima buku menunjukkan peningkatan kemampuan membaca hingga 8 persen dalam beberapa bulan. Indikator formal, seperti AN, juga mencatat kemajuan. SD Negeri 003 Batu Aji di Kepulauan Riau, misalnya, berhasil meraih skor literasi 96,67 dalam AN 2023 dan menerima penghargaan BOS Kinerja. Para guru mengakui, kehadiran buku-buku bermutu telah memperkaya kosakata, meningkatkan rasa percaya diri siswa, memperkuat pemahaman bacaan mereka, dan mulai berpikir kritis.
Memang, semua ini hanya mungkin terjadi karena adanya partisipasi semesta. Pemerintah pusat menyediakan buku dan pelatihan, sementara pemerintah daerah ikut mendistribusikan dan mendukung sarana literasi. Kepala sekolah dan guru menjadi penggerak utama di lapangan. Komunitas literasi, perpustakaan desa, dan TBM menjangkau anak-anak di luar sekolah. Di rumah, orang tua menciptakan kebiasaan membaca yang sederhana, tetapi berdampak besar: membacakan cerita sebelum tidur, menyediakan rak buku kecil, atau menemani anak membaca rutin setiap hari.
Media massa juga berperan penting. Melalui resensi buku, ruang cerita pendek, dan konten literasi digital, dapat menjadi saluran penyebaran budaya membaca yang efektif. Media sosial bisa dimanfaatkan untuk mempopulerkan literasi sebagai gaya hidup.
Budaya literasi tidak tumbuh dari seminar mewah atau sekolah elit, tetapi dari ruang sederhana—tempat anak melihat buku pertama kali, mendengar cerita yang menginspirasi, dan merasakan bahwa membaca itu menyenangkan. Ketika semua elemen bergerak bersama, literasi tidak lagi menjadi sekadar program, melainkan menjadi bagian dari denyut kehidupan. Mari kita mulai dari halaman pertama—dan jangan pernah berhenti membaca. (H-2)