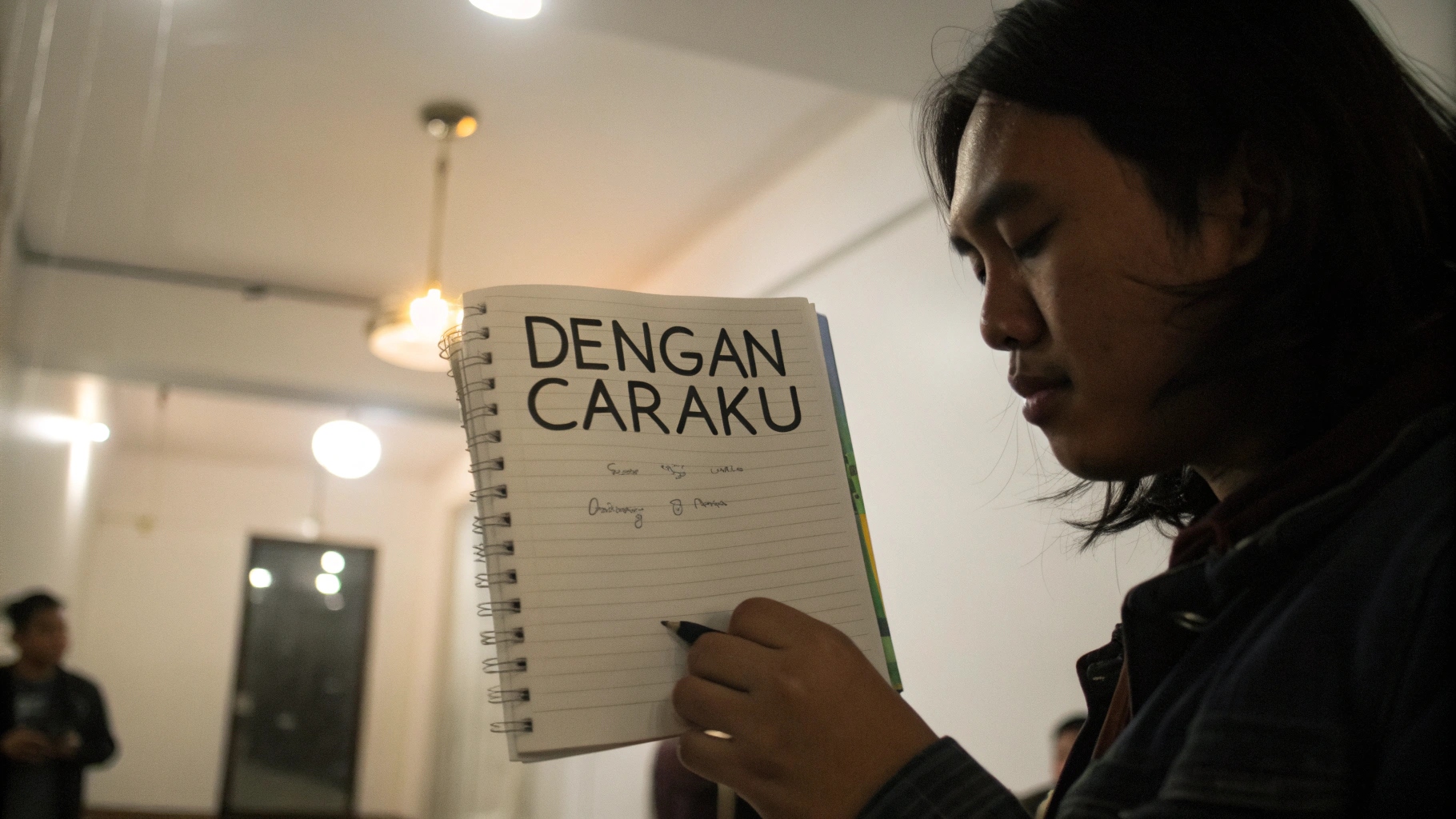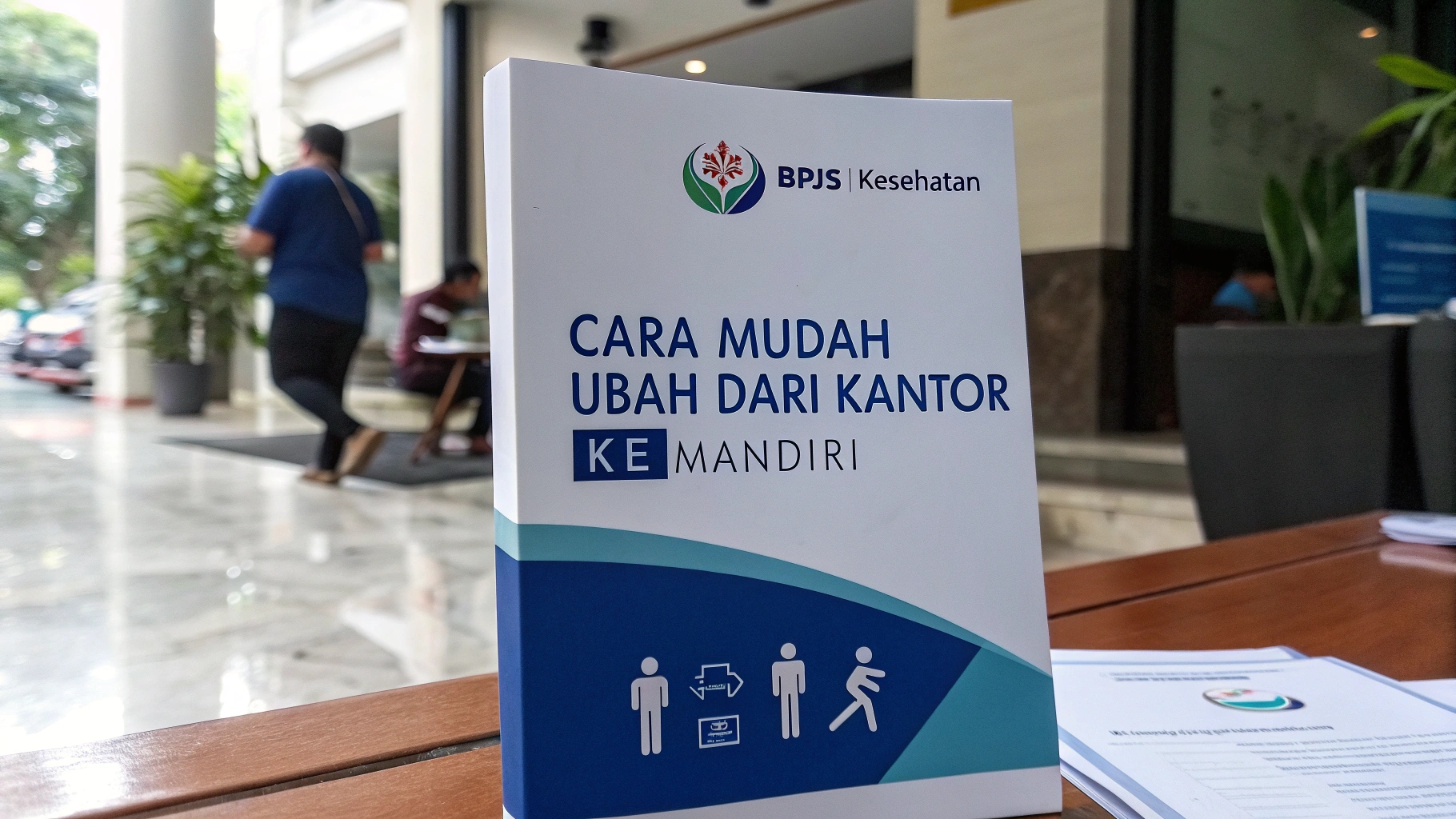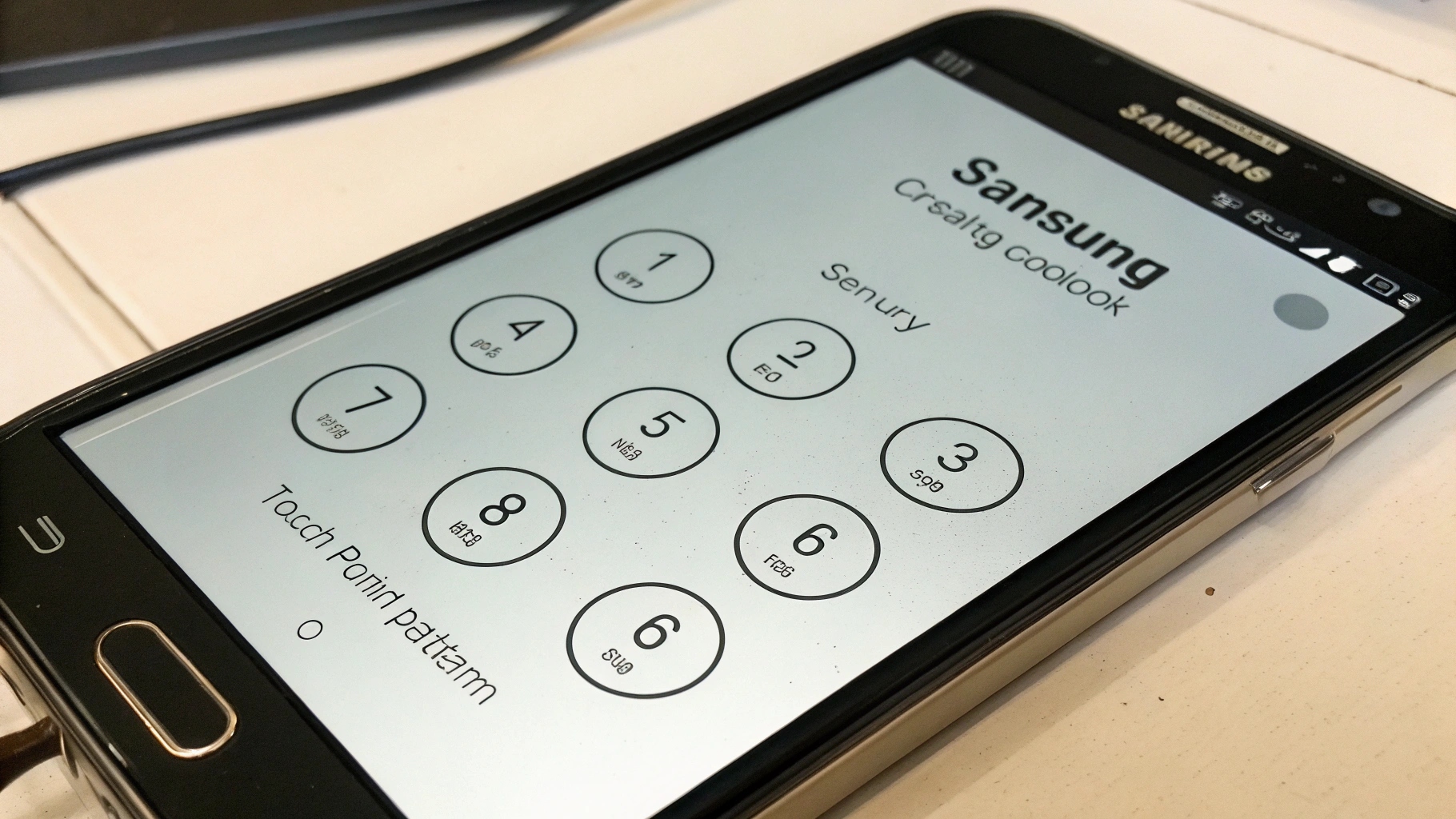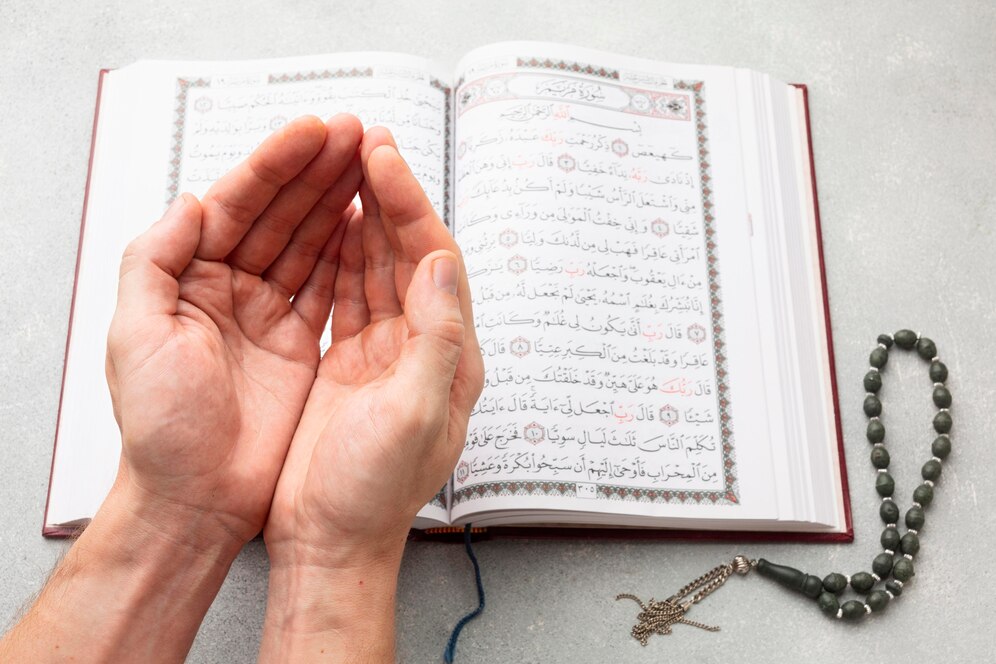MI/Seno(Dok. Pribadi)
MI/Seno(Dok. Pribadi)
"KERUSAKAN bangsa terlampau banyak. Kita pun gagal dalam melihat secara jernih benang merah yang menjadi akar utama masalah bangsa." Kegelisahan yang disampaikan oleh Sukidi, pemikir kebinekaan sekaligus lulusan Harvard University ialah fakta yang tidak bisa terbantahkan. Bahkan, pemerintah telah kehilangan kapasitas untuk melakukan diagnosis akar masalah dan mencarikan solusinya secara komperhensif.
Salah satu penyebab kerusakan Republik ini adalah kegagalan komunikasi publik. Akhir-akhir ini, pernyataan para pejabat publik yang menyakiti hati rakyat serta tidak menunjukkan empati menjadi daftar panjang masalah yang merusak tatanan moral bangsa. Problem komunikasi ini sistemik, bukan hanya terjadi di pemerintah pusat, melainkan juga pemerintah daerah.
Mundurnya Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi atas respons insiden teror kepala babi yang diterima jurnalis Tempo menunjukkan potret ketidakcakapan Istana dalam mengelola komunikasi publik. Meskipun pengunduran diri tersebut ditolak presiden, fenomena itu menjadi indikasi kuat yang mana pemerintah sedang mengalami krisis komunikasi.
Kondisi itu cukup memperihatinkan mengingat komunikasi publik menjadi salah satu hal fundamental dalam mewujudkan sistem demokrasi yang sehat. Komunikasi publik pemerintah kepada rakyatnya yang melibatkan dialog terbuka dan argumentasi rasional (Habermas, 1996).
Komunikasi bukan hanya sekadar penyampaian pesan politik, kebijakan dan program, tetapi jauh lebih subtansi dari itu ialah membangun kepercayaan, menjaga hubungan dengan rakyat untuk memperkuat legitimasi, saling memahami dan penuh hormat (Grunig & Hunt, 1984).
Prabowo Subianto sebagai presiden juga tengah melakukan evaluasi terhadap pola komunikasi pemerintahan. Dalam beberapa pernyataannya di media, Presiden mengingatkan kepada para menteri dan mereka yang diberikan amanah sebagai penyelenggara negara untuk membenahi komunikasi publik.
Namun, alih-alih kepala negara menjadi teladan untuk pejabat publik lainnya dengan menjunjung tinggi etika komunikasi, senada antara laku dan perbuatan, tetapi yang terjadi justru presiden sendiri menunjukkan ketidakpekaan terhadap kondisi rakyat dengan inkonsistensi penyampaian pesan dan pernyataan yang penuh kontroversi.
BAHAYA INKONSISTENSI PESAN
Baru-baru ini, Presiden menyampaikan angka keracunan akibat makan bergizi gratis jumlahnya kecil, hanya 0,005%. Klaim keberhasilan program ini menimbulkan spekulasi di ruang publik dan media, meskipun terhitung kecil berdasarkan angka statistik, tetapi ini adalah nyawa manusia. Sungguh sangat ironis, ketika hal ini muncul dari ucapan presiden. Padahal, di sisi lain, Presiden juga pernah menyampaikan dalam pidatonya siap mati demi bangsa dan rakyat Indonesia sebagai bentuk komitmen membela rakyat. Perilaku komunikasi kontradiktif seperti ini menjadi kekhawatiran diikuti oleh para menteri sampai dengan kepala daerah.
Dalam konteks pemerintahan dan organisasi, inkonsistensi dalam komunikasi dan penyampaian pesan dapat merusak citra dan reputasi organisasi atau individu. Hal itu akan berdampak pada pembentukan persepsi negatif yang sulit diperbaiki dalam jangka waktu yang panjang pada hubungan dengan publik dan stakeholder (Fitzpatrick & Gauthier, 2001). Sebab, audiens menjadi kebingungan dan dapat menghambat pada pemahaman serta pengambilan keputusan yang tepat (McCombs & Shaw, 1972).
Sebagaimana diungkapkan dalam a theory of cognitive dissonance yang dicetuskan oleh Leon Festinger (1957) inkonsistensi pesan juga menimbulkan ketidaknyamanan secara psikologis seperti cemas, bingung, dan tidak nyaman ketika menerima informasi yang bertentangan sehingga cenderung menghindari dan menolak pesan tersebut.
Kebijakan lain misalnya terkait dengan komitmen Presiden terhadap isu pemberantasan korupsi. Presiden memberikan statement siap menghukum mati koruptor. Namun, dalam kesempatan lain pidato di beda tempat kemudian menyampaikan memaafkan koruptor dan meminta keadilan untuk anaknya ketika aset koruptor disita. Itu memperlihatkan bukan hanya terkait dengan buruknya kredibilitas komunikator, tetapi juga ketidakjelasan pesan ini berpotensi menjadi bola liar karena tidak bisa terkomunikasikan dengan baik, implikasinya akan muncul kesalahpahaman dan multitafsir di masyarakat.
Stuckey (2010) dalam artikelnya berjudul Rethinking the Rhetorical Presidency and Presidential Rhetoric menekankan bahwa jabatan presiden ini memiliki kekuatan luar biasa dalam mengartikulasikan atau mendefinisikan identitas nasional dan memajukan kebijakan. Konsep rhetorical presidency selama ini menempatkan retorika Presiden sebagai alat utama dalam membangun hubungan emosional dan mempengaruhi opini publik.
Namun, Stuckey mengkritisi bahwa ketergantungan berlebihan pada retorika tanpa diimbangi dengan tindakan dan kebijakan konkret akan mengarah pada post-deliberative policy making, kondisi yang mana proses pengambilan keputusan menjadi kurang rasional dan dialogis karena didominasi oleh komunikasi yang manipulatif. Semua retorika Presiden juga sangat berorientasi pada institusi dan mengkontsruksi realitas serta norma kepresidenan. Artinya, apa pun yang disampaikan oleh Prabowo Subianto sebagai presiden bukan lagi mewakili pendapat pribadi, kepentingan tertentu dan kelompoknya, melainkan atas nama bangsa (Firmantoro, 2025).
PENTINGNYA KOMUNIKASI DIALOG
Penjelasan komprehensif dan pentingnya mengelola tata komunikasi publik menjadi hal yang sangat krusial. Jika tidak ada protokol komunikasi, akan sangat sulit terbangun model two way symetrical atau model komunikasi dua arah yang simetris untuk bisa menjaga hubungan antara pemerintah dan publiknya (Grunig & Hunt, 1984). Model itu menekankan pada komitmen pentingnya dialog.
Akan tetapi, dalam beberapa kasus, baik itu pemerintah maupun DPR, kerap kali membuat keputusan penting seperti mengesahkan rancangan undang-undang tanpa melibatkan dialog dan meaningfull participation atau partisipasi bermakna dengan masyarakat.
Lebih ironi lagi, ketika rapat digelar di hotel mewah yang semakin sulit diakses. Tranparansi dan akuntabilitas hanya sekadar angan-angan. Publik hanya bisa menyaksikan bagaimana konstitusi cacat prosedur dengan langkah ugal-ugalan. Realitas ini menjadi potret nyata bagaimana pengkhianatan pemerintah dan DPR kepada rakyat dengan membuat kebijakan yang menyengsarakan.
Di situlah kita melihat ada pola komunikasi yang terputus antara pemimpin dengan rakyatnya yang mana pemimpin lebih menonjolkan sikap arogansi dan monolog. Bukan dialog yang terjadi, justru semakin memperlebar jurang komunikasi yang tidak mengedepankan empati kepada masyarakat. Apakah pertemuan Presiden dengan tujuh orang jurnalis itu ialah bentuk dialog yang efektif atau hanya sekedar menggugurkan kewajiban semata?
Deddy Mulyana (2013) dalam karyanya, Komunikasi Politik, Politik Komunikasi, menyampaikan bahwa dialog bukan saja bahasa sebagai medium komunikasi, melainkan juga bahasa dengan makna yang lebih dalam, yakni keinginan, harapan, aspirasi, cita-cita ketakutan, kekhawatiran yang dirasakan mitra dialog.
Dialog yang sebenarnya adalah menyatu dengan rakyat. Melibatkan diri secara intim dan memasuki perspektif serta pengalaman batin mereka. Melalui dialog, individu dapat memahami perspektif orang lain, meningkatkan empati dan membangun kohesi sosial (Buber, 1958). Hal itu senada dengan apa yang diungkapkan Jurgen Habermas dalam bukunya, The Structural Tranformation of Public Sphere (1962), yang mana komunikasi dialog warga secara kritis, bebas dan tanpa paksaan menjadi fondasi demokrasi deliberatif yang sehat dan inklusif.
KEMAMPUAN MENDENGARKAN
Habermas menjelaskan manusia sebagai makhluk rasional melalui dialog dapat menemukan solusi dan bisa menghasilkan perubahan yang positif. Pemimpin dan rakyat berada dalam posisi yang setara. Warga negara terbuka untuk berbicara dan mendengarkan. Sejatinya, baik pemimpin atau rakyatnya harus lebih banyak mendengarkan daripada banyak berbicara. Mendengarkan ialah kemampuan komunikasi terbaik. Ketidakmampuan mendengarkan seperti yang terjadi di Indonesia dan banyak negara lainnya menyebabkan negara tidak akan berkembang maju dan berakibat pada tata kelola pemerintahan yang buruk.
Di tengah krisis keteladanan moral baik di tingkat eksekutif dan legislatif mulai dari pusat hingga daerah, Republik ini betul-betul merindukan sosok pemimpin teladan yang autentik dan berupaya untuk mengubah gaya komunikasi menjadi lebih banyak mendengarkan daripada lebih banyak berbicara untuk memahami kebutuhan dan keinginan masyarakat yang mereka layani sehingga bisa merespon secara tepat. Mendengarkan yang efektif ialah kunci membangun serta memeliharan hubungan, pengambilan keputusan, transparansi dan pemecahan masalah (Steil & Bommelje, 2004; Wolvin, 2010; Rynders, 1999).
Namun, di era teknologi informasi digital seperti saat ini, skill mendengarkan dengan gaya populisme bisa dengan mudah dicitrakan melalui media sosial. Sebagai rakyat, kerap kali dibuat bingung apakah ini benar-benar tulus atau justru ada tujuan dan kepentingan politik hanya sekedar untuk mendapatkan simpati rakyat dengan memanfaatkan kondisi psikologis. Tipe pemimpin seperti ini memang sangat terencana untuk menggunakan strategic image construction agar terlihat citra positif di mata publik. Penggunaan media dan retorika dirancang untuk menciptakan kesan adanya empati dengan rakyat, tapi tidak selalu mencerminkan dengan tindakan nyata.
Penelitian Mazzoleni & Bracciale (2018) yang berjudul Socially Mediated Populism: the Communicative Strategies of Political Leaders on Facebook mengungkap bagaimana pemimpin populis memanfaatkan media sosial dengan retorika dan manipulasi narasi politik untuk membangun hubungan personal dan emosional dengan rakyat tanpa komitmen yang jelas dengan kebijakan yang substansial. Tujuan dari pembuatan kontennya tidak lain hanyalah untuk menambah followers, menaikkan rating, mengejar popularitas dan elektabilitas.
SETOP KOMODIFIKASI RAKYAT
Rakyat hanya sekadar dijadikan sebagai objek untuk dikomodifikasi semata-mata untuk kepentingan politik pragmatis dan menutupi kegagalan kinerja. Kita sendiri kadang sulit membedakan ini pemimpin, conten creator, Youtuber, atau Tiktokers.
Strategi politik pura-pura merakyat itu memang cukup efektif untuk mengelabui rakyat yang secara literasi politik dan digital lemah. Padahal, rakyat tidak butuh konten dan menjadi figuran untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Rakyat butuh sejahtera dan diberikan akses lapangan kerja yang luas. Tipe pemimpin seperti ini setiap turun ke lapangan langsung terekam kamera. Hal itu tentu menjadi tanda tanya apakah benar melakukan kerja nyata, sekadar akting, atau kebutuhan membuat konten?
Jika saat ini banyak pejabat publik yang lebih sibuk membuat konten daripada bekerja, lalu siapa yang mengurus pendidikan, kesehatan, kemiskinan, ekonomi dan pelayanan publik? Permasalahan akan semakin kompleks, ketimpangan sosial parah, pembusukan institusi, pelayanan birokrasi yang korup, kolusi dan nepotisme semakin tumbuh subur. Itu karena pemerintah bekerja untuk kepentingan politik kekuasaan, bukan untuk masyarakat. Jangan sampai rakyat dibutakan dan menyesal di akhir.
Memang sulit kita benar-benar menemukan patriot jujur tanpa pamrih, memiliki persepsi sosial yang akurat, melakukan dialog secara alami, dan berjuang untuk kemajuan Indonesia sesuai dengan cita-cita ideal para pendirinya. Namun, tidak ada kata terlambat untuk para pemimpin bangsa menumbuhkan kesadaran kolektif dalam mengubah arah perjalanan bangsa dengan mengedepankan etika komunikasi publik dan mampu menjadi teladan serta berkorban dengan ketulusan.