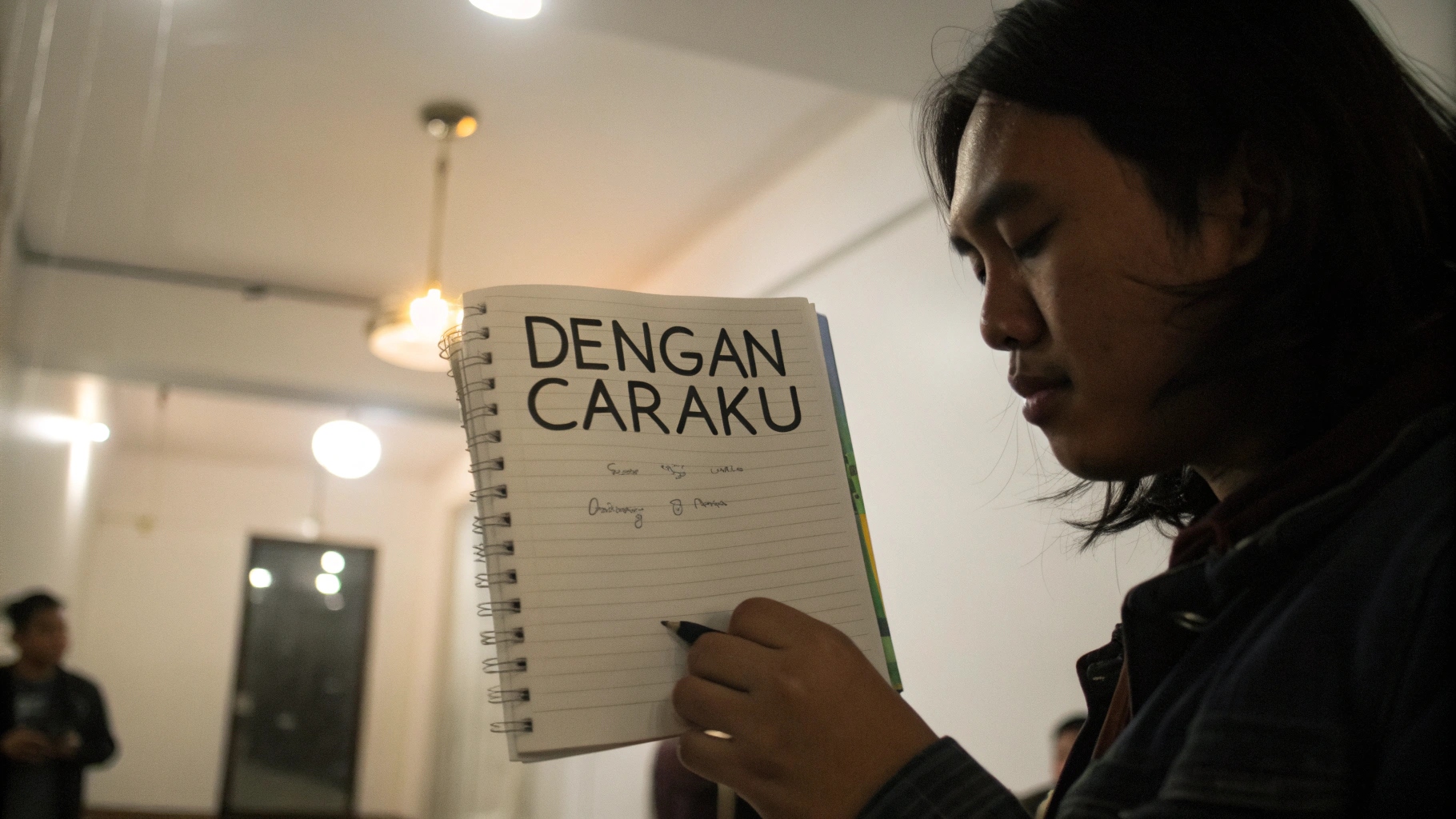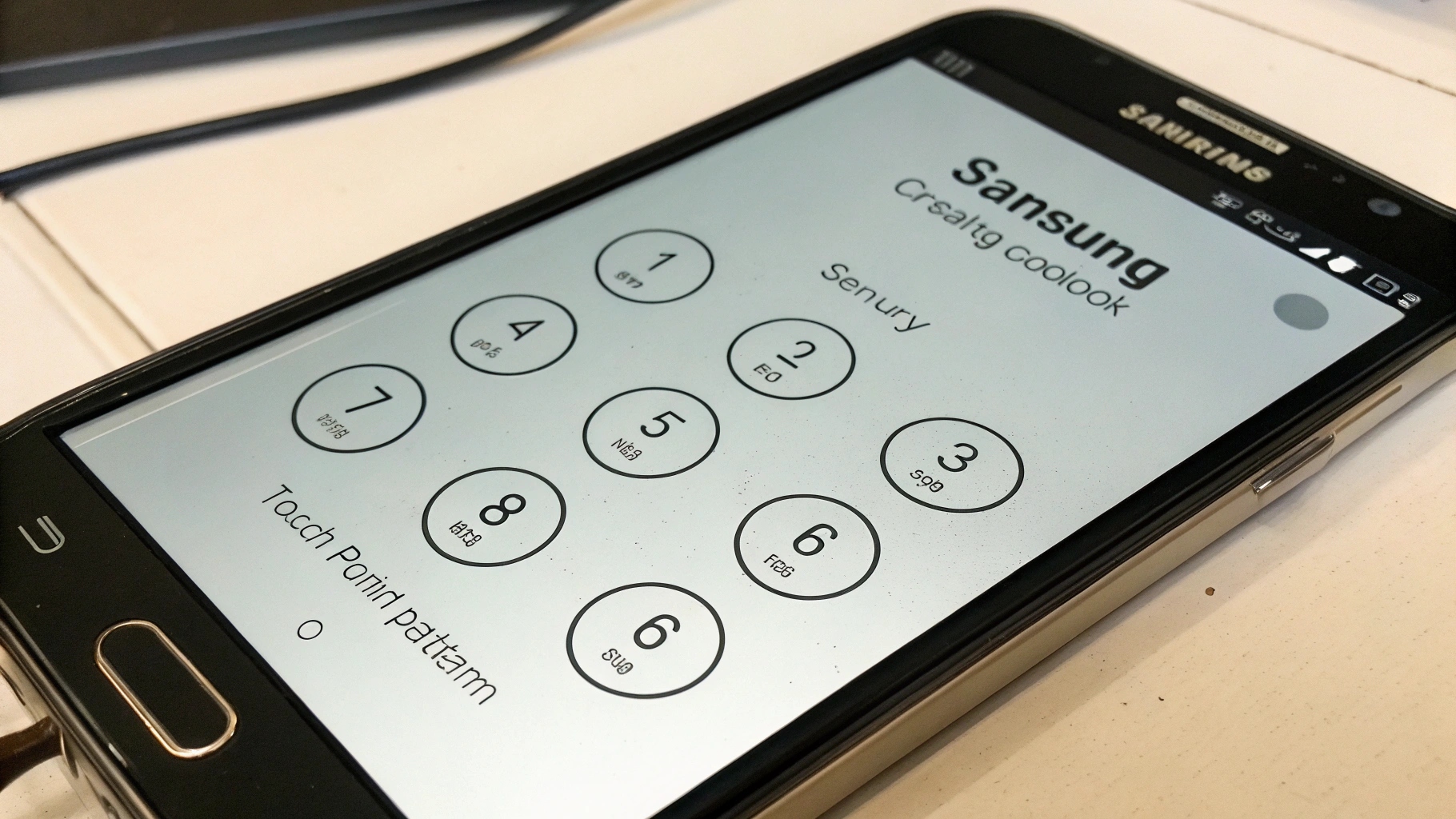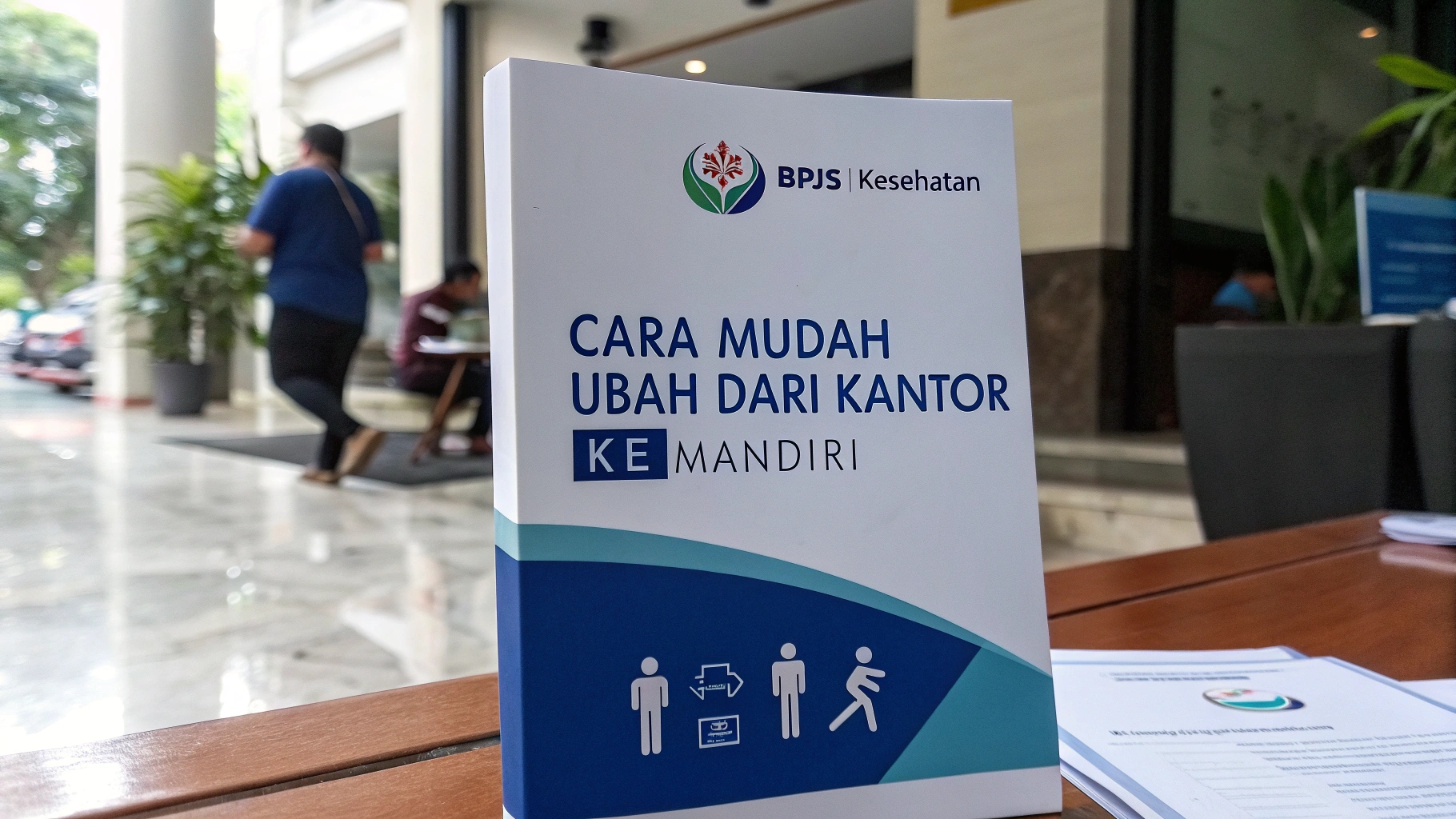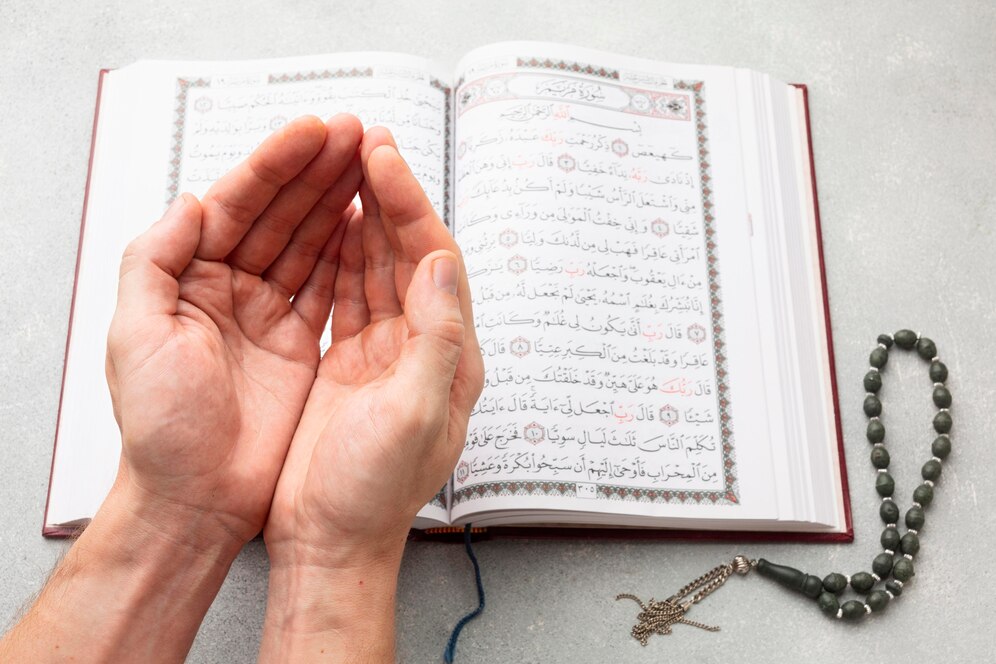(MI/Despian N)
(MI/Despian N)
PASCA disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), sampai saat ini masih terdapat beberapa catatan yang belum dapat teratasi.
Ketua Advokasi Forum Pengada Layanan, Ina Irawati mengatakan bahwa salah satu hal yang belum rampung adalah aturan turunan UU TPKS yang seharusnya ada 7 namun baru 4 yang disahkan.
“Meskipun kita apresiasi proses legislasi, setelah disahkan sampai saat ini yang seharusnya 7 aturan turunan baru ada 4 yaitu Peraturan Presiden nomor 9 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana kekerasan Seksual; Peraturan Presiden nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak; Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2024 tentang Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu dalam Penanganan, Pelindungan dan Pemulihan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Masih ada hal krusial yang belum disahkan sampai saat ini,” ungkapnya dalam Media Briefing bertajuk Menagih Komitmen Negara: Mewujudkan Upaya Pencegahan, Penanganan, Pelindungan dan Pemulihan yang Komprehensif bagi Korban Kekerasan Seksual di Kantor Komnas Perempuan, Jakarta, Kamis (22/5).
Lebih lanjut, menurutnya selama ini lebih dari 50% lembaga di Indonesia sudah memberikan layanan menggunakan UU TPKS. Dari data yang mereka himpun, ada 45,2% lembaga atau organisasi yang sudah menggunakan UU TPKS.
Kemudian ada 43 anggota Forum Pengada Layanan yang mendampingi proses hukum UU TPKS yang mencapai 511 kasus. Jenisnya beragam seperti pelecehan seksual fisik, non fisik, dan kekerasan seksual berbasis elektronik.
“Dari yang kami catat ada 93 putusan dari 511 kasus tersebut dengan pidana beragam antara 4 bulan sampai 14 tahun penjara. Kemudian ada pengalaman di mana eksekusi masih minimal seperti korban menerima restitusi. Kemudian ketika korbannya anak biasanya aparat penegak hukum memprosesnya dengan UU Anak. Pengalaman kami di beberapa daerah aparat penegak hukum masih mempersoalkan belum adanya aturan turunan yang bisa diaplikasikan dalam penanganan kasus,” ujar Ina.
“Di beberapa daerah juga ada penyalahgunaan wewenang sebagai kepala UPTD PPA yang justru melakukan kekerasan. Penggunaan UU lain seperti UU Perlindungan Anak dan UU ITE dirasa memiliki dampak hukum yang lebih besar dibandingkan UU TPKS,” sambungnya.
Ina menegaskan bahwa pemerintah perlu melakukan percepatan penyusunan 3 aturan turunan UU TPKS, di mana prioritas harus diberikan pada regulasi yang krusial untuk implementasi teknis dan operasional di lapangan.
Selain itu, sosialisasi mengenai UU TPKS juga harus dimasifkan dan diperluas, terutama masyarakat di daerah dan wilayah 3T. Materi sosialisasi harus mudah dipahami dan menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk informasi mengenai mekanisme pelaporan dan akses layanan.
“Perlu juga adanya peningkatan alokasi anggaran, pengembangan mekanisme dan sistem koordinasi yang lebih efektif antar lembaga terkait, serta peningkatan kualitas dan kuantitas SDM termasuk penyedia layanan, psikolog klinis dan forensik, ahli gender di seluruh Indonesia agar penanganan kasus TPKS dapat dilakukan secara komprehensif dan merata,” ujar Ina.
Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum mengenai UU TPKS dan penanganan kasus kekerasan seksual juga perlu dilakukan dengan perspektif korban dan disabilitas perlu ditingkatkan. Penggunaan pasal-pasal yang lebih spesifik dalam UU TPKS harus dioptimalkan.
Upaya-upaya untuk mengatasi budaya patriarki dan stigma terhadap korban kekerasan seksual juga perlu ditingkatkan melalui edukasi publik dan kampanye yang berkelanjutan. Dukungan terhadap korban harus dikuatkan agar mereka berani melapor dan mendapatkan keadilan.
KAWAL IMPLEMENTASI
Di tempat yang sama, Ketua Perempuan Mahardhika, Mutiara Ika Pratiwi menambahkan bahwa pihaknya mengambil fokus untuk mengawal implementasi UU TPKS di dunia kerja. Kekerasan seksual yang terjadi di dunia kerja dikatakan telah dipengaruhi oleh ketidak-setaraan relasi kuasa gender dan atas pekerjaan sehingga menempatkan perempuan pekerja pada posisi rentan.
“Kepmenaker 88/2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang menindaklanjuti UU TPKS di tempat kerja belum tersosialisasi secara maksimal. Pembentukan Satgas PPKS sebagai mandat dari Kepmen tersebut terbentuk baru hanya di sebagian kecil tempat kerja, dan belum sepenuhnya mendapat dukungan dari pemerintah maupun perusahaan,” tegas Ika.
Sosialisasi merupakan bagian penting dari aspek penceganan. Namun begitu, dalam konteks dunia kerja, kebutuhan sosialisasi masih sering terganjal dengan sistem kerja berbasis target yang berlaku di perusahaan atau tempat kerja. Sinergi multi-pihak yang gaungkan pada masa awal pengesahan UU belum berjalan secara maksimal.
Satgas PPKS di tempat kerja berdasarkan Kepmen 88/2023 meliputi unsur dari perwakilan manajemen perusahaan, buruh dan serikat pekerja. Namun hingga saat ini pembentukan Sataas PPKS belum berjalan secara maksimal. Pemerintah perlu memperkuat monitoring dan pengawasan.
“Peristiwa intimidasi kepada pendamping korban bukanlah hal baru. UU TPKS menjamin bahwa pendamping berhak mendapatkan perlindungan hukum selama mendampingi korban. Komitmen negara dibutuhkan untuk menjamin hak tersebut,” jelasnya.
KASUS FEMISIDA
Sementara itu, Direktur Proyek Jakarta Feminist, Anindya Restuviani mengatakan bahwa sampai saat ini, telah terdapat 180 kasus femisida di 38 provinsi di Indonesia dengan total 187 korban dan 197 pelaku. Pada 2023, pihaknya telah menemukan 145 kasus femisida dengar korban cis-puan, 6 kasus femisida dengan korban transpuan, 12 kasus pembunuhan anak perempuan, dan 17 kasus tindak kriminal dengan korban perempuan.
“Kasus pembunuhan terbanyak (42%) terjadi di pulau Jawa, dengan jumlah kasus terbanyak dilakukan di Jawa Timur (24 kasus), Jawa Barat 22 Kasus, Jawa Tengah 14 kasus. Gorontalo Papua Selatan, dan Sulawesi Tenggara tidak ditemukan kasus femisida,” ucap Anindya.
“Dalam kelompok korban, 32% korban merupakan perempuan di rentang usia 26-40 tahun. Dalam kelompok pelaku, 94% pelaku berjenis kelamin laki-laki. 36% pelaku berada dalam rentang usia 26-40 tanun. Sebanyak 13% korban memiliki relasi keluarga dengan pelaku. Para korban dalam relasi ini adalah anak, ibu, kakak, adik, dan saudara keluarga lain,” sambungnya.
RELASI INTIM
Perempuan yang memiliki relasi intim dengan pelaku dikatakan menjadi korban paling banyak dalam kasus femisida. Mereka adalah istri, pacar, selingkuhan, kekasih gelap, mantan, dan teman kencan.
Selain itu, beberapa korban adalan orang-orang yang memiliki hubungan non-personal dengan pelaku seperti tetangga, teman, pekerja seks, teman kerja, pelajar, dan sebagainya.
“Motif pembunuhan dari kasus-kasus ini sebagian besar terjadi karena adanya problem komunikasi. Mirisnya ada dua kasus di mana korban dibunuh karena pelaku justru tidak terlibat masalah dengan korban tetapi kesal karena dimarahi dan cekcok dengan suami dan ayah dari masing-masing korban,” kata dia.
Salah satu kejadian menarik dari kasus femisida adalah seorang pria, anak anggota DPR RI, menganiaya pacarnya (29) hingga tewas. Pemberitaan menunjukkan penyiksaan brutal yang sengaja dilakukan untuk menimbulkan penderitaan fisik dan psikis termasuk pemukulan, pelindasan dengan mobil, perekaman disertai ejekan, hingga akhirnya korban dimasukkan ke dalam bagasi mobil dan dibawa ke apartemen sebelum kemudian ke rumah sakit. Sayangnya, korban sudah meninggal 30-45 menit sebelum tiba di ruman sakit.
Kendatipun laporan media yang detail, bukti CCTV, dan visum et repertum menunjukkan luka akibat benda tumpul dan bekas lindasan mobil telah memperlihatkan kekerasan yang jelas, hakim Pengadilan Negeri Surabaya tetap memvonis bebas pelaku.
“Melihat dari hal ini, pemerintah perlu mencabut atau revisi peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah yang diskriminatif terhadap perempuan. Mengintegrasikan UU PKDRT dan UU TPKS dengan aturan pidana pembunuhan misalnya, Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 352 Ayat 2 tentang penganiayaan berat berencana. Integrasi ini penting untuk memberikan pemberatan hukuman bagi pelaku femisida dan mengakui femisida bentuk kekerasan berbasis gender yang membutuhkan respons hukum yang lebih komprehensif,” tegas Anindya.
“Bagi aparat penegak hukum, diperlukan pengelolaan data kasus pembunuhan berdasarkan gender korban untuk memantau dan menganalisis tren femisida serta mendorong perbaikan kebijakan,” pungkasnya. (Des/H-1)