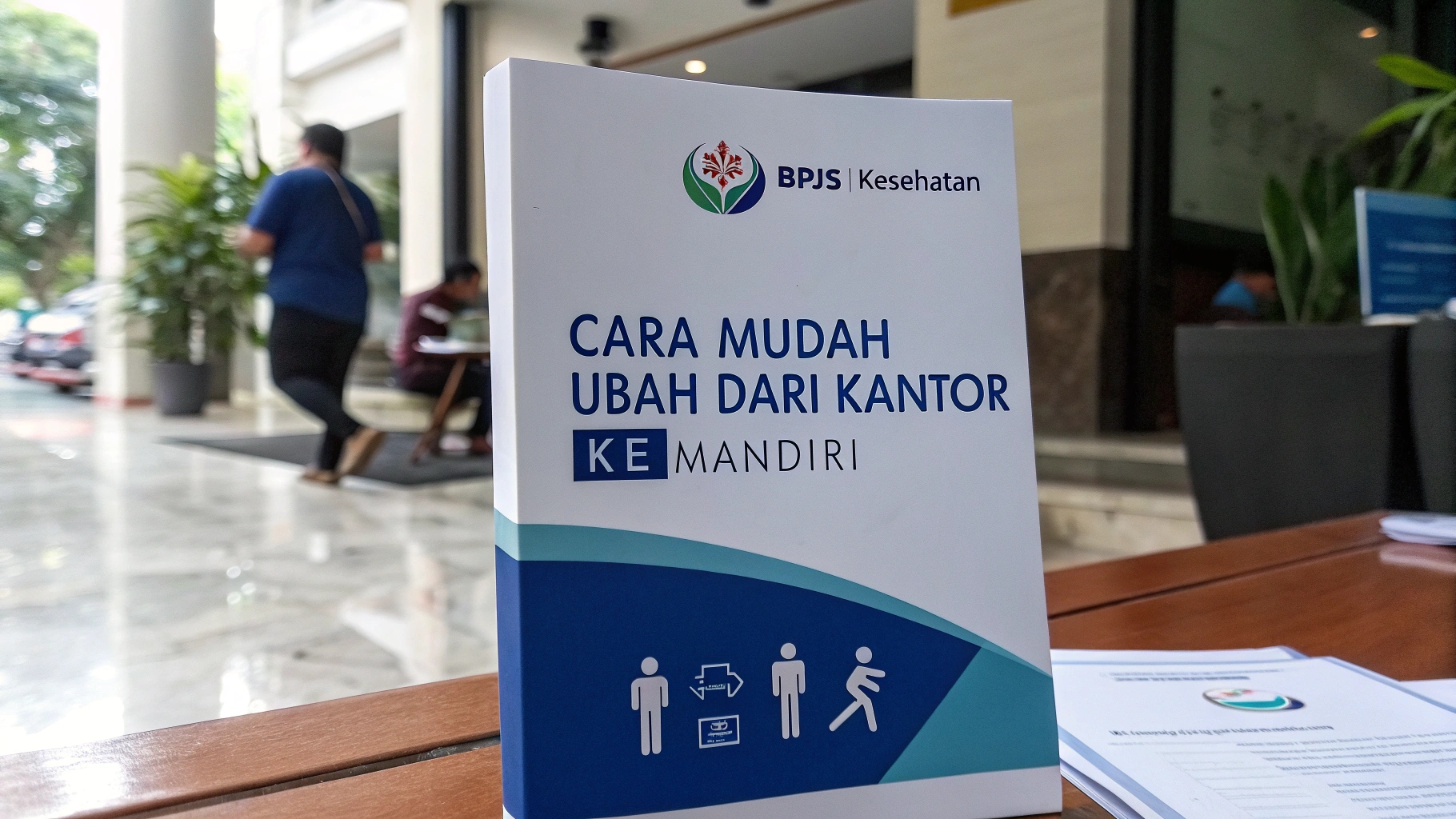(MI/Seno)
(MI/Seno)
DALAM politik global, kekuasaan bukan lagi sekadar tentang peluru, melainkan juga tentang persepsi. Tentang bagaimana risiko direkayasa, bukan untuk dihindari, melainkan untuk dijual. Di dunia yang digerakkan oleh narasi, tarif menjadi puisi yang ditulis dengan bahasa ekonomi. Seperti biasa, Donald Trump tidak datang membawa kebaruan, tetapi kemampuan lama yang dibungkus ulang: membuat pasar percaya bahwa ancaman bisa menjadi solusi.
MOTIF LEBIH TERSEMBUNYI
Sejak awal 2025, gelombang kebijakan tarif kembali didorong dari Gedung Putih. Targetnya bukan hanya Tiongkok, melainkan juga Indonesia, Uni Eropa, dan bahkan Kanada serta India. Retorika America first kembali digaungkan, seolah dunia tidak pernah belajar dari luka yang sama beberapa tahun silam.
Namun, kali ini motifnya lebih tersembunyi. Jika kita cermati, lonjakan tarif selalu beririsan dengan kenaikan yield US treasury tenor 10 tahun. Pada 8 April, ketika yield menyentuh ambang 4.5%, Trump mengumumkan tarif halt terhadap puluhan negara--kecuali Tiongkok. Lalu, pada 12 Mei, ketika yield kembali naik, Washington dan Beijing tiba-tiba sepakat menurunkan tarif bilateral sebesar 115 basis poin selama 90 hari. Korelasi itu terlalu presisi untuk dianggap kebetulan.
Di balik teatrikalitasnya, Trump sedang memainkan skenario fiskal terselubung. Dengan utang federal AS melampaui US$36 triliun dan defisit anggaran yang semakin dalam akibat rencana pemotongan pajak, pemerintah menghadapi tekanan untuk membiayai utang dengan yield yang semakin mahal.
Dalam logika pasar, menciptakan ketegangan global akan mendorong arus modal ke aset aman seperti US treasury, menurunkan yield dan meringankan beban fiskal. Maka itu, tarif bukan hanya instrumen dagang, melainkan juga alat pengendali pasar obligasi. Strategi itu bukan bagian dari kitab ekonomi konvensional, melainkan nyatanya berjalan efektif--selama The Fed meresponsnya dengan nada dovish.
Namun, di sinilah letak paradoksnya. Jika inflasi justru terpicu akibat kenaikan harga barang impor, The Fed tidak punya banyak ruang untuk menurunkan suku bunga. Bahkan, bisa jadi sebaliknya. Ketika retorika tarif tidak lagi membuat investor merasa aman, yield bisa melonjak lebih tinggi--dan seluruh strategi fiskal Trump runtuh oleh tekanan pasar yang tak lagi percaya pada ilusi risiko.
Ancaman berikutnya datang dari Eropa. Dengan rencana mengenakan tarif hingga 50% terhadap ekspor otomotif, baja, dan pertanian dari Uni Eropa, Trump tampaknya tengah memainkan kartu lama kepada lawan yang baru. Namun, berbeda dengan Tiongkok, Eropa memiliki sejarah diplomasi panjang dengan AS, tertanam sejak Marshall Plan pasca-Perang Dunia II.
Uni Eropa kemungkinan akan memilih jalur negosiasi, bukan konfrontasi langsung. Itu bukan karena lemah, melainkan karena mereka memahami bahwa stabilitas jangka panjang lebih penting daripada kemenangan jangka pendek. Ketegangan itu, meski ditahan dalam diplomasi, tetap akan memicu sentimen risiko global.
DAMPAK BAGI INDONESIA
Bagi Indonesia, dampak dari kebijakan itu muncul dalam dua wajah. Di satu sisi, tarif terhadap produk ekspor unggulan seperti CPO, tekstil, karet, alas kaki, dan furnitur akan menggerus potensi penerimaan ekspor. Dalam simulasi Samuel Sekuritas, tarif 34% terhadap barang Indonesia dapat mengganggu hingga US$20,1 miliar nilai ekspor.
Bahkan, dalam skenario tarif moderat 10%, Indonesia tetap berpotensi kehilangan US$2,96 miliar. Ini bukan hanya angka neraca dagang, melainkan juga menyangkut mata pencaharian ratusan ribu pekerja di sektor padat karya. Sejak 2024, lebih dari 100 ribu buruh telah terkena PHK dan tensi tarif baru hanya akan memperpanjang daftar luka.
Namun, di sisi lain, terbuka ruang untuk menjadi penyeimbang dari disrupsi Tiongkok. Ketika AS menutup pintu bagi produk Tiongkok, Indonesia bisa mengambil alih ceruk tersebut. Dalam simulasi tarif 100% terhadap Tiongkok, Indonesia berpeluang menambah ekspor hingga US$11,4 miliar, khususnya pada alas kaki, tekstil, furnitur, dan bahkan rare earth metals--yang selama ini belum termanfaatkan optimal. Beberapa perusahaan seperti PT Hwa Seung dan PT Parkland bahkan tercatat sebagai eksportir utama alas kaki ke AS dan bisa mendongkrak kapasitas produksi jika dukungan kebijakan diberikan.
Namun, perlu diingat, peluang ini tidak otomatis. Diperlukan kecepatan dalam reformasi logistik, efisiensi rantai pasok, dan perbaikan ekosistem industri. Tanpa itu, kesempatan hanya akan lewat sebagai angka di kertas simulasi.
DAMPAK BAGI PEREKONOMIAN GLOBAL
Dampak terhadap perekonomian global pun tidak bisa diabaikan. Setiap putaran tarif akan mengurangi efisiensi ekonomi, menaikkan biaya produksi, dan memperlambat perdagangan. Dalam jangka menengah, World Bank dan IMF telah mengoreksi proyeksi pertumbuhan global ke bawah akibat tekanan ini.
Ketidakpastian yang timbul dari kebijakan tarif akan menahan belanja investasi, memperlambat permintaan global, dan pada akhirnya menyeret pertumbuhan banyak negara, termasuk Indonesia. Bahkan, dalam skenario tarif lanjutan dan retaliasi Eropa atau Tiongkok, pertumbuhan ekonomi dunia bisa turun di bawah 2%, mendekati garis tipis antara ekspansi dan stagnasi.
Bagi Indonesia, tantangan terbesar ada pada transmisi ke permintaan domestik. Dengan tekanan terhadap ekspor, disrupsi sektor manufaktur, dan tekanan nilai tukar yang dapat menurunkan daya beli, pertumbuhan ekonomi Indonesia berisiko terkoreksi. Proyeksi 5% tahun ini bisa bergeser ke kisaran 4.7%-4.8%, terutama jika harga komoditas turut terpukul dan realisasi belanja pemerintah terhambat.
Dalam konteks itu, BI dan otoritas fiskal harus cermat membaca dinamika global. Tekanan yield, volatilitas nilai tukar, dan perlambatan ekspor harus dijawab dengan bauran kebijakan yang bukan hanya reaktif, tetapi juga struktural. Di sisi lain, diplomasi dagang harus ditingkatkan, baik melalui forum multilateral seperti ASEAN dan APEC maupun kanal bilateral dengan AS dan Eropa. Indonesia harus mengubah posisi dari hanya sekadar reaktif terhadap tarif menjadi aktor aktif dalam merancang peta jalan perdagangan barunya.
Tarif tidak lagi hanya soal bea masuk. Ia kini telah menjelma sebagai ekspresi ketegangan struktural dalam perekonomian global--antara fiskal dan moneter, antara geopolitik dan pasar, antara narasi dan realitas. Dalam ruang inilah kebijakan ekonomi harus dibangun bukan hanya dengan kalkulasi makro, melainkan juga dengan sensitivitas terhadap dinamika narasi global.
Tarif, dalam bayangan publik, mungkin terlihat sebagai urusan bea dan cukai semata. Namun, hari ini, ia telah menjelma menjadi cerita besar tentang arah dunia. Ia bukan lagi sekadar instrumen ekonomi, melainkan simbol dari pergeseran kekuasaan global dari rasa percaya yang semakin menipis antarnegara, dan dari kecemasan tentang masa depan yang makin sulit diprediksi.
Trump, dengan segala kontroversinya, memahami satu hal yang sering luput dari para teknokrat: pasar dan politik bukan soal angka saja, tapi soal rasa. Soal narasi. Dengan memainkan rasa takut, dia menciptakan permintaan. Dengan menciptakan musuh, dia mengundang simpati. Dengan mengatur tempo ancaman serta 'diskon' tarif, dia membentuk persepsi yang mampu menggoyang yield, menggeser pasar, dan memengaruhi agenda kebijakan negara-negara lain, termasuk kita di Indonesia.
Bagi negara berkembang seperti Indonesia, kita tak punya kemewahan untuk bersikap reaksioner terus-menerus. Kita harus mulai menyusun strategi, bukan hanya kebijakan tambal sulam. Harus ada transformasi serius, baik di sisi ekspor, logistik, maupun kemampuan kita membaca arah angin global. Karena dalam dunia yang makin penuh ketidakpastian ini, yang lambat bukan hanya tertinggal, melainkan bisa tertelan.
Ekonomi bukan hanya soal pertumbuhan angka-angka makro. Ia soal harapan. Soal ibu-ibu di Karawang yang takut pabrik tempat mereka bekerja akan tutup karena pesanan dari AS dihentikan. Soal anak-anak muda yang berjuang membuat UMKM menembus pasar luar negeri, tapi terus tersandung tarif dan hambatan dagang yang tak masuk akal. Soal investor yang mulai ragu, bukan karena fundamental kita lemah, melainkan karena arah kebijakan global makin tak rasional.
MEMAINKAN SIMFONI KITA SENDIRI
Dalam dunia yang sedang mencari pegangan, Indonesia seharusnya bisa tampil sebagai jangkar stabilitas. Namun, itu hanya mungkin jika kita berani membuat peta jalan baru. Bukan dengan mengikuti ritme ancaman dari Washington atau Beijing, melainkan dengan memainkan simfoni kita sendiri--berbasis pada keunggulan, kecepatan adaptasi, dan keberanian mengambil keputusan jangka panjang.
Pada akhirnya, yang menentukan bukan seberapa keras dunia mengguncang, melainkan seberapa kokoh fondasi yang kita bangun. Dalam dunia yang makin kacau ini, bangsa yang mampu bertahan bukan yang terkuat atau terkaya, melainkan yang paling lincah membaca arah perubahan, dan paling cerdas menulis ulang naskahnya sendiri.
Pada akhirnya, seperti yang pernah dikatakan Keynes, "Pasar bisa tetap irasional lebih lama daripada Anda bisa tetap berdaya." Namun, dalam dunia hari ini, yang irasional bukan lagi pasar, melainkan kebijakan dan justru karena itu kebijakan ekonomi harus menjadi jangkar di tengah arus politik global yang makin sulit ditebak.