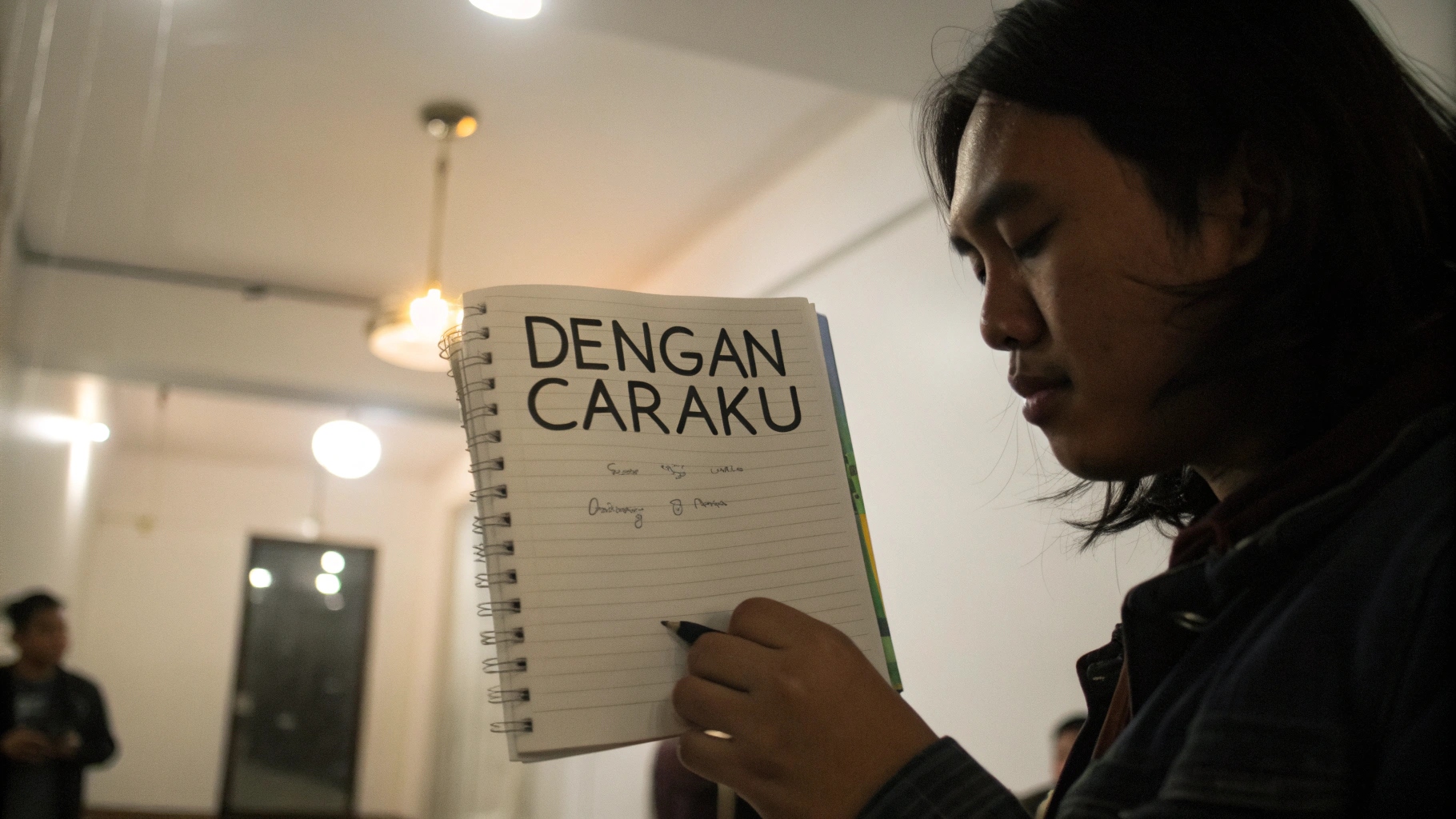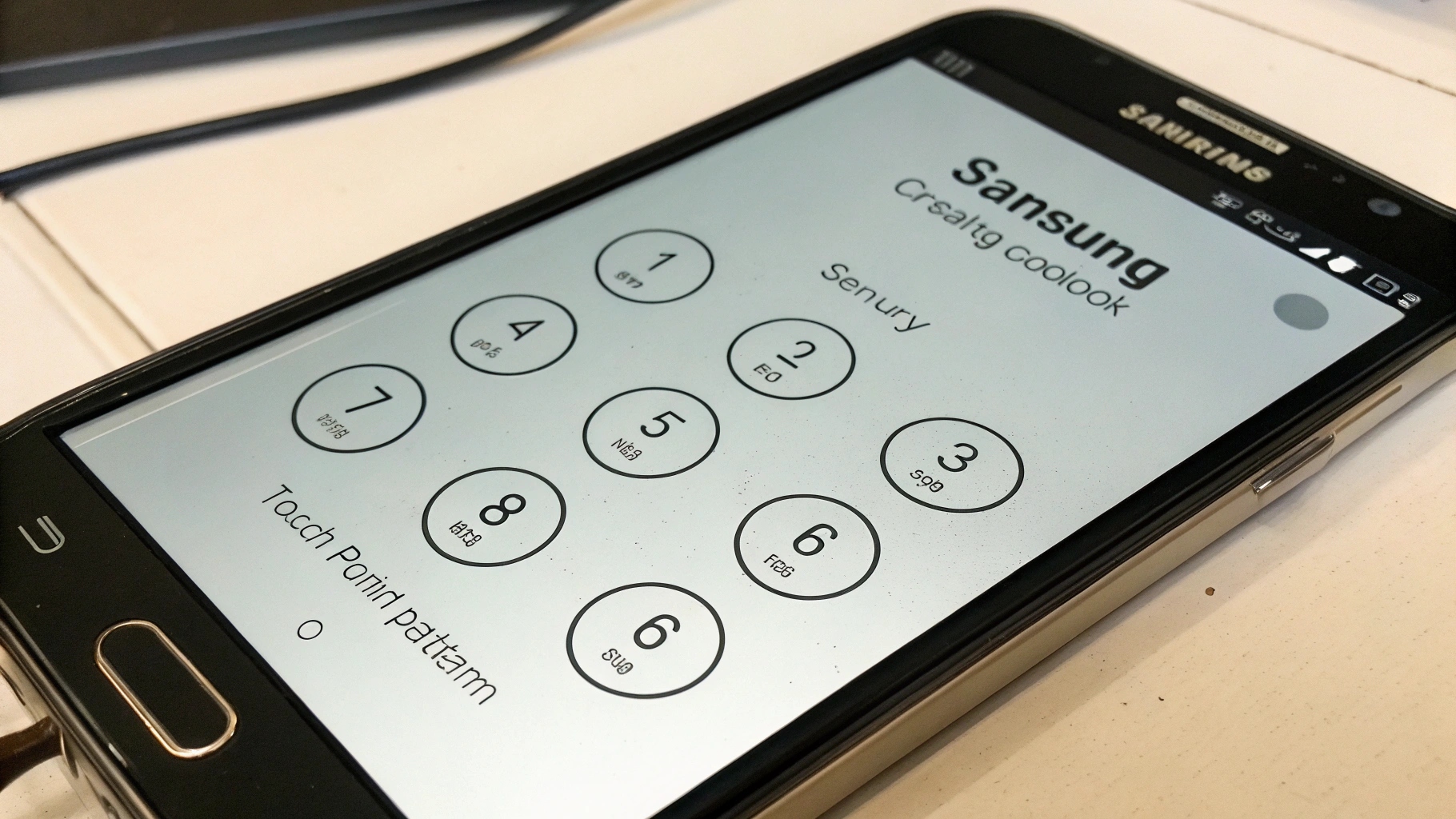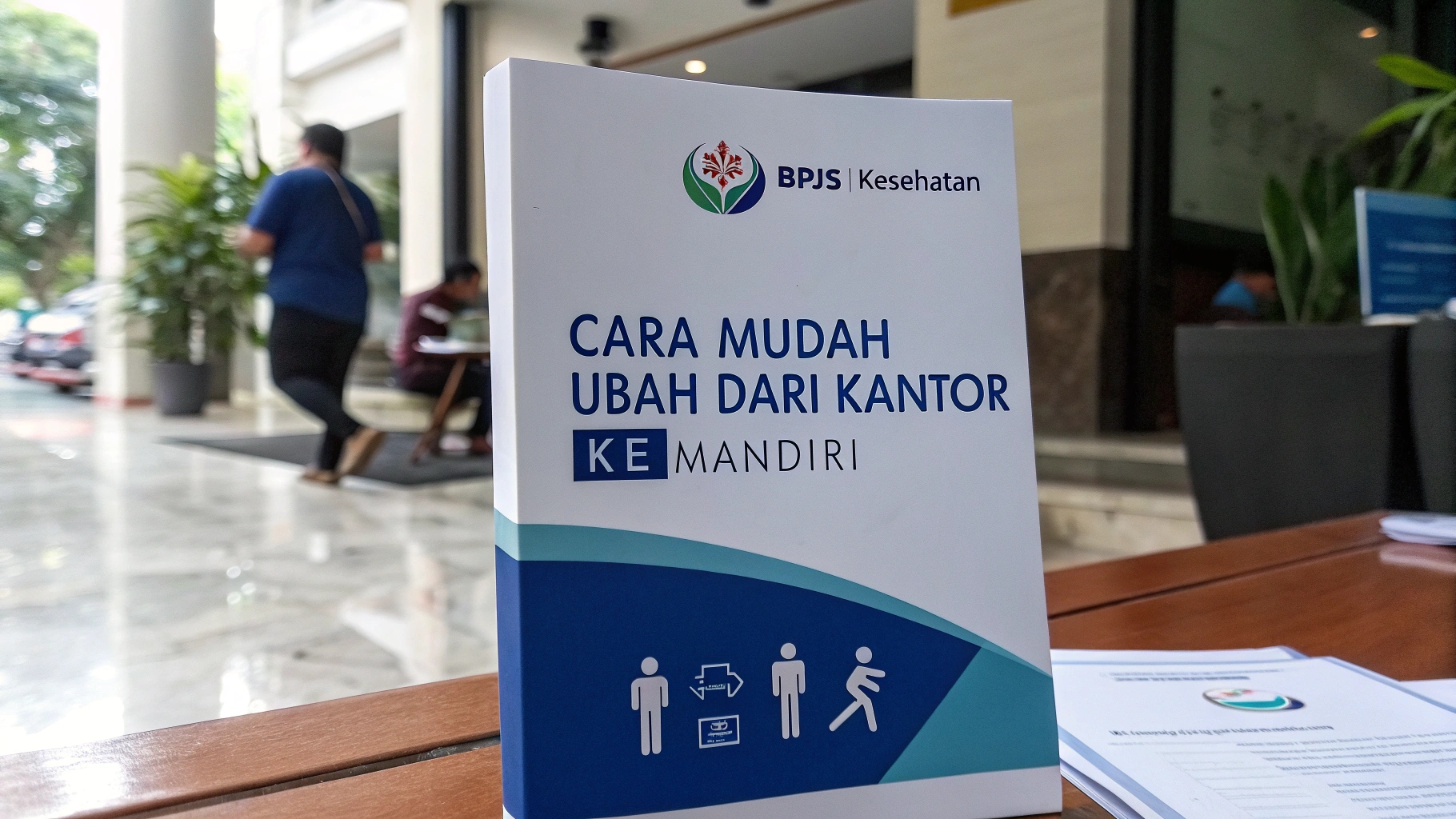(Dok. Pribadi)
(Dok. Pribadi)
SETIAP bulan Mei, kita diingatkan pada dua tonggak sejarah bangsa yang seharusnya memperkuat arah pembangunan pendidikan nasional, yaitu Hari Pendidikan Nasional pada 2 Mei dan Hari Kebangkitan Nasional pada 20 Mei. Keduanya bukan sekadar seremonial tahunan, karena di baliknya tersimpan pesan bahwa Indonesia lahir dari hasil pendidikan yang mengedepankan semangat berpikir kritis dan cita-cita luhur untuk membangun keadilan sosial.
Tanggal 2 Mei yang diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional merupakan hari lahir Ki Hadjar Dewantara, tokoh sentral pendidikan Indonesia. Dalam berbagai tulisannya, Ki Hadjar menekankan bahwa tujuan pendidikan bukan sekadar mencetak tenaga kerja, melainkan juga membentuk manusia merdeka, yakni pembelajar yang berpikir kritis, mandiri, dan memiliki kesadaran sosial (Dewantara, 1964). Pendidikan menurut beliau adalah proses memanusiakan manusia, bukan menstandarkan anak menjadi produk seragam.
Adapun 20 Mei 1908 merupakan momen berdirinya Budi Utomo, organisasi kepemudaan yang diinisiasi oleh sekelompok pemuda terdidik yang sadar bahwa penjajahan Belanda hanya bisa dilawan dengan kekuatan akal dan rasa (Putra, 2023). Para pemuda ini tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga tajam secara moral dan sosial. Kepedulian terhadap rakyat kecil, kesenjangan di masyarakat, dan masa depan bangsa adalah kenyataan yang membangkitkan mereka untuk bergerak melawan penjajahan.
Dua peristiwa di atas memiliki satu benang merah, yaitu kebangkitan nasional Indonesia dibangun oleh generasi yang berpikir kritis dan peduli pada keadilan sosial. Maka, tidak berlebihan jika kita menyimpulkan bahwa kemampuan berpikir kritis dan kesadaran sosial adalah fondasi dari Indonesia sebagai bangsa. Keduanya hanya bisa dilatih dan ditumbuhkan melalui pendidikan yang berkualitas, yakni pendidikan yang berorientasi pada keadilan sosial, bukan sekadar pencapaian akademik. Namun, pertanyaannya, apakah pendidikan kita hari ini masih setia pada fondasi tersebut? Atau, masihkah pendidikan kita hari ini mewarisi semangat para pendiri bangsa itu?
REALITAS DAN REFLEKSI
Sayangnya, jika kita jujur melihat wajah pendidikan Indonesia hari ini, yang tampak justru sebaliknya. Sistem pendidikan kita lebih sibuk menyiapkan siswa menghadapi berbagai macam tes akademik daripada menyiapkan mereka untuk berkontribusi menyelesaikan masalah-masalah sosial di sekitar mereka.
Kurikulum banyak bicara tentang pengetahuan, tetapi miskin dalam mengajarkan keberanian moral. Proses pendidikan di sekolah terasa seperti ajang pamer pencapaian akademik, bukan perjalanan menjadi manusia yang utuh. Alih-alih mendorong anak untuk bertanya, kita justru lebih banyak menuntut mereka untuk hafal. Di sekolah, alih-alih memberi ruang berpikir kritis kepada siswa, kita sering kali menjadikan mereka sebagai objek untuk memenuhi target administratif. Dalam konteks ini, pendidikan kita kian menjauh dari prinsip pendidikan perdamaian, yakni pendidikan yang bertujuan mengembangkan kapasitas manusia secara utuh sebagai manusia yang damai, tanpa kekerasan, dan bertanggung jawab untuk mewujudkan dunia yang berkeadilan sosial (Reardon, 2021).
Situasi ini diperparah oleh tantangan zaman digital yang sangat kompleks. Arus informasi yang begitu cepat tidak diimbangi dengan kemampuan literasi kritis (Najah dkk, 2024). Banyak anak dan remaja terjebak dalam dunia maya yang penuh kekerasan, hoaks, dan ujaran kebencian, tanpa pernah diajak merenung, memahami, dan memilah. Ditambah lagi, di saat mereka membutuhkan teladan, yang terlihat di ruang publik justru sering kali adalah contoh-contoh elite yang antikritik, enggan mendengar, bahkan menggunakan kuasa untuk membungkam.
Di tengah kekacauan itu, para guru di sekolah yang sering dilihat sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam pendidikan sering kali tidak diberi ruang untuk bertumbuh. Kualitas pendidik masih menjadi isu besar. Banyak guru yang belum mendapatkan pelatihan tentang pendekatan pembelajaran yang memanusiakan. Mereka masih disibukkan dengan beban administratif yang menumpuk dan ketidakpastian kesejahteraan. Bagaimana mungkin guru bisa menumbuhkan karakter yang baik, ketika mereka sendiri belum diperlakukan dengan baik?
Ketika anak dididik hanya untuk patuh dan takut salah, maka ia tidak akan tumbuh menjadi warga negara yang berani bersuara ketika ada ketimpangan. Dan ketika guru lebih dituntut untuk menuntaskan target belajar daripada memfasilitasi dialog, maka hilanglah kesempatan emas untuk menumbuhkan empati dan solidaritas.
APA YANG BISA KITA LAKUKAN?
Meskipun tantangannya besar, jalan ke depan tetap ada dan harus kita tempuh bersama. Kita bisa memulai dari ruang terdekat. Di rumah, orangtua mulai belajar berhenti mengukur anak hanya dari prestasi akademik dan lebih banyak mendengar maupun memberi ruang bagi anak untuk bertanya, menyimak, dan bersuara, bahkan ketika pendapatnya berbeda. Di sekolah, manajemen sekolah memfasilitasi guru untuk berkembang, sedangkan guru terus belajar dan berani menciptakan ruang kelas yang aman, kritis, dan penuh empati agar siswa mampu menjadi manusia yang berani berpihak kepada kebenaran dan keadilan.
Di lingkungan masyarakat, warga negara juga organisasi-organisasi di bidang terkait perlu semakin kritis bersuara melalui berbagai platform yang tersedia untuk mendorong kebijakan pendidikan yang tidak hanya fokus pada pembangunan fisik sekolah, tapi juga pembangunan nalar dan karakter.
Di sisi sebaliknya, para pemegang kekuasaan yang juga pengambil keputusan, perlu belajar mendengar lebih baik dan menerima kritik. Jangan biarkan semangat Ki Hadjar Dewantara maupun Budi Utomo hanya menjadi pesan dalam pidato seremoni.
Pendidikan yang mendorong kemampuan berpikir kritis dan membangun kepedulian pada keadilan sosial seharusnya bukanlah kemewahan. Ini bukanlah pendidikan yang hanya bisa diakses oleh mereka yang memiliki sumber daya agar bisa mengikuti pelatihan-pelatihan terkait. Ia adalah kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi jika kita ingin masa depan Indonesia dipenuhi oleh manusia-manusia yang berani, adil, dan bijak.
Dua peringatan di bulan Mei ini bukan hari nasional semata. Ia adalah pengingat bahwa kita pernah, dan seharusnya bisa lagi, membangun pendidikan yang membebaskan dan membangkitkan. Kini saatnya kita hidupkan kembali semangat itu di rumah, di sekolah, dan di ruang publik. Bukan hanya untuk kita, melainkan juga untuk generasi mendatang yang pantas hidup di Indonesia yang lebih damai dan berkeadilan sosial.