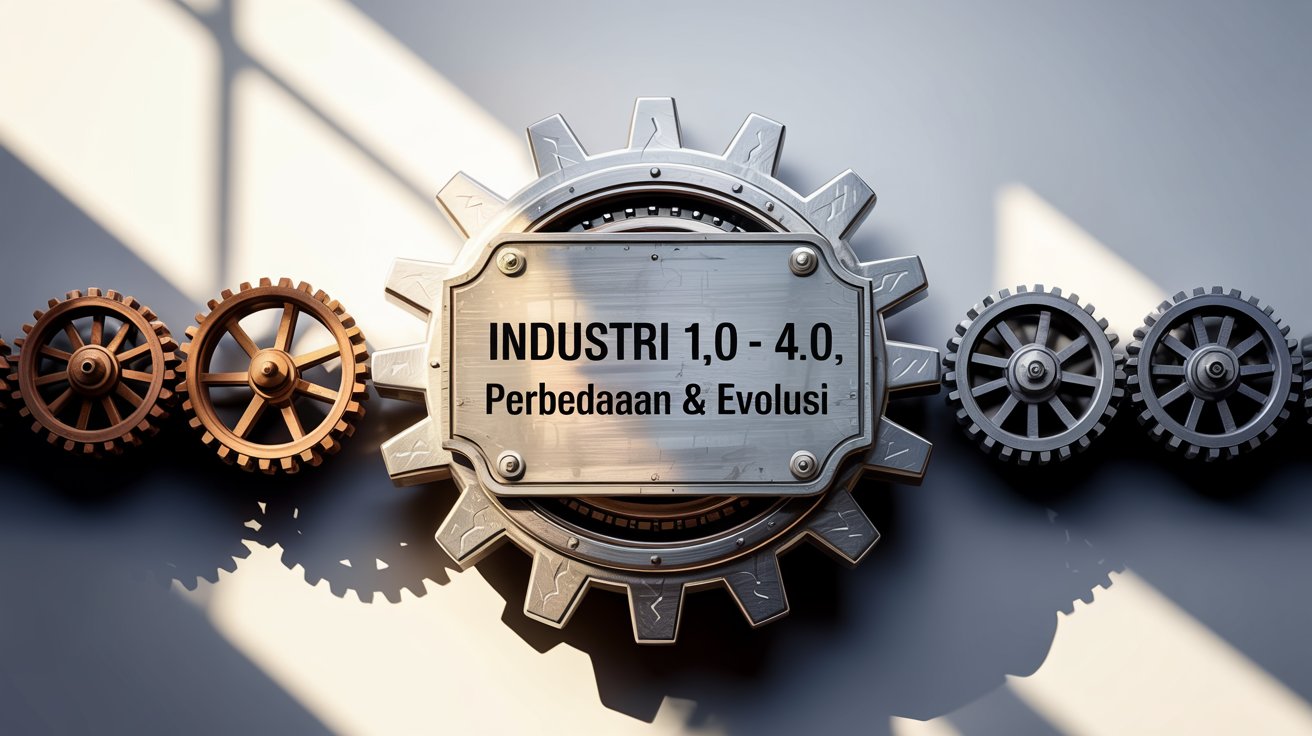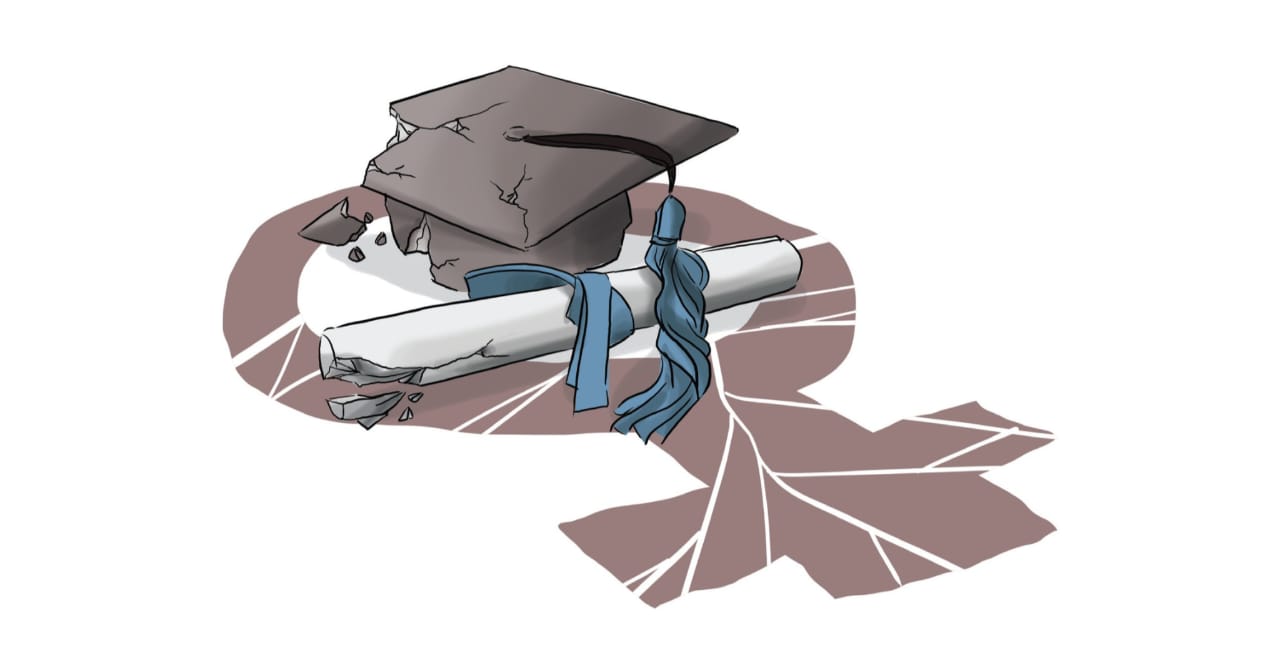 (MI/Duta)
(MI/Duta)
KAMPUS seharusnya menjadi wilayah yang steril dari tindak kekerasan seksual. Namun, hingga hari ini tindak kekerasan seksual di kampus masih saja terus terjadi. Kasus terbaru tindak kekerasan seksual kembali mencoreng nama baik Universitas Gadjah Mada (UGM). Seorang Guru Besar Fakultas Farmasi UGM, Edy Meiyanto, diduga melakukan tindak pencabulan kepada 15 mahasiswa perempuan di jenjang S-1, S-2, dan S-3 sejak 2022 hingga 2024.
Sebelumnya, di UGM juga terjadi kasus pelecehan seksual yang dilakukan dosen FISIPOL, Eric Hiariej. Setelah melalui proses panjang dan penolakan banding oleh MA, ia kemudian resmi diberhentikan sebagai dosen UGM pada November 2023. Hieriej dilaporkan seorang mahasiswi yang mengaku menjadi korban tindak pelecehan seksual saat bimbingan tugas kampus.
Kasus pelecehan seksual lain di kampus juga terjadi di Universitas Negeri Semarang, Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan sejumlah kampus lain. Biasanya saat mahasiswi melakukan bimbingan skripsi, sedang praktik di laboratorium atau di berbagai momen lain, mereka umumnya tidak berdaya ketika sang dosen melakukan tindakan pelecehan seksual. Dengan memanfaatkan kesenjangan relasi kuasa yang timpang, yang didukung rape culture, pelaku sering menempatkan mahasiswi sebagai korban yang potensial.
DOSEN CABUL
Daftar tindak pelecehan dan tindak kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus dapat terus diperpanjang. Di luar kasus yang terlaporkan melalui jalur hukum, masih banyak kasus lain yang terpendam karena ketidakberanian korban melaporkan peristiwa yang dialami mereka.
Studi yang dilakukan penulis (2024) berjudul Tindak Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus menemukan bahwa selama ini tidak sedikit mahasiswi yang menjadi korban tindak pelecehan seksual. Menurut 300 mahasiswi yang pernah menjadi korban tindak kekerasan seksual di kampus, status pelaku tindak pelecehan seksual sebagian besar (39,7%) ialah teman kuliah sendiri yang satu angkatan.
Sementara itu, sebanyak 31,3% responden mengaku pelaku tindak pelecehan seksual ialah teman kuliah, tetapi beda angkatan. Biasanya kakak kelas sering kali menjadi pelaku TPKS. Mereka umumnya memanfaatkan momen ospek atau perpeloncoan menjadi kesempatan untuk melakukan perundungan--yang tak jarang menjurus pada kekerasan seksual.
Data yang menarik, dari 300 responden, sebanyak 9,7% mengaku pelaku tindak kekerasan seksual ialah dosen atau asisten dosen. Sementara itu, sebanyak 19,3% responden mengaku pelaku tindak pelecehan seksual ialah tenaga kependidikan, office boy, sekuriti, dan pekerja bangunan yang kebetulan mengerjakan proyek di lingkungan kampus.
Di sini, meski tidak besar, 9,7% dosen dan asisten dosen yang menjadi pelaku tindak kekerasan seksual tentu sangat memprihatinkan. Dosen dan asisten dosen, dalam posisinya yang asimetris, memang sering membuat mahasiswa tidak bisa berbuat apa-apa ketika dosen dan asisten dosen melakukan hal-hal yang sebetulnya tidak mereka sukai.
Berdasarkan pengalaman, kasus-kasus kekerasan terhadap mahasiswi yang dilakukan dosen sering kali melibatkan lebih dari satu korban. Namun, hanya sedikit korban yang berani melapor karena posisi kuasa yang tidak imbang antara korban dan pelaku. Dengan otoritas yang dimiliki, dosen-dosen cabul itu biasanya akan lebih leluasa untuk menekan secara halus mahasiswi bimbingan mereka, baik secara verbal maupun fisik.
Ancaman akan memberi nilai yang jelek bagi korban yang menolak atau konteks relasi yang asimestris sering kali menjadi ruang sosial yang memungkinkan dosen memiliki peluang membuat korban tidak berdaya.
Data yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan melaporkan sepanjang 2015 hingga 2020, dari keseluruhan pengaduan tindak kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, sebanyak 27 di antaranya terjadi di lingkungan kampus. Bahkan, survei yang dilakukan Koalisi Ruang Publik Aman menunjukkan bahwa sekolah atau kampus ternyata menduduki urutan ketiga sebagai lokasi terbanyak terjadinya kekerasan seksual. Artinya, jauh dari kesan bahwa kampus ialah ruang yang aman bagi para mahasiswa, ternyata hantu tindak kekerasan seksual merupakan ancaman yang serius dan membutuhkan pemecahan segera.
Sebuah studi yang dilakukan National Union of Students (NUS) di Inggris menunjukkan bahwa satu dari tujuh mahasiswa perempuan mengalami pelecehan atau kekerasan seksual selama masa kuliah mereka (NUS, 2018). Di Amerika Serikat, studi yang dilakukan oleh National Institute of Justice menunjukkan bahwa 19% dari mahasiswa perempuan mengalami kekerasan seksual selama masa kuliah mereka (Krebs et al, 2007).
Studi lain yang dilakukan American Association of Universities menunjukkan sebanyak 23% dari mahasiswa perempuan dan 5% dari mahasiswa laki-laki melaporkan bahwa mereka telah mengalami pelecehan seksual atau percobaan pemerkosaan selama masa kuliah mereka (Cantor et al, 2015). Sementara itu, studi yang dilakukan National Institute of Justice menunjukkan bahwa 5,2% dari mahasiswa perempuan mengalami pemerkosaan atau percobaan pemerkosaan selama masa kuliah mereka (Fisher et al, 2000).
Kekerasan seksual di perguruan tinggi bukan sekadar sebuah masalah individu yang disebabkan hasrat mesum atau nafsu pelaku, melainkan juga memiliki kaitan dengan relasi kuasa. Sebuah studi yang dilakukan Foubert (2014) menunjukkan bahwa tindakan kekerasan seksual terjadi karena adanya perbedaan kekuatan antara pelaku dan korban. Bias gender yang melekat dalam masyarakat juga menjadi faktor penting dalam memengaruhi terjadinya kekerasan seksual di perguruan tinggi. Studi Choate (2019) menunjukkan bahwa tindakan kekerasan seksual terjadi ketika para pelaku menggunakan kekuasaan mereka untuk memaksa korban melakukan tindakan seksual yang tidak diinginkan.
SOFTIFIKASI
Tindak kekerasan seksual di PT dewasa ini diakui atau tidak sudah menjadi situasi darurat yang benar-benar mendesak untuk segera ditangani. Meski sudah ada berbagai upaya dan ancaman hukuman juga telah diperberat untuk membuat pelaku tindak kekerasan seksual jera, dari waktu ke waktu, kasus ini tetap saja terjadi di berbagai PT.
Upaya menangani kasus kekerasan seksual di kampus, diakui atau tidak, membutuhkan kepedulian dan komitmen yang tinggi. Selama ini ada kesan perbincangan tentang tindak kekerasan seksual telah mengalami proses softifikasi. Masyarakat menjadi makin terbiasa dan karena itu sepertinya mahfum ketika membaca berita tentang tindak kekerasan seksual. Alih-alih bersikap empatif dan peduli terhadap nasib korban tindak kekerasan seksual, yang terjadi di lapangan ialah sikap pembiaran dan bahkan cenderung menyalahkan korban. Mahasiswi yang menjadi korban tindak kekerasan seksual tidak jarang dituduh kurang mampu menjaga diri dan bahkan dituduh ikut menikmati serta berperan mengundang terjadinya tindak kekerasan seksual yang dialaminya.
Tidak sedikit warga masyarakat yang masih meyakini bahwa tindak kekerasan seksual terjadi karena semakin banyak perempuan atau dalam hal ini mahasiswi yang berani berpakaian mini dan ketat serta dengan sengaja menonjolkan keindahan tubuhnya. Sementara itu, ada pula yang mengatakan bahwa tindak kekerasan seksual terjadi karena adanya faktor N (niat) dan K (kesempatan). Artinya, tidak sekadar kekhilafan dan motif bejat pelaku, tindak kekerasan seksual juga diyakini terjadi karena adanya kesempatan yang memungkinkan dan menstimulasi peristiwa itu terjadi.